Oleh : dwi astriani Nim: 2501041030
PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN. FAKULTAS ILMU KESEHATAN. UNIVERSITAS DHARMAS INDONESIA TAHUN 2026
Dosen Pengampu : Dr. Amar Salahuddin, M.Pd
Kebidanan sering dipahami sebagai profesi yang paling dekat dengan perempuan, khususnya dalam pengalaman paling intim dalam hidup mereka: kehamilan, persalinan, dan nifas.
Namun, di balik citra lembut dan penuh empati itu, praktik kebidanan hari ini tidak sepenuhnya bebas dari persoalan besar yakni semakin berkurangnya ruang bagi suara tubuh dan pengalaman subjektif perempuan itu sendiri.
Dalam sistem kesehatan modern yang semakin terstandarisasi, tubuh perempuan kerap diperlakukan sebagai “objek klinis” yang harus patuh pada grafik, angka, dan prosedur.
Dalam banyak ruang bersalin, perempuan datang dengan harapan melahirkan dengan aman dan bermartabat.
Namun realitasnya, tidak sedikit yang pulang dengan perasaan tidak didengar, bahkan trauma. Keputusan sering diambil cepat atas nama efisiensi dan protokol, sementara rasa, ketakutan, dan intuisi ibu dianggap sekunder.
Di titik inilah kebidanan menghadapi paradoks: profesi yang seharusnya membela perempuan justru berisiko menjadi perpanjangan tangan sistem yang menyingkirkan suara mereka.
Bidan berada di posisi yang unik dan dilematis. Di satu sisi, mereka terikat pada regulasi medis, standar operasional, serta hierarki kesehatan.
Di sisi lain, bidan dibekali nilai filosofis tentang kemitraan, penghormatan terhadap proses alami, dan pemberdayaan perempuan. Ketegangan antara dua kutub inilah yang sering tidak dibicarakan secara jujur dalam pendidikan maupun praktik kebidanan.
Persalinan bukan sekadar peristiwa biologis, melainkan pengalaman eksistensial. Cara seorang perempuan melahirkan dapat memengaruhi rasa percaya dirinya, relasinya dengan tubuh, bahkan kesehatan mentalnya.
Ketika proses ini dipercepat tanpa penjelasan yang memadai, atau ketika keputusan dibuat tanpa persetujuan yang sungguh-sungguh dipahami, maka yang terluka bukan hanya tubuh, tetapi juga martabat.
Opini ini tidak dimaksudkan untuk menolak kemajuan medis. Intervensi menyelamatkan nyawa, dan data adalah alat penting.
Namun masalah muncul ketika data menjadi lebih “didengar” daripada manusia.
Grafik partograf bisa menunjukkan kemajuan persalinan, tetapi tidak bisa membaca ketakutan atau kesiapan batin seorang ibu.
Di sinilah kebidanan seharusnya berdiri: menjembatani ilmu dan rasa, sains dan nurani.
Bidan sejatinya bukan hanya pelaksana tindakan, tetapi penjaga makna kelahiran.
Peran ini menuntut keberanian moral berani menyuarakan kepentingan perempuan, berani memperlambat ketika sistem ingin mempercepat, dan berani bersikap reflektif terhadap kekuasaan yang melekat pada jas putih dan otoritas medis.
Kebidanan yang kehilangan refleksi kritis berisiko berubah menjadi sekadar pekerjaan teknis, bukan lagi panggilan kemanusiaan.
Pendidikan kebidanan pun perlu dievaluasi. Apakah mahasiswa bidan cukup dilatih untuk berpikir kritis dan etis, atau justru dibentuk menjadi tenaga patuh pada prosedur tanpa mempertanyakan konteks?
Mahasiswa perlu diperkenalkan pada realitas sosial, gender, dan hak reproduksi, bukan hanya anatomi dan farmakologi.
Tanpa itu, bidan masa depan akan kesulitan membela perempuan dalam sistem yang kompleks.
Pada akhirnya, kebidanan yang manusiawi adalah kebidanan yang bersedia mendengar bukan hanya denyut jantung janin, tetapi juga suara pelan perempuan yang sedang berjuang melahirkan.
Dalam dunia kesehatan yang semakin cepat dan mekanistik, mendengar adalah bentuk perlawanan paling sederhana sekaligus paling radikal.
Jika kebidanan ingin tetap relevan dan bermartabat, ia harus kembali pada akarnya: menjaga kehidupan dengan menghormati manusia secara utuh.
Sebab kelahiran bukan hanya soal siapa yang lahir, tetapi juga bagaimana seorang perempuan diperlakukan saat melahirkan.












.jpg)





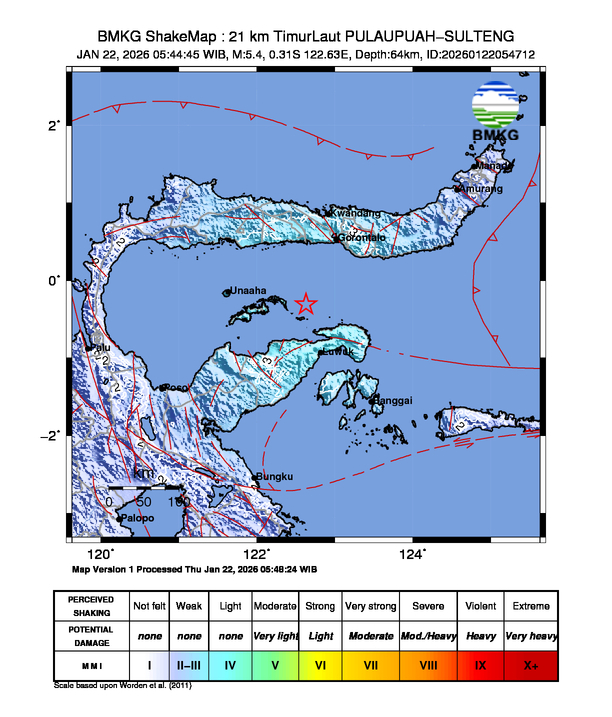
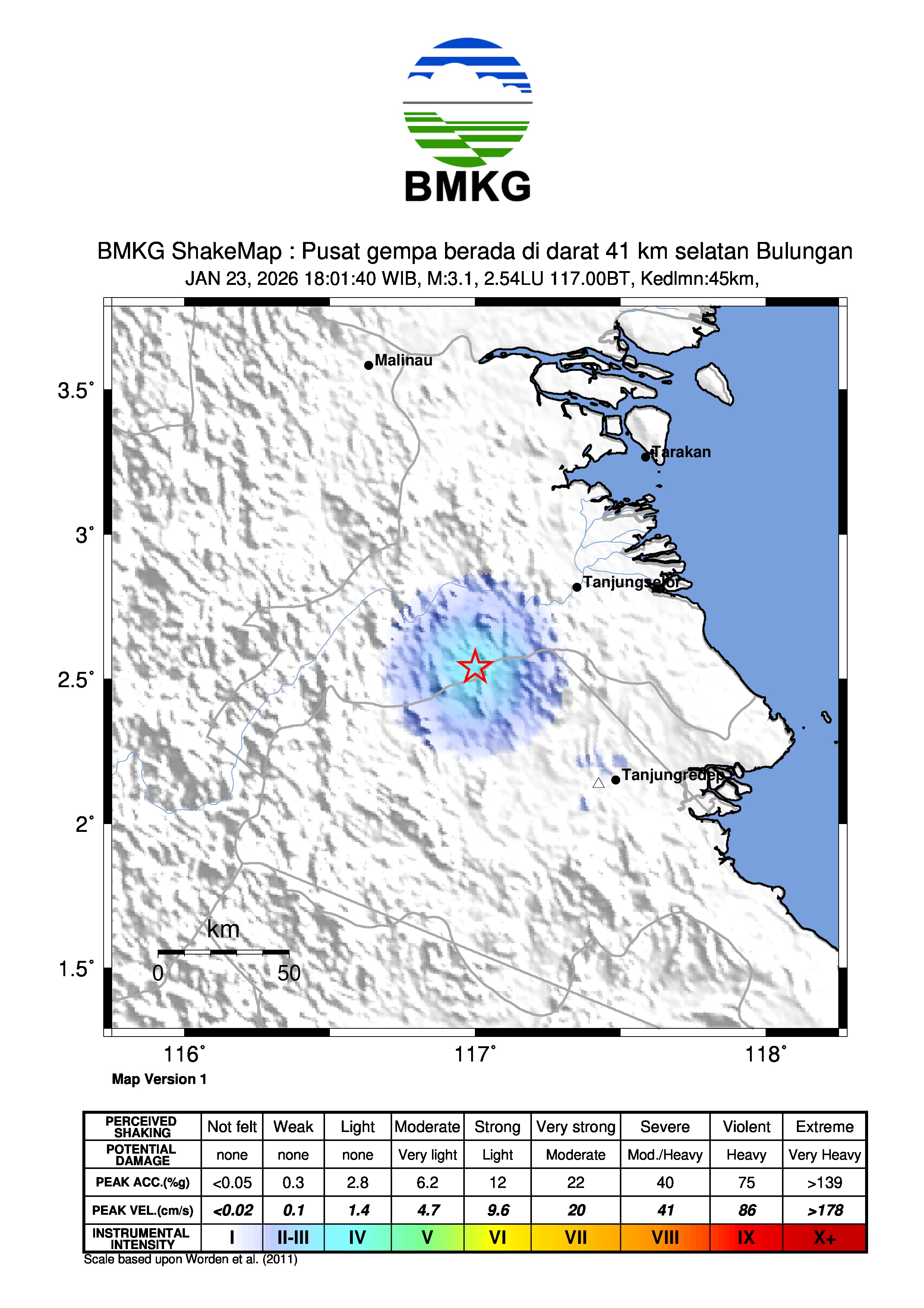






No comments:
Post a Comment