Oleh: Siti Permata Yuliyandi Mahasiswa Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas
Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatera, khususnya Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada akhir November hingga Desember 2025, telah menewaskan ratusan jiwa dan meninggalkan luka mendalam bagi ribuan warga yang kehilangan tempat tinggal, harta benda, dan sanak saudara. Di tengah tangis dan derita korban bencana, muncul fenomena yang tidak kalah memprihatinkan: serangkaian pernyataan dan tindakan pejabat publik yang justru memantik kontroversi dan menuai kecaman luas dari masyarakat.
Dari pernyataan Kepala BNPB yang menyebut situasi mencekam "hanya ramai di media sosial", Bupati Aceh Tenggara yang mengusulkan Presiden menjabat seumur hidup di tengah penderitaan warga, anggota DPRD yang malah studi banding ke Yogyakarta saat daerahnya terisolasi, hingga pejabat yang membuat konten vlog 'A Day In My Life' di lokasi bencana semua ini mencerminkan krisis empati dan profesionalisme dalam penanganan bencana nasional.
Presiden Prabowo Subianto sendiri harus turun tangan mengingatkan para pejabat untuk tidak menjadikan bencana sebagai ajang pencitraan. "Saya mohon jangan pejabat-pejabat, tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir," tegasnya dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 15 Desember 2025. Peringatan ini seharusnya tidak perlu disampaikan jika para wakil rakyat memahami esensi kepemimpinan dan tanggung jawab mereka terhadap rakyat yang menderita.
Kapabilitas Simbolik dan Krisis Empati
Konsep Kapabilitas Simbolik dalam Sistem Politik
Kapabilitas simbolik adalah kemampuan sistem politik dalam memberikan makna atau pengertian dari sebuah sistem politik kepada lingkungan di dalam masyarakat maupun di luar masyarakat. Dalam konteks penanggulangan bencana, kapabilitas simbolik pejabat publik tercermin dari kemampuan mereka menyampaikan pesan kehadiran negara, empati, dan keseriusan dalam menangani krisis kemanusiaan.
Efektivitas mengalirnya simbol dari sistem politik terhadap lingkungan masyarakat menentukan tingkat kemampuan simbolik ini, dimana faktor karisma seorang pemimpin dan latar belakang sosial pejabat politik dapat memberikan keuntungan tersendiri. Namun, apa yang terjadi di Sumatera justru menunjukkan kegagalan kapabilitas simbolik ini simbol yang dihasilkan pejabat tidak lagi dipersepsikan sebagai empati atau kepemimpinan, melainkan sebagai pencitraan dan eksploitasi penderitaan rakyat.
Dalam kondisi bencana, setiap tindakan pejabat tidak pernah berdiri sendiri. Kehadiran mereka selalu berada dalam dua ruang,ruang nyata di mana warga berjuang menghadapi musibah, dan ruang digital tempat setiap detik dapat menjadi sorotan. Dilema ini seharusnya mendorong pejabat untuk bertindak lebih autentik, namun yang terjadi justru sebaliknya mereka terjebak dalam logika pencitraan yang kontraproduktif.
Fernando EMaS, Direktur Rumah Politik Indonesia, menilai bahwa derasnya kritik terhadap pejabat publik muncul akibat meningkatnya apatisme masyarakat terhadap perilaku para pemimpin yang dianggap tidak mencerminkan empati yang tulus. Publik kini memiliki kepekaan tinggi untuk membedakan mana tindakan yang benar-benar ditujukan untuk membantu korban, dan mana yang sekadar untuk konten media sosial.
Tindakan pejabat yang lebih mengutamakan pencitraan daripada penyelesaian masalah mengakibatkan erosi kepercayaan publik terhadap institusi negara. Momen bencana yang mestinya menjadi ruang empati justru kerap dijadikan panggung politik, membuat masyarakat semakin sinis terhadap pejabat negara.
Ketika rakyat tidak lagi percaya bahwa pejabat hadir untuk membantu mereka secara tulus, maka legitimasi politik dan sosial pemerintah akan terus terkikis. Dalam jangka panjang, ini dapat mengancam stabilitas demokrasi karena masyarakat kehilangan kepercayaan pada sistem. Pencitraan pejabat di lokasi bencana juga mengalihkan fokus dari persoalan struktural yang sebenarnya harus diselesaikan. Alih-alih fokus pada pencegahan illegal logging, perbaikan sistem peringatan dini, dan penguatan infrastruktur mitigasi bencana, energi publik justru tersedot untuk mengkritik tingkah laku pejabat yang tidak pada tempatnya.
Kekuasaan menjaga stabilitas simbolik dan arus keuntungan, sementara risiko dialihkan kepada mereka yang tak punya daya tawar ini bukan kelalaian, ini keputusan. Ketika pejabat lebih sibuk mengurus citra daripada menyelesaikan akar masalah, bencana berikutnya hanya tinggal menunggu waktu.
Fenomena pencitraan pejabat di tengah bencana Sumatera mencerminkan krisis mendalam dalam kapabilitas simbolik sistem politik Indonesia. Kapabilitas simbolik, yang seharusnya menjadi instrumen untuk membangun kepercayaan dan memperkuat legitimasi pemerintah, justru mengalami degradasi akibat tindakan pejabat yang lebih mengutamakan kepentingan citra politik pribadi daripada penanganan nyata terhadap penderitaan rakyat.
Dari konsep teoritis, kapabilitas simbolik mensyaratkan adanya keselarasan antara simbol yang ditampilkan dengan makna yang diterima masyarakat. Namun yang terjadi adalah diskoneksi masif: pejabat menampilkan simbol "kepedulian" melalui foto menggotong beras atau membersihkan lumpur, tetapi masyarakat membaca simbol tersebut sebagai "pencitraan" dan "eksploitasi bencana". Ketika output simbolik tidak lagi efektif, bahkan kontraproduktif, maka kepercayaan publik terhadap sistem politik pun ikut merosot.
Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan peringatan tegas agar pejabat tidak menjadikan bencana sebagai ajang wisata pencitraan. Namun peringatan saja tidak cukup.
Diperlukan perubahan mendasar dalam kultur birokrasi dan politik Indonesia agar empati sejati, bukan sekadar aksi simbolik kosong, yang menjadi landasan dalam penanganan bencana.












.jpg)





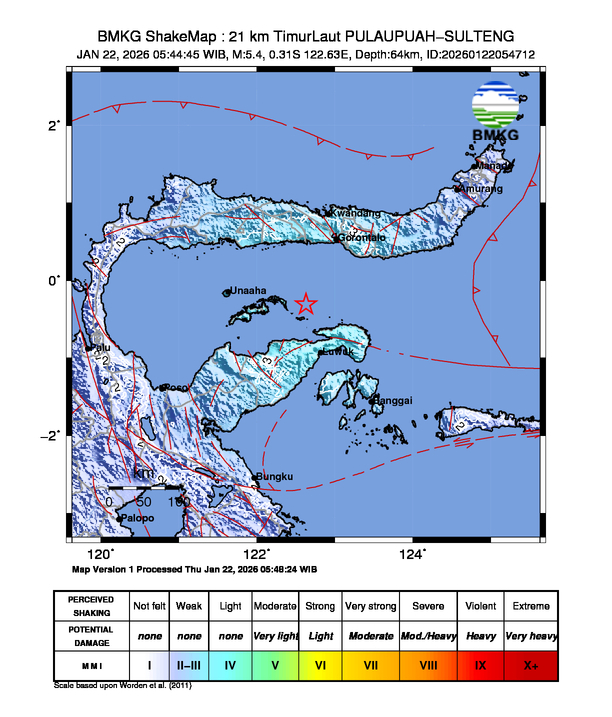
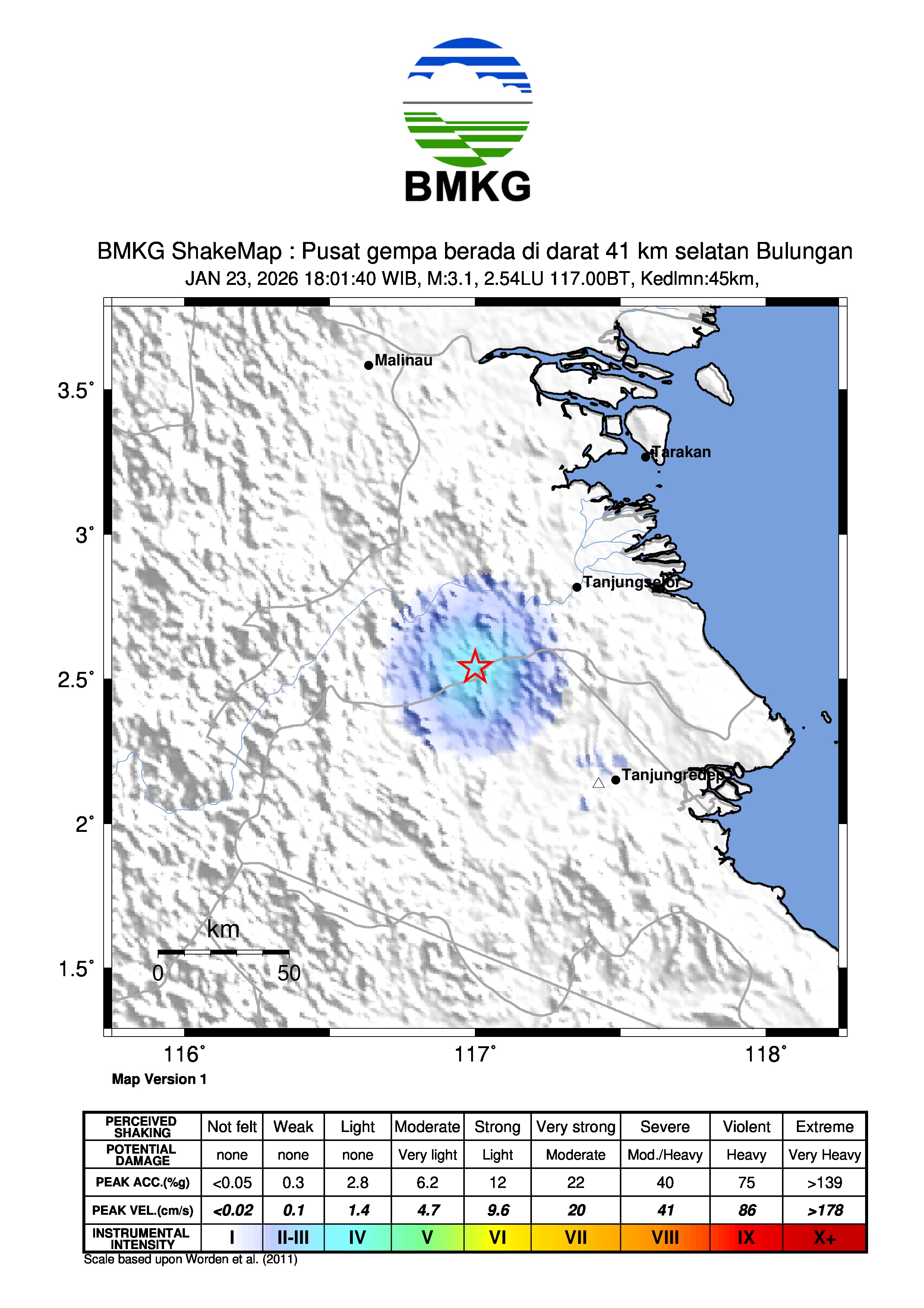






No comments:
Post a Comment