Penulis:Elmida Yani D Mahasiswa Jurusan Biologi, Universitas Andalas, Padang. Email: elmidayanny21@gmail.com
Bagi banyak warga di Pulau Sumatera, musim hujan bukan lagi sekadar perubahan cuaca. Hal ini datang bersama kekhawatiran akan banjir, longsor, dan akses hidup yang terputus. Jalan yang amblas, sawah yang terendam, serta permukiman yang harus dievakuasi menjadi pemandangan yang berulang dari tahun ke tahun. Situasi ini perlahan terasa seperti rutinitas, seolah bencana adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Namun, benarkah semua ini murni musibah alam? Pertanyaan ini penting diajukan ketika pola bencana terus berulang di lokasi yang relatif sama. Jika hujan deras selalu berujung banjir, dan lereng selalu longsor setiap musim penghujan, maka ada persoalan yang lebih dalam dari sekadar cuaca ekstrem.
Dalam berbagai kajian lingkungan, bencana jarang dipandang sebagai peristiwa tunggal. Ia merupakan akumulasi dari proses panjang yang melibatkan perubahan bentang alam. Sumatera, dengan kekayaan hutan, pegunungan, sungai, dan lahan basahnya, sejatinya memiliki sistem perlindungan alami yang kuat. Sistem ini bekerja menjaga keseimbangan air, tanah, dan kehidupan manusia. Hutan hujan tropis di Sumatera berperan penting dalam menyerap air hujan dan menahan tanah. Akar-akar pohon memperkuat struktur tanah, sementara tajuk hutan memperlambat jatuhnya air ke permukaan. Ketika hutan masih utuh, hujan deras jarang berubah menjadi bencana. Air diserap dan dialirkan secara perlahan ke sungai.
Masalah muncul ketika tutupan hutan berkurang drastis. Fragmentasi hutan, alih fungsi lahan, dan degradasi kawasan lindung membuat fungsi ekologis tersebut melemah. Air hujan yang dulu tertahan kini mengalir deras membawa lumpur, menutup sungai, dan merendam wilayah hilir. Dalam konteks ini, banjir bukan lagi peristiwa alamiah, melainkan konsekuensi dari rusaknya sistem penyangga kehidupan.
Hal serupa terjadi pada ekosistem gambut yang banyak tersebar di Sumatera. Gambut adalah penyimpan air dan karbon yang sangat efektif. Ia bekerja seperti spons raksasa yang menjaga keseimbangan hidrologi. Namun ketika gambut dikeringkan, daya serapnya hilang. Di musim kemarau, ia mudah terbakar dan memicu kabut asap. Di musim hujan, air tidak lagi tertahan, sehingga banjir menjadi ancaman serius. Di sinilah persoalan lingkungan bertemu dengan kebijakan. Dalam perspektif ekologi politik, kerusakan alam tidak bisa dilepaskan dari keputusan tata kelola. Tata ruang yang longgar, perizinan yang mengabaikan daya dukung lingkungan, serta lemahnya pengawasan mempercepat degradasi ekosistem. Alam akhirnya menanggung beban dari pilihan-pilihan tersebut, dan masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak.
Sering kali, kawasan dengan nilai ekologis tinggi justru dipandang sebagai ruang kosong yang siap dimanfaatkan. Hutan dan lahan basah dilihat dari potensi ekonominya, bukan dari fungsi perlindungannya. Konservasi kerap dianggap penghambat pembangunan, padahal dalam biologi konservasi, menjaga ekosistem adalah bentuk investasi jangka panjang untuk keselamatan manusia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa biaya menjaga lingkungan jauh lebih kecil dibanding biaya menanggulangi bencana. Pemulihan infrastruktur, bantuan sosial, dan kerugian ekonomi pascabencana menyedot anggaran besar. Sebaliknya, ekosistem yang sehat bekerja sebagai infrastruktur alami yang melindungi manusia tanpa perlu proyek mahal.
Sayangnya, pendekatan penanganan bencana di Sumatera masih cenderung reaktif. Fokus sering tertuju pada bantuan setelah kejadian, sementara upaya pencegahan belum mendapat porsi yang seimbang. Padahal, perlindungan hutan, pemulihan daerah aliran sungai, dan restorasi gambut adalah langkah mitigasi paling efektif. Bencana yang terus berulang seharusnya dibaca sebagai pesan ekologis. Alam memberi sinyal bahwa daya dukung lingkungan telah melemah. Jika pesan ini diabaikan, intensitas dan skala bencana akan meningkat. Dalam jangka panjang, bukan hanya lingkungan yang rusak, tetapi juga ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. Untuk selanjutnya, Sumatera membutuhkan perubahan cara pandang dalam pembangunan. Konservasi tidak boleh lagi ditempatkan sebagai proyek tambahan atau kewajiban administratif. Ia harus menjadi fondasi perencanaan. Pendekatan berbasis lanskap yang melihat hutan, sungai, lahan pertanian, dan permukiman sebagai satu kesatuan perlu diperkuat agar keseimbangan ekologis tetap terjaga.
Peran masyarakat lokal juga sangat penting. Banyak wilayah yang masih memiliki kearifan dalam mengelola alam secara lestari. Melibatkan masyarakat bukan hanya soal partisipasi, tetapi juga pengakuan bahwa mereka adalah penjaga pertama ekosistem. Pengalaman menunjukkan bahwa kawasan yang dikelola bersama masyarakat cenderung lebih tahan terhadap tekanan lingkungan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola lingkungan perlu diperkuat. Kebijakan pembangunan seharusnya membuka ruang bagi pertimbangan ilmiah dan suara publik. Tanpa itu, kerusakan akan terus berulang, dan bencana akan tetap menjadi berita musiman.
Bencana di Pulau Sumatera seharusnya menjadi ruang refleksi bersama, bukan sekadar rutinitas tahunan. Alam telah berkali-kali memberi peringatan tentang cara kita mengelolanya. Menjawab peringatan itu dengan konservasi bukan pilihan idealistis, melainkan kebutuhan mendesak.
Sumatera tidak kekurangan sumber daya alam, tetapi berisiko kehilangan daya dukung lingkungannya jika tata kelola terus diabaikan. Melindungi hutan, gambut, dan sungai berarti melindungi ruang hidup manusia. Jika ingin keluar dari lingkaran bencana, keberanian untuk berpihak pada alam harus dimulai sekarang.
LAMPIRAN












.jpg)





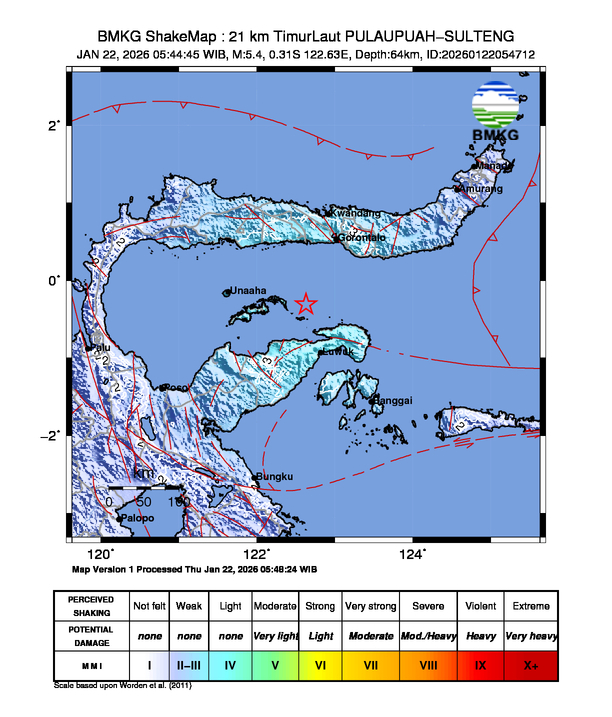
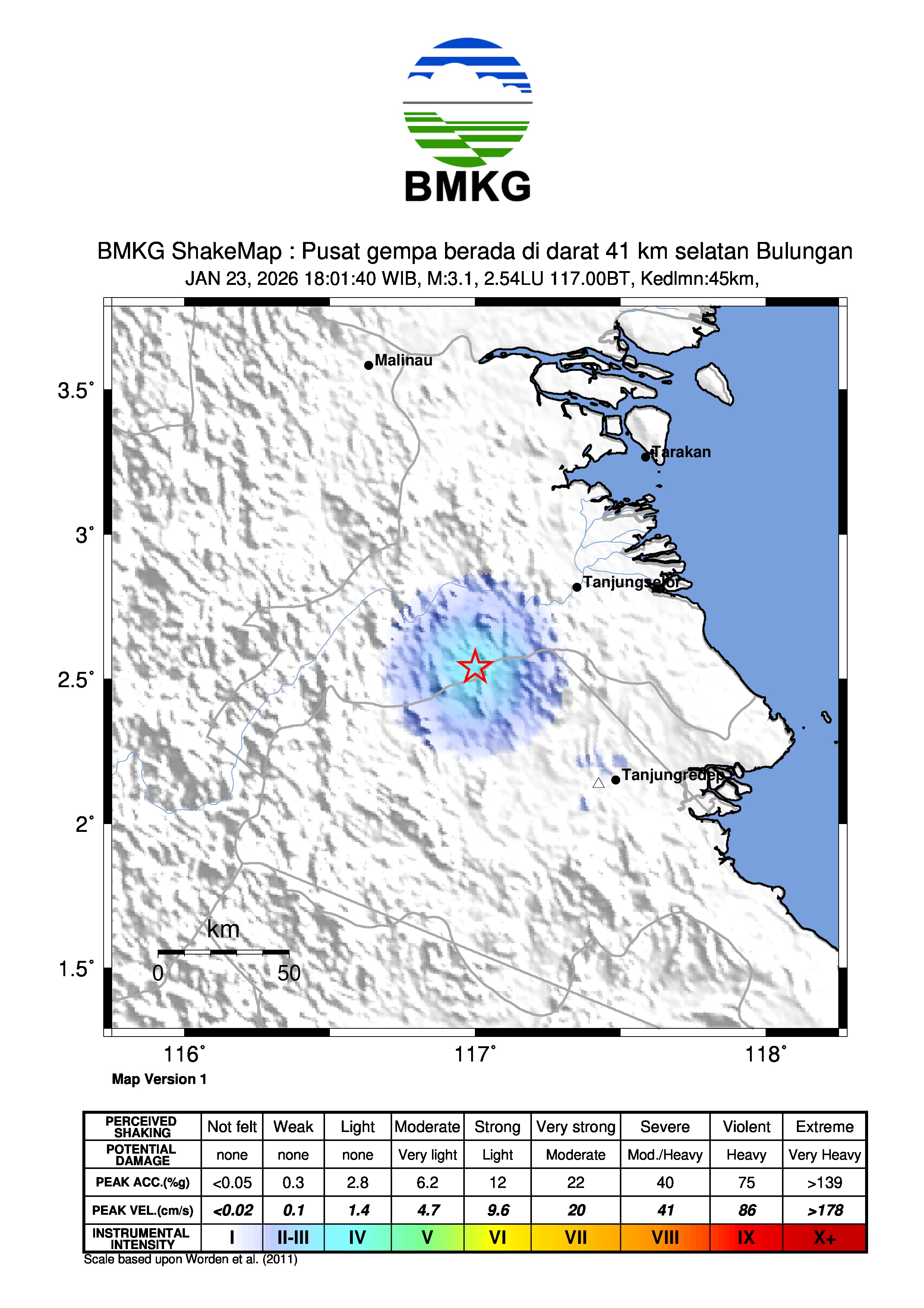






No comments:
Post a Comment