Oleh: Auvhi Delilla Syahri Mahasiswa Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas
Kalau bicara soal kapabilitas regulatif penanggulangan bencana di Indonesia, kesan pertama yang muncul sebenarnya cukup meyakinkan. Negara sudah menyiapkan kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, lengkap dengan pembentukan BNPB di tingkat pusat dan BPBD di daerah. Secara normatif, negara terlihat hadir, sadar akan risiko, dan seolah siap menghadapi ancaman bencana yang hampir selalu mengintai. Namun, kesan tersebut mulai retak ketika regulasi diuji dalam situasi nyata.
Masalah paling mendasar bukan terletak pada kekosongan hukum, melainkan pada jarak antara aturan dan keberanian untuk menegakkannya. Regulasi sering kali berhenti sebagai pedoman administratif, bukan alat kontrol yang benar-benar memaksa perubahan perilaku para aktor, terutama di tingkat lokal. Padahal, Indonesia berada dalam kondisi kerentanan ekstrem. World Risk Report 2023 menempatkan Indonesia di peringkat kedua negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia, dan sekitar 96 persen penduduknya hidup di wilayah rawan bencana. Angka-angka ini seharusnya cukup untuk membuat regulasi bersifat keras, tegas, dan tidak mudah ditawar oleh kepentingan lain.
Ironisnya, dalam praktik, regulasi justru sering kalah oleh logika pembangunan jangka pendek. Penataan ruang, pengelolaan lingkungan, dan izin pemanfaatan lahan kerap berjalan seolah risiko bencana adalah urusan nanti, bukan konsekuensi langsung dari kebijakan hari ini. Negara sebenarnya telah mencoba merapikan basis kebijakan melalui Peraturan BNPB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Indonesia One Disaster Data, yang bertujuan menyatukan dan memperkuat data kebencanaan nasional. Namun, data yang lengkap tidak otomatis menjadi keputusan yang berani. Peta risiko bisa saja akurat, tetapi tetap dikesampingkan ketika berhadapan dengan tekanan ekonomi dan politik lokal.
Keterbatasan ini terlihat jelas dalam kasus banjir dan longsor di Sumatra Barat. Wilayah ini secara geografis berada di kawasan rawan, dengan curah hujan tinggi dan kondisi topografi yang sensitif. Risiko tersebut bukan hal baru dan telah lama tercatat dalam berbagai dokumen perencanaan. Namun, alih fungsi lahan, lemahnya pengawasan tata ruang, serta aktivitas pembangunan di kawasan rentan tetap berlangsung. Ketika banjir dan longsor kembali terjadi dan menelan korban jiwa, situasi tersebut memperlihatkan bahwa regulasi gagal berfungsi sebagai alat pencegah.
Negara hadir setelah bencana terjadi, bukan ketika risiko mulai dibangun secara perlahan.
Relasi pusat dan daerah turut memperlihatkan batas kapabilitas regulatif ini.
Pemerintah pusat cenderung berhati-hati dalam menetapkan status bencana nasional, sementara pemerintah daerah sering dipaksa menjadi garda terdepan meskipun kapasitasnya tidak selalu memadai.
Akibatnya, respons awal terhadap bencana di Sumatra Barat berjalan dalam kondisi timpang: kebutuhan di lapangan mendesak, sementara dukungan struktural bergerak lebih lambat.
Ketika peristiwa banjir dan longsor besar pada tahun 2025 tetap menimbulkan korban dalam jumlah signifikan, hal itu menunjukkan bahwa mekanisme regulatif belum cukup adaptif terhadap eskalasi risiko yang cepat dan kompleks.
Pada akhirnya, persoalan penanggulangan bencana di Indonesia bukan sekadar soal seberapa lengkap regulasi disusun, melainkan sejauh mana negara berani menggunakan regulasi tersebut sebagai alat kontrol yang nyata.
Dalam konteks negara dengan tingkat risiko bencana yang sangat tinggi, sikap kompromistis terhadap praktik pembangunan yang berisiko justru memperlemah fungsi hukum itu sendiri. Kasus banjir dan longsor di Sumatra Barat menunjukkan bahwa bencana bukan hanya peristiwa alam, tetapi juga akumulasi dari keputusan politik dan kebijakan yang dibiarkan berjalan tanpa koreksi yang tegas.
Jika regulasi terus diposisikan sebagai prosedur administratif yang bekerja setelah bencana terjadi, maka negara akan terus berada dalam pola reaktif yang berulang.
Sebaliknya, penanggulangan bencana menuntut keberanian politik untuk mengintervensi kepentingan jangka pendek, memperkuat pengawasan, dan menegakkan aturan secara konsisten, bahkan ketika hal tersebut tidak populer.
Tanpa perubahan orientasi tersebut, regulasi hanya akan menjadi arsip hukum, sementara risiko terus dibangun di ruang-ruang yang seharusnya dilindungi.
Dengan demikian, tantangan utama ke depan bukanlah merumuskan aturan baru, melainkan memastikan bahwa regulasi yang sudah ada benar-benar dijalankan sebagai instrumen pencegahan.
Di titik inilah kehadiran negara diuji: apakah ia sekadar hadir setelah bencana terjadi, atau mampu berdiri lebih awal untuk mencegahnya.












.jpg)





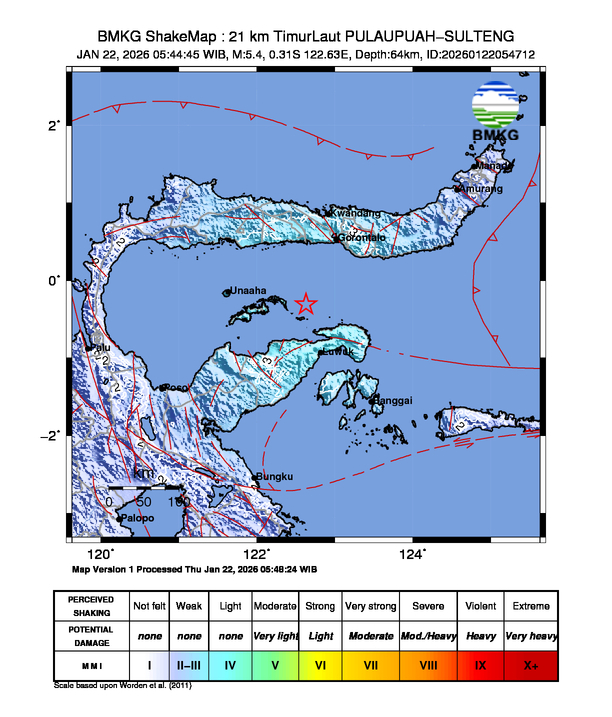
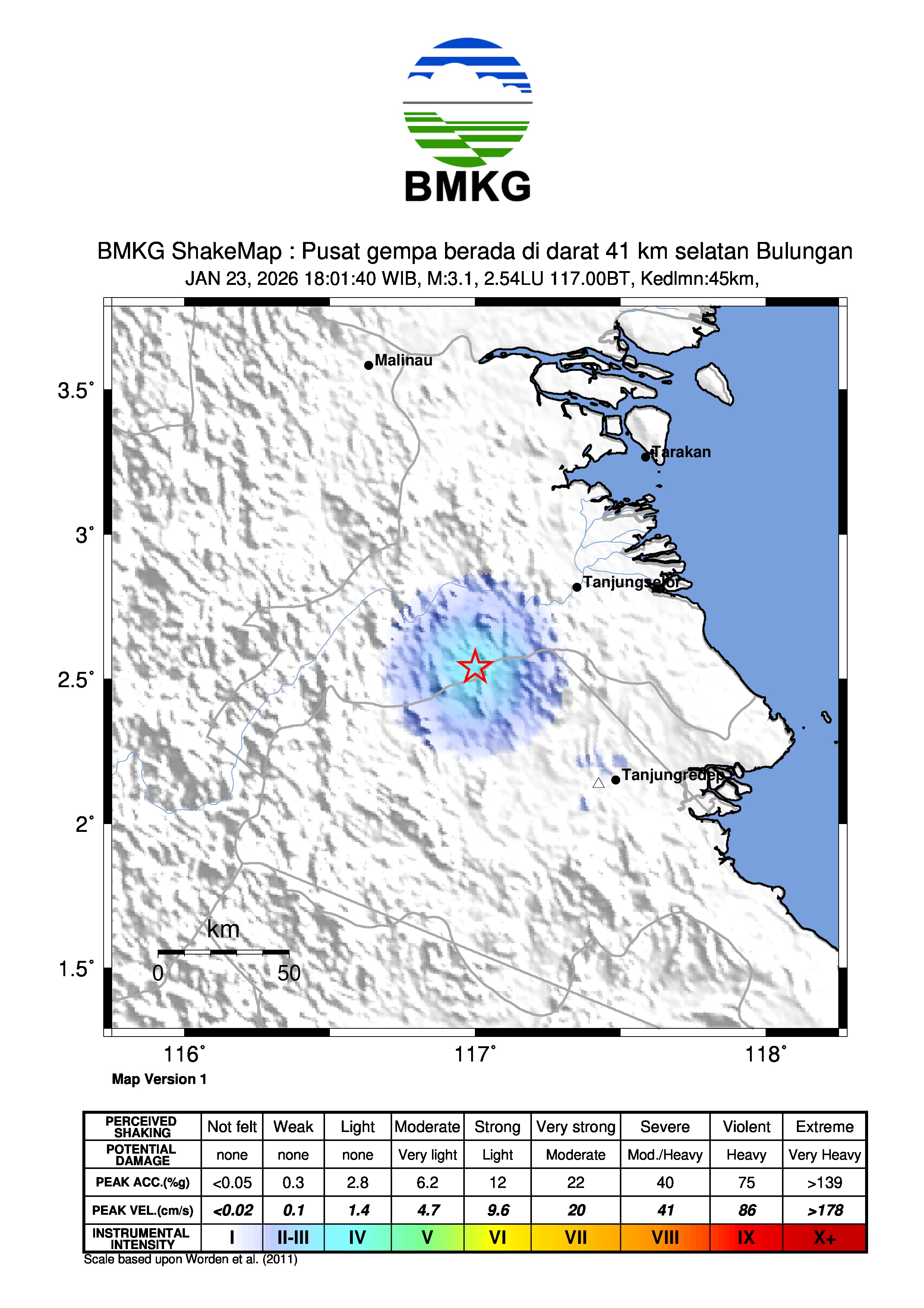






No comments:
Post a Comment