Oleh: Zefin Vachry Nanda ilmu politik universitas Andalas Padang
Partai politik adalah pilar utama demokrasi. Dalam sistem politik modern, efektif atau tidaknya sebuah partai dalam memperjuangkan kepentingan rakyat sangat bergantung pada kualitas dan militansi anggotanya. Untuk itulah, Undang-Undang memberikan mandat tegas kepada partai politik untuk menyelenggarakan pendidikan politik (Dikpol) bagi kader dan masyarakat.
Namun, di tengah kontestasi politik yang semakin sengit, terutama menjelang Pemilu dan Pilkada mendatang, muncul pertanyaan mendasar: Seberapa jauh program pendidikan politik yang dilakukan partai politik mampu meningkatkan kesadaran ideologis dan partisipasi substantif anggota?
Sayangnya, pemandangan yang dominan menunjukkan bahwa Dikpol partai politik seringkali terjebak dalam ritual seremonial dan berorientasi jangka pendek, alih-alih menjadi investasi jangka panjang dalam membangun kader yang kritis dan berkesadaran politik tinggi.
Pendidikan Politik yang Terjebak dalam Agenda Elektoral
Secara ideal, Dikpol adalah kawah candradimuka bagi kader. Ia seharusnya menjadi ruang untuk menanamkan ideologi, pemahaman visi-misi partai, etika politik, serta kemampuan analisis isu publik. Keluaran utamanya adalah kader yang memiliki loyalitas berbasis keyakinan, bukan transaksional.
Namun, di lapangan, fokus Dikpol kerap bergeser tajam. Mayoritas pelatihan yang diselenggarakan cenderung berpusat pada orientasi elektoral semata. Materi yang disajikan lebih didominasi oleh pelatihan teknis pemenangan, seperti strategi kampanye, teknik komunikasi massa, dan mobilisasi massa—bahkan terkadang, secara terselubung, mengajarkan praktik politik door-to-door yang pragmatis.
Pergeseran ini melahirkan konsekuensi serius: anggota partai hanya menjadi "massa mengambang" yang aktif bergerak saat musim kampanye tiba. Setelah perhelatan politik usai, mereka kembali pasif, kurang memiliki inisiatif dalam mengawal kebijakan publik atau menyuarakan kritik konstruktif terhadap pemerintahan, bahkan terhadap kebijakan internal partai sendiri.
Anggota yang seharusnya menjadi motor penggerak partisipasi masyarakat, justru gagal berpartisipasi secara maksimal dalam proses pembangunan ideologi partai itu sendiri. Partisipasi menjadi transaksional, terukur dari seberapa besar perolehan suara yang dihasilkan, bukan dari kualitas kontribusi pemikiran atau gerakan sosialnya.
Mengukur Partisipasi Substantif
Efektivitas Dikpol tidak bisa hanya diukur dari jumlah sertifikat yang dibagikan atau seberapa meriahnya acara pembukaan. Indikator keberhasilan yang sesungguhnya harus terlihat dari tingkat partisipasi substantif anggota di luar kegiatan pemilu.
Pertanyaannya: Berapa banyak anggota yang secara aktif terlibat dalam penyusunan agenda daerah? Berapa banyak kader muda yang berani menyuarakan inovasi atau bahkan kritik internal yang konstruktif? Jika jumlahnya minim, maka ada kegagalan masif dalam transfer ilmu dan penanaman kesadaran dalam program Dikpol.
Untuk konteks lokal (misalnya di Palembang), Dikpol seharusnya melahirkan kader yang paham betul bagaimana mengatasi masalah banjir tahunan, bagaimana mendorong UMKM lokal, atau bagaimana mengawasi anggaran pembangunan infrastruktur. Jika kader hanya sibuk dengan urusan pencalonan dan pembagian atribut, maka pendidikan politik yang dilakukan hanyalah ritual tanpa ruh.
Sebuah contoh kontras adalah (sebutkan contoh ideal, misalnya gerakan sosial atau program komunitas yang diinisiasi kader). Keluaran Dikpol yang ideal adalah kader yang menjadi agen perubahan dan produsen good news bagi masyarakat, bukan sekadar pelengkap daftar hadir politik.
Reorientasi Menuju Investasi Jangka Panjang
Jika partai politik serius ingin menjadi pilar demokrasi yang kuat, sudah saatnya mereka melakukan reorientasi total terhadap program pendidikan politik.
Pertama, Dikpol harus diubah dari kursus kilat elektoral menjadi pembinaan berkelanjutan yang berbasis ideologi. Materi harus fokus pada isu-isu publik yang mendalam, seperti analisis kebijakan, ekonomi kerakyatan, hingga tata kelola pemerintahan yang baik.
Kedua, partai perlu melibatkan akademisi, pakar kebijakan, dan praktisi non-partisan dalam perumusan kurikulum. Tujuannya adalah memastikan materi Dikpol kaya akan analisis kritis, bukan sekadar dogma partai.
Ketiga, diperlukan sistem evaluasi yang mengukur output karya nyata anggota. Misalnya, anggota yang telah mengikuti Dikpol wajib menghasilkan paper analisis isu daerah, atau menginisiasi minimal satu program sosial di tingkat ranting.
Pendidikan politik adalah investasi, bukan sekadar biaya operasional menjelang pemilu. Dengan Dikpol yang efektif, partai akan mendapatkan anggota yang sadar, militan secara ideologis, dan mampu memberikan kontribusi substantif dalam menyelesaikan permasalahan bangsa—sebuah prasyarat mutlak untuk kualitas demokrasi yang lebih baik.
Bahaya Memilih "Gaya" daripada "Capaian"
Fenomena ini menimbulkan masalah fundamental: Gen Z berpotensi memilih pemimpin berdasarkan gaya atau vibes yang disajikan di media sosial, bukan berdasarkan kecakapan atau capaian yang telah teruji.
Para Paslon yang piawai dalam branding digital, mampu menciptakan konten yang 'relatable', atau memiliki dukungan dari influencer besar, seringkali unggul dalam popularitas. Sementara itu, substansi seperti visi-misi yang realistis, komitmen terhadap reformasi birokrasi, atau keberlanjutan fiskal, menjadi catatan kaki yang mudah diabaikan.
Ini adalah partisipasi politik yang kosong. Kita bersukacita melihat tingginya partisipasi, tetapi kita gagal memastikan bahwa partisipasi itu menghasilkan pilihan yang berkualitas. Ketika pemilih didikte oleh euforia digital, kita berisiko memilih pemimpin yang popularitasnya hanya berbasis di dunia maya, tetapi tidak memiliki kompetensi nyata untuk mengelola negara dan menghadapi tantangan kompleks di dunia nyata.
Bahaya jangka panjangnya sangat nyata. Generasi penerus bangsa ini terperangkap dalam pilihan yang didikte oleh popularitas dangkal, yang pada akhirnya akan merugikan mereka sendiri. Mereka akan mewarisi dampak dari keputusan politik yang tidak didasari oleh rasionalitas.
Kritik dan Ajakan untuk Sadar
Maka dari itu, tulisan ini adalah sebuah kritik keras yang membangun, terutama ditujukan kepada Gen Z. Suara Anda bukan sekadar penanda kehadiran di kotak suara; suara Anda adalah tanggung jawab moral yang menentukan nasib bangsa selama lima tahun ke depan.
Untuk menghindari jerat buzzer dan framing digital, Gen Z harus mengaktifkan mode skeptisisme digital.
1. Verifikasi Informasi: Jangan biarkan jempol Anda lebih cepat dari akal sehat Anda. Setiap klaim politik yang provokatif wajib dikonfirmasi ke sumber berita kredibel atau platform cek fakta.
2. Kembali ke Substansi: Alihkan perhatian dari personal attack dan gimmick Paslon. Fokuslah pada visi-misi, rekam jejak kepemimpinan, dan solusi yang ditawarkan. Tanyakan: "Apakah Paslon ini mampu memimpin, atau hanya lihai ber-TikTok?"
3. Memperluas Sumber: Jangan hanya bergantung pada feed media sosial yang sudah disaring oleh algoritma. Cari tahu pandangan yang berseberangan, baca analisis mendalam, dan hadiri diskusi yang substansial.
Partisipasi politik yang tinggi dari Gen Z adalah modal besar bagi masa depan demokrasi Indonesia. Jangan biarkan modal berharga ini disia-siakan dengan menjadi objek manipulasi narasi digital. Jadilah pemilih yang kritis, rasional, dan bertanggung jawab. Mari kita jadikan Gen Z sebagai generasi yang tidak hanya ramai di bilik suara, tetapi juga cerdas dalam membuat pilihan.































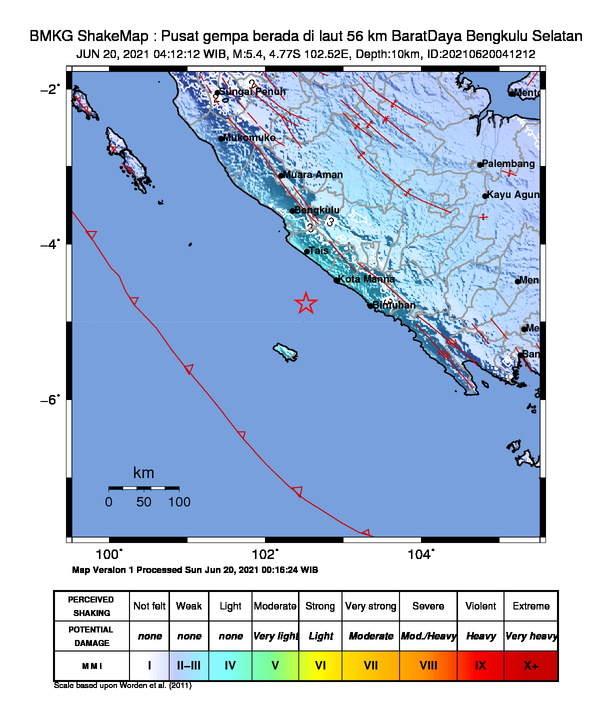








0 Comments