Oleh : Lioni ipatgawati. Nim : 2501041036
PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS DHARMAS INDONESIA TAHUN 2026
Dosen Pengampu : Dr. Amar Salahuddin, M.Pd
Dalam riuh rendah klakson kendaraan yang memekakkan telinga dan kepungan hutan beton yang kian menjulang, kita seringkali lupa bahwa manusia, pada hakikatnya, adalah makhluk biologis yang dibentuk oleh alam, bukan oleh semen dan aspal.
Urbanisasi massal yang terjadi di abad ke-21 bukan sekadar perpindahan demografis atau transformasi fisik sebuah wilayah, melainkan sebuah pergeseran radikal terhadap cara manusia berinteraksi dengan dunianya.
Kota-kota modern tumbuh menjadi entitas yang sangat efisien secara ekonomi, namun sering kali dingin, impersonal, dan "berjarak" secara psikologis dari kebutuhan dasar penghuninya.
Di tengah dinamika yang menyesakkan ini, Ruang Terbuka Hijau (RTH) harus didefinisikan ulang.
Ia tidak boleh lagi dipandang sebagai sekadar pelengkap estetika tata kota atau syarat administratif yang bersifat opsional.
Dalam perspektif humanisme, RTH adalah infrastruktur kesehatan esensial sebuah
jembatan yang menghubungkan kembali jiwa manusia yang lelah dengan akar
alaminya demi membangun resiliensi psikologis yang tangguh di tengah tekanan urban.
Pendekatan humanisme dalam perencanaan kota menekankan bahwa setiap jengkal ruang harus memiliki nilai manfaat bagi martabat dan kesejahteraan manusia. Namun, realitas urban saat ini menunjukkan fenomena yang memprihatinkan. Masyarakat kota terjebak dalam apa yang disebut sebagai kelelahan kognitif kronis.
Setiap hari, otak manusia dipaksa melakukan "perhatian terarah" yang sangat intensif, mulai dari menavigasi kemacetan hingga memproses bombardir informasi visual dari reklame yang agresif. Tanpa adanya jeda hijau, manusia mengalami degradasi mental yang berujung pada iritabilitas dan ketidakmampuan mengelola emosi. Argumen ini diperkuat oleh data dari jurnal The Lancet Planetary Health yang mengungkapkan bahwa individu yang tinggal di lingkungan dengan akses ruang hijau yang rendah memiliki risiko 20% lebih tinggi terkena gangguan kecemasan dan depresi dibandingkan mereka yang tinggal di dekat taman.
Hal ini memberikan bukti empiris bahwa keberadaan pohon dan taman di tengah kota bukan sekadar hiasan, melainkan "ruang penyembuhan" yang bekerja secara neurobiologis dalam menyeimbang kan kimiawi otak kita.
Sebagai penulis, saya memandang bahwa akses terhadap ruang terbuka hijau seharusnya tidak lagi menjadi sebuah privilese atau kemewahan, melainkan hak asasi manusia yang mendasar.
Urbanisasi yang tidak terkendali telah menciptakan bentuk ketidakadilan baru yang disebut "segregasi resiliensi".
Di kota-kota besar, masyarakat kelas atas mampu membeli hunian eksklusif yang dilengkapi taman privat yang asri, sementara masyarakat berpenghasilan rendah harus berhimpitan di gang-gang sempit tanpa sehelai daun pun untuk dipandang.
Padahal, studi yang diterbitkan dalam Journal of Epidemiology and Community Health menunjukkan bahwa hubungan positif antara ruang hijau dan kesehatan mental justru ditemukan paling kuat pada kelompok masyarakat dengan status sosioekonomi rendah.
Bagi mereka yang hidup dalam keterbatasan, taman kota adalah satu-satunya sarana pelarian gratis dari tekanan hidup yang berat. Oleh karena itu, membiarkan RTH beralih fungsi menjadi pusat perbelanjaan atau lahan parkir bukan hanya kesalahan tata ruang, melainkan sebuah bentuk kejahatan sistemik terhadap hak kesehatan mental warga yang paling rentan.
Secara psikologis, kehadiran vegetasi di tengah kota memicu efek restoratif yang luar biasa melalui mekanisme Attention Restoration Theory (ART). Berdasarkan penelitian dalam International Journal of EnvironmentalMResearch and Public Health, paparan terhadap elemen alami seperti tekstur daun,nspektrum warna hijau, hingga senyawa organik seperti phytoncides yang dilepaskan pohon, terbukti secara klinis mampu meningkatkan sel pembunuhmalami (natural killer cells) dalam sistem imun manusia dan menurunkan kadar kortisol, sang hormon stres, secara signifikan. Namun, manfaat RTH lebih dalamndari sekadar fungsi biologis, ia adalah ruang demokratis yang memanusia kan manusia.
Di bawah naungan pohon yang rindang, strata sosial seolah luruh.
Taman menyediakan panggung bagi interaksi organik yang tidak dimediasi oleh transaksi ekonomi. Saat warga berkumpul, berolahraga, atau sekadar duduknbersisian di taman, terjadi pelepasan hormon oksitosin yang mendorong rasa percaya dan empati antar sesama. Inilah yang membangun modal sosial, yang pada gilirannya menjadi perisai psikologis kolektif saat masyarakat menghadapi krisis atau bencana.
Namun, hambatan terbesar dalam mewujudkan paradigma RTH sebagai infrastruktur kesehatan adalah cara pandang ekonomi yang sempit dan teknokratis. Banyak pengambil kebijakan yang masih melihat lahan kosong hanya dari nilai pajaknya jika dibangun gedung.
Argumen ekonomi ini sesungguhnya sangat rapuh jika kita memasukkan variabel biaya kesehatan masyarakat ke dalam kalkulasi pembangunan.
Sebuah studi komprehensif di Belanda yang dipublikasikan dalam Scientific Reports mengestimasi bahwa peningkatan ruang hijau dalam radius satu kilometer dari pemukiman dapat menghemat biaya kesehatan nasional hingga jutaan Euro per tahun akibat penurunan prevalensi penyakit terkait stres dan gangguan pernapasan. Jika pemerintah kota mampu menyadari bahwa investasi pada satu batang pohon adalah investasi pada penurunan angka bunuh diri dan peningkatan produktivitas kerja warga, maka wajah kota-kota kita pasti akan berubah.
Kita membutuhkan kota yang memiliki pori-pori untuk bernapas, bukan kota yang tersumbat oleh ambisi pertumbuhan fisik semata yang mengabaikan aspek kejiwaan.
Ke depannya, kita harus bergerak menuju visi "Kota Biofilik", di mana alam tidak diletakkan di pinggiran, melainkan diintegrasikan secara mulus ke dalam setiap aspek infrastruktur kota. Jalur pedestrian yang teduh, atap gedung yang hijau, dan koridor ekologi yang menghubungkan sudut-sudut kota adalah manifestasi nyata dari penghargaan terhadap martabat manusia.
Resiliensi psikologis masyarakat kota tidak akan pernah bisa dibangun di atas lingkungan yang gersang, bising, dan penuh polusi.
Ia membutuhkan nutrisi visual dan akustik alami yang hanya bisa disediakan oleh ekosistem yang sehat. Setiap pohon yang ditebang tanpa pengganti yang sepadan adalah pengurangan terhadap cadangan kesehatan mental warga.
Kita harus menuntut para perencana kota untuk tidak hanya menghitung kekuatan beton (hardscape), tetapi juga menghargai kekuatan penyembuhan yang ditawarkan oleh alam (softscape).
Sebagai penutup, penting untuk kita renungkan bahwa urbanisasiadalah keniscayaan sejarah, namun membiarkan manusia kehilangan kemanusiaan nya dalam proses tersebut adalah sebuah kegagalan peradaban.
Ruang Terbuka Hijau adalah benteng terakhir pertahanan psikologis manusia di tengah gempuran modernitas yang impersonal dan serba cepat. Ketika kita memberikan ruang bagi alam untuk tumbuh di jantung kota, sebenarnya kita sedang memberikan ruang bagi diri kita sendiri untuk tetap waras, sehat, dan bermartabat.
Pesan saya bagi setiap pemangku kebijakan dan warga kota: jangan pernah melihat taman sebagai lahan sisa yang belum dibangun.
Lihatlah setiap jengkal hijau sebagai apotek alam yang menyediakan obat bagi jiwa-jiwa yang letih.
Kota yang hebat bukanlah kota yang memiliki gedung paling menjulang atau teknologi paling mutakhir, melainkan kota yang mampu membuat warganya merasa paling tenang dan manusiawi saat mereka melangkah keluar dari pintu rumahnya. Lindungilah ruang hijau seolah-olah Anda sedang melindungi kewarasan Anda sendiri, karena pada hakikatnya, memang itulah yang sedang Anda lakukan.



































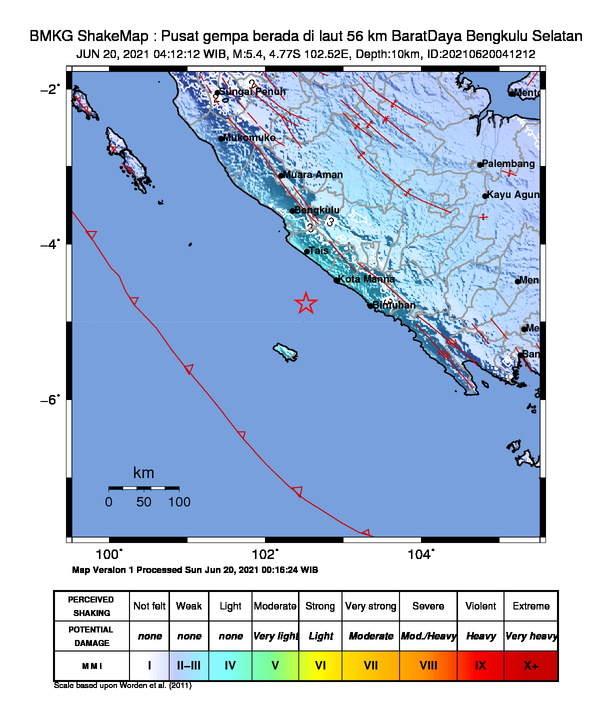








0 Comments