Oleh ; Devi Novita Sari. Nim : 2501041006. PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN. UNIVERSITAS DHARMAS INDONESIA TAHUN 2026
Dosen Pengampu : Dr. Amar Salahuddin, M.Pd
Di tengah gegap gempita transformasi digital, pemerintah, korporasi, dan lembaga pendidikan berlomba-lomba menggaungkan pentingnya "literasi digital."
Program pelatihan diadakan, webinar digelar, dan modul dibuat untuk mengajari masyarakat cara menggunakan aplikasi, platform ecommerce, atau media sosial. Namun, fokusnya kerap hanya pada aspek keterampilan teknis (digital skills). Padahal, jantung dari literasi digital yang sesungguhnya justru terletak pada sesuatu yang lebih mendasar dan sering terabaikan: pola pikir kritis dan etis dalam berinteraksi di ruang digital.
Inilah sisi gelap dari narasi literasi digital kita kita pandai mengklik, tetapi gagap menyaring.
Sudut pandang ini sengaja diambil karena arus utama pembicaraan tentang literasi digital cenderung instrumental dan ekonomis. Literasi digital dijual sebagai alat untuk naik kelas ekonomi: bisa jualan online, bisa kerja daring, dan menjadi lebih "produktif."
Hal itu tidak salah, tetapi dangkal. Kita lupa bahwa sebelum
menjadi pasar atau tenaga kerja digital, manusia adalah warga negara (digital citizens) yang hidup dalam ekosistem informasi yang kompleks.
Tanpa pola pikir yang tepat, keterampilan teknis justru bisa menjadi bumerang. Orang yang mahir menggunakan TikTok belum tentu imun terhadap hoaks yang viral di platform tersebut. Seorang penjual online yang lihai memanfaatkan algoritma Instagram bisa saja terjebak dalam menyebarkan konten negatif atau melakukan cyberbullying kepada kompetitor. Inilah paradoksnya: kita menciptakan masyarakat yang terampil secara digital, tetapi rapuh secara mental dan intelektual di ruang siber.
Argumen utama saya adalah, membangun pola pikir digital yang sehat lebih urgent daripada sekadar mengajarkan keterampilan operasional.
Pola pikir ini mencakup beberapa elemen krusial. Pertama, skeptisisme sehat.
Di dunia di mana informasi diproduksi dan disebarkan dengan kecepatan cahaya, kemampuan untuk mempertanyakan, mengecek ulang, dan tidak serta-merta mempercayai apa yang pertama kali dilihat adalah tameng utama.
Kedua, kesadaran akan jejak digital dan privasi.
Banyak pengguna yang piawai mengunggah konten, tetapi tidak menyadari bahwa setiap like, share, dan pencarian membentuk profil digital mereka yang
bisa dimanfaatkan oleh pihak lain, seringkali tanpa persetujuan yang sadar.
Ketiga, empati dan etika digital.
Ruang digital yang terasa anonym seringkali melunturkan norma kesopanan.
Komentar kasar, doxxing
(menyebarkan data pribadi), dan ujaran kebencian adalah buah dari absennya empati ini.
Untuk memperkuat bangunan argumen ini, data dan ilustrasi kasus sangat diperlukan.
Survei yang dirilis oleh
Reuters Institute pada 2023 menunjukkan bahwa Indonesia termasuk dalam negara dengan tingkat kepercayaan terhadap informasi di media sosial yang cukup tinggi sekaligus kerentanan terhadap misinformasi yang juga tinggi.
Ini mengindikasikan bahwa skill mengakses informasi ada, tetapi filter kritis tidak.
Sebuah kasus nyata yang menggambarkan fatalnya ketiadaan pola pikir ini adalah maraknya panic buying dan penimbunan obat- obatan pada puncak pandemi COVID-19, yang sebagian besar dipicu oleh informasi yang tidak terverifikasi yang menyebar di grup-grup WhatsApp dan Facebook.
Orang-orang yang secara teknis mampu menggunakan aplikasi pesan tersebut justru menjadi agent penyebaran kepanikan.
Ilustrasi lain terlihat dalam dunia pendidikan.
Program "Merdeka Belajar" mendorong penggunaan teknologi, tetapi apakah disertai dengan pendidikan tentang bagaimana mengevaluasi kredibilitas sumber digital yang digunakan siswa untuk mengerjakan tugas? Atau tentang plagiarisme konten digital?
Tanpa fondasi pola pikir ini, siswa hanya menjadi penyalin dan penikmat konten pasif, bukan pencipta dan analis yang cerdas.
Pesan utama dari tulisan ini tunggal dan jelas: Pemerintah, institusi pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan harus segera melakukan reorientasi program literasi digital.
Literasi digital tidak boleh lagi dipahami sebagai paket kursus aplikasi semata, tetapi harus diintegrasikan sebagai pendidikan karakter dan pola pikir yang berkelanjutan. Kurikulum di sekolah perlu memasukkan materi tentang berpikir kritis di dunia digital, keamanan data pribadi, dan etika berkomunikasi online.
Kampanye publik harus bergeser dari sekadar
"melek teknologi" menjadi "cerdas dan santun bermedia."
Pada akhirnya, tujuan literasi digital sejati adalah menciptakan ruang digital yang tidak hanya efisien, tetapi juga beradab, inklusif, dan aman bagi semua warganya. Kita tidak ingin hanya mencetak generasi yang jari- jemarinya lincah mengetik, tetapi yang hatinya peka dan pikirannya tajam dalam menyikapi setiap gempuran informasi. Membangun digital skills itu seperti memberikan pisau; sedangkan membangun digital mindset adalah mengajarkan untuk memegangnya dengan hati-hati, tahu kapan menggunakan nya, dan untuk tujuan apa.
Sudah waktunya kita berhenti hanya terpukau pada ketajaman pisau itu, dan mulai serius memikirkan jiwa dari orang yang memegangnya.












.jpg)





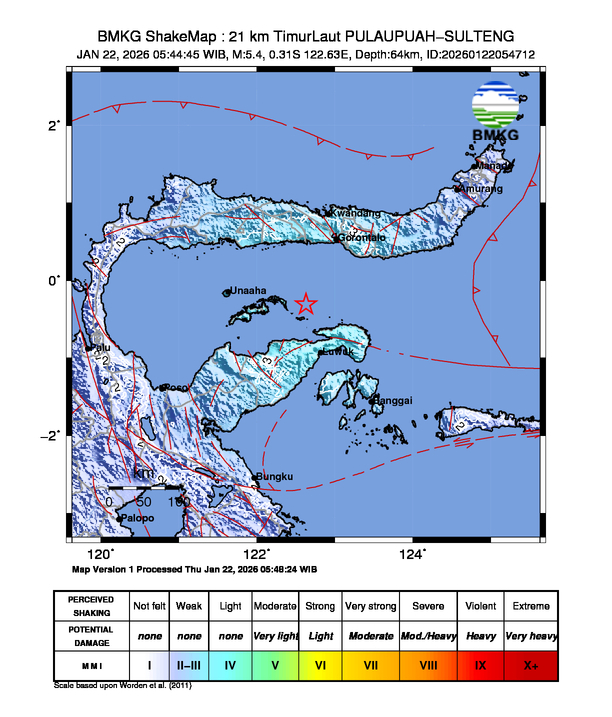
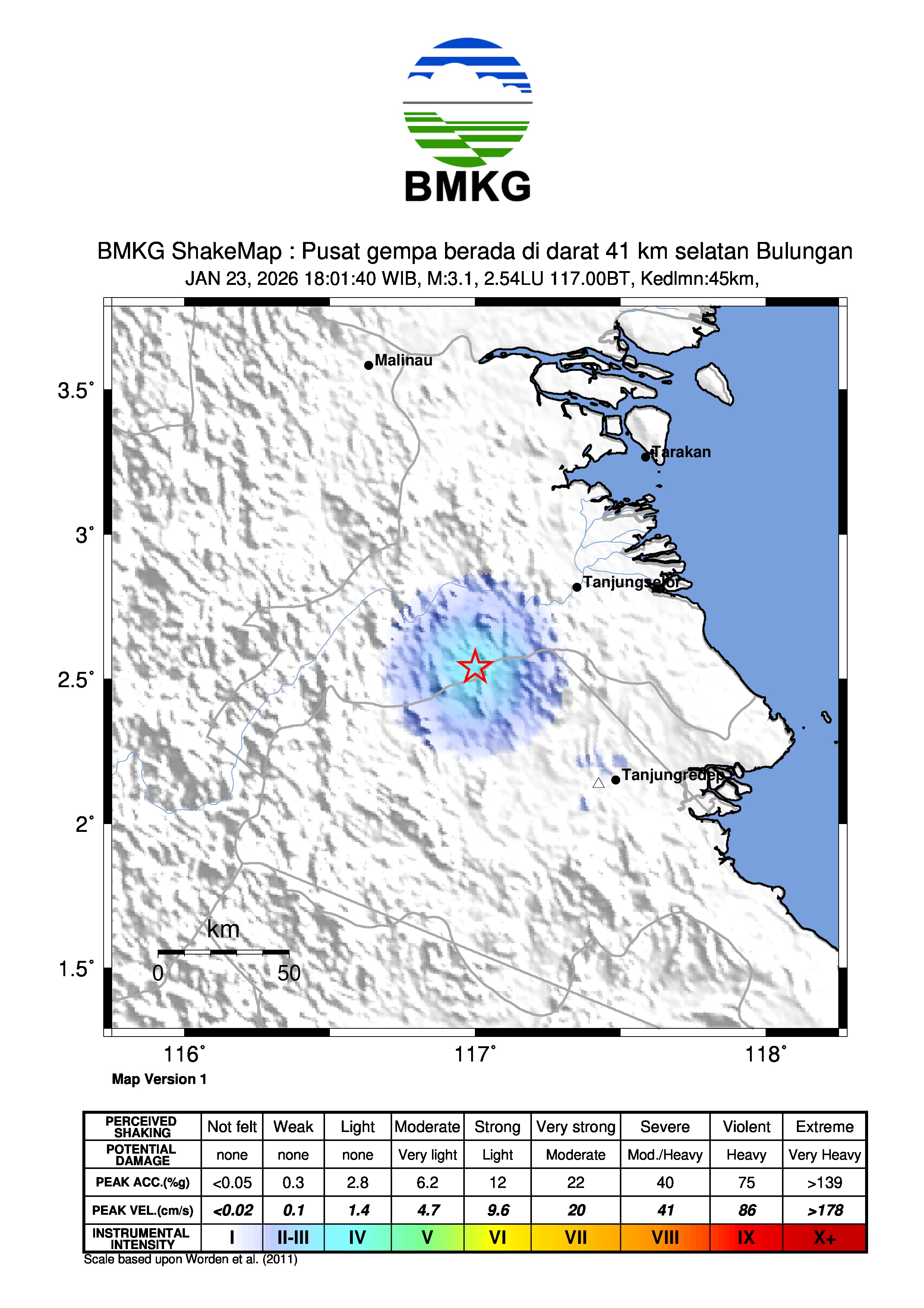






No comments:
Post a Comment