Oleh
Mulyadi, S.H
Penulis adalah Mahasiswa Magister Hukum Universitas Andalas
Indonesia sejak awal berdirinya tidak pernah memposisikan diri sebagai negara dengan sistem hukum yang tunggal, seragam, dan homogen. Pilihan tersebut bukanlah suatu kebetulan, melainkan refleksi dari realitas historis, sosiologis, dan kultural bangsa Indonesia yang sejak lama hidup dalam keragaman sistem nilai, norma, dan tata aturan sosial.
Sebelum terbentuknya negara modern, dengan perangkat hukum positifnya, berbagai komunitas di nusantara telah mengenal dan mempraktikkan sistem hukum mereka sendiri yang lahir dari kebiasaan, tradisi, serta nilai-nilai lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, pluralisme hukum bukanlah konsep impor atau konstruksi akademik semata, melainkan fakta empiris yang melekat dalam perjalanan sejarah hukum Indonesia.
Pluralisme hukum Indonesia tercermin dari keberadaan berbagai sistem hukum yang hidup berdampingan, seperti hukum negara, hukum agama, dan hukum adat. Ketiganya tidak selalu berada dalam relasi yang harmonis, tetapi secara nyata membentuk konfigurasi sistem hukum nasional. Hukum negara hadir sebagai produk kekuasaan formal yang dilembagakan melalui peraturan perundang-undangan, sementara hukum adat tumbuh sebagai hukum tidak tertulis yang hidup, ditaati, dan diyakini oleh masyarakat sebagai pedoman perilaku yang sah dan mengikat. Hukum adat tidak dapat dipahami sekadar sebagai peninggalan masa lalu, melainkan sebagai sistem normatif yang dinamis dan terus beradaptasi dengan perkembangan masyarakat.
Dalam ranah pidana, keberadaan hukum pidana adat memiliki posisi yang sangat khas. Berbeda dengan hukum pidana positif yang bersifat tertulis, formal, dan menitikberatkan pada asas legalitas, hukum pidana adat berangkat dari nilai-nilai kolektif dan rasa keadilan masyarakat setempat. Hukum pidana adat sejak lama berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang efektif, karena lahir dari kesepakatan sosial dan memiliki legitimasi moral yang kuat di mata masyarakat adat. Pelanggaran terhadap norma adat tidak hanya dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi juga sebagai tindakan yang mengganggu keseimbangan sosial, kosmis, dan spiritual komunitas.
Fungsi utama hukum pidana adat bukan semata-mata untuk menghukum pelaku, melainkan untuk memulihkan harmoni yang terganggu akibat suatu pelanggaran. Oleh karena itu, sanksi adat sering kali diarahkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan pada pembalasan dalam arti retributif. Mekanisme seperti musyawarah adat, pemberian denda adat, ritual pemulihan, atau permintaan maaf terbuka mencerminkan orientasi restoratif yang telah lama hidup dalam praktik hukum pidana adat. Pendekatan ini bahkan dinilai lebih efektif dalam menciptakan perdamaian sosial dibandingkan proses peradilan pidana formal yang kaku dan berjarak dari masyarakat.
Seiring dengan berkembangnya negara hukum modern dan menguatnya rezim hak asasi manusia, penerapan hukum pidana adat tidak luput dari sorotan kritis.Prinsip-prinsip Hak Asassi Manusia (HAM) yang menekankan perlindungan martabat manusia, persamaan dihadapan hukum, serta larangan terhadap perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi, menuntut adanya standar normatif yang jelas dalam setiap praktik penegakan hukum, termasuk hukum pidana adat. Dititik inilah muncul ketegangan antara nilai-nilai tradisional yang hidup dalam masyarakat adat dan prinsip-prinsip universal HAM yang diadopsi oleh negara.
Tidak semua sanksi atau mekanisme hukum pidana adat sejalan dengan prinsip HAM. Beberapa praktik adat masih memuat unsur diskriminatif, baik berbasis gender, status sosial, maupun asal-usul keturunan. Selain itu, terdapat pula sanksi adat yang bersifat eksesif, seperti pengucilan sosial berkepanjangan, pengusiran dari komunitas, denda adat yang tidak proporsional, hingga hukuman fisik yang berpotensi melanggar hak atas integritas tubuh dan martabat manusia. Ketika praktik-praktik semacam ini dipertahankan tanpa koreksi, hukum pidana adat berpotensi kehilangan legitimasi konstitusionalnya.
Konstitusi Indonesia sesungguhnya telah memberikan kerangka normatif yang jelas dalam menyikapi persoalan ini. Pasal 18 B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Frasa “sepanjang masih hidup” dan “sesuai dengan perkembangan masyarakat” menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hukum adat bersifat dinamis dan kondisional, bukan statis dan absolut.
Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Norma ini mengandung makna bahwa penghormatan terhadap hukum adat harus ditempatkan dalam konteks negara hukum modern yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban. Konstitusi tidak memosisikan hukum adat sebagai sistem hukum yang kebal terhadap kritik, melainkan sebagai entitas yang harus terus bertransformasi agar tetap relevan dan berkeadilan.
Pengakuan konstitusional tersebut menegaskan bahwa hukum adat, termasuk hukum pidana adat, bukanlah entitas ilegal atau tersisih dari sistem hukum nasional. Sebaliknya, ia merupakan bagian dari realitas hukum Indonesia yang diakui keberadaannya dan memiliki kontribusi penting dalam menjaga ketertiban sosial di tingkat lokal. Pengakuan ini sekaligus mengandung kewajiban untuk memastikan bahwa penerapan hukum pidana adat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi, khususnya perlindungan hak asasi manusia.
Persoalan konstitusionalitas hukum pidana adat tidak dapat dipahami semata-mata sebagai soal pengakuan normatif, melainkan juga sebagai soal pembatasan dan pengendalian. Konstitusionalitas hukum pidana adat diuji bukan hanya dari keberadaannya, tetapi dari cara penerapannya. Ketika hukum pidana adat dijalankan dengan mengabaikan martabat manusia, maka pada saat itu pula ia kehilangan dasar konstitusionalnya. Sebaliknya, ketika hukum pidana adat mampu beradaptasi dengan nilai-nilai HAM dan prinsip negara hukum, ia justru memperkaya sistem hukum nasional dengan pendekatan keadilan yang lebih kontekstual dan manusiawi.
Dalam kerangka inilah, diskursus mengenai batasan HAM dalam penerapan hukum pidana adat menjadi sangat relevan dan mendesak. Negara dituntut untuk mampu menyeimbangkan antara penghormatan terhadap pluralisme hukum dan kewajiban konstitusional untuk melindungi hak asasi manusia. Tantangan utama bukanlah memilih antara hukum adat atau HAM, melainkan merumuskan mekanisme harmonisasi yang memungkinkan keduanya berjalan seiring dalam kerangka negara hukum Indonesia yang berkeadilan dan beradab.
Pengakuan konstitusional tersebut sejak awal telah diletakkan dalam kerangka yang bersyarat. Konstitusi tidak memberikan legitimasi mutlak terhadap semua praktik hukum adat tanpa pengecualian. Pengakuan tersebut dibatasi oleh perkembangan masyarakat, prinsip negara kesatuan, dan yang paling penting, penghormatan terhadap hak asasi manusia. Di sinilah letak problem utama penerapan hukum pidana adat: bagaimana menjaga keberlanjutan nilai-nilai adat tanpa mengorbankan perlindungan HAM sebagai prinsip universal dan konstitusional.
Hukum pidana adat dipahami sebagai living law, yakni hukum yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat dan dipatuhi karena memiliki legitimasi sosial. Hukum pidana adat tidak berorientasi pada pembalasan semata, melainkan pada pemulihan keseimbangan kosmis dan sosial yang terganggu akibat suatu pelanggaran. Sanksi adat sering kali bersifat simbolik, kolektif, dan restoratif, seperti denda adat, permintaan maaf di hadapan komunitas, atau ritual tertentu.
Hukum pidana adat kerap dipandang lebih humanis dan kontekstual dibandingkan hukum pidana negara yang bersifat formal dan retributif.
Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktiknya, sebagian sanksi pidana adat justru menimbulkan persoalan HAM yang serius. Pengucilan sosial, pengusiran dari komunitas, denda adat yang tidak proporsional, hingga hukuman fisik masih ditemukan dalam beberapa praktik hukum adat. Sanksi semacam ini berpotensi melanggar hak atas martabat manusia, prinsip persamaan di hadapan hukum, serta larangan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Ketika sanksi adat menimbulkan penderitaan fisik atau psikologis yang berlebihan, maka legitimasi moral dan konstitusional nya patut dipertanyakan.
Negara, sebagai pemegang kewajiban utama perlindungan HAM, tidak dapat bersikap netral atau pasif terhadap praktik hukum pidana adat yang melanggar HAM. Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa, pembatasan hak asasi manusia hanya dapat dilakukan dengan undang-undang dan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Artinya, tidak ada ruang bagi pembenaran pelanggaran HAM atas nama tradisi atau budaya semata. Budaya dan adat istiadat tidak boleh dijadikan tameng untuk melegitimasi praktik yang bertentangan dengan martabat manusia.
Menafikan hukum pidana adat secara total dengan alasan HAM juga merupakan pendekatan yang keliru dan ahistoris. Pendekatan semacam ini berisiko melanggengkan dominasi hukum negara yang sentralistik dan mengabaikan kearifan lokal. Lebih jauh, penghapusan hukum pidana adat justru dapat memicu alienasi hukum, di mana masyarakat adat merasa hukum negara asing dan tidak mencerminkan nilai-nilai mereka. Oleh karena itu, persoalan konstitusionalitas hukum pidana adat tidak seharusnya dipahami dalam kerangka “diterima atau ditolak”, melainkan dalam kerangka harmonisasi dan transformasi.
Harmonisasi antara hukum pidana adat dan HAM merupakan kebutuhan mendesak dalam sistem hukum Indonesia kontemporer. Harmonisasi ini menuntut proses selektif dan kritis terhadap praktik-praktik hukum pidana adat.
Nilai-nilai adat yang sejalan dengan HAM, seperti musyawarah, pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab kolektif, dan penghormatan terhadap korban, perlu dipertahankan dan diperkuat. Sebaliknya, praktik-praktik yang bersifat diskriminatif, represif, atau merendahkan martabat manusia harus ditinggalkan atau ditransformasikan. Pendekatan keadilan restoratif menawarkan jalan tengah yang konstruktif. Keadilan restoratif menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, serta rekonsiliasi sosial, bukan pada pembalasan. Nilai-nilai ini sejatinya memiliki irisan yang kuat dengan filosofi hukum pidana adat. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip HAM ke dalam praktik hukum pidana adat melalui pendekatan restoratif, hukum adat tidak kehilangan identitasnya, tetapi justru memperoleh legitimasi baru dalam kerangka negara hukum modern.
Negara memiliki peran strategis dalam proses harmonisasi ini. Pengakuan terhadap hukum pidana adat harus disertai dengan pembinaan, pengawasan, dan pemberian batas normatif yang jelas. Negara tidak boleh menyerahkan sepenuhnya penerapan hukum pidana adat tanpa standar HAM yang tegas. Negara juga tidak boleh memaksakan hukum pidana nasional secara kaku tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat adat. Keseimbangan antara pengakuan dan pembatasan inilah yang menjadi inti dari konstitusionalitas hukum pidana adat.
Pembaruan hukum pidana nasional, pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana tercermin dalam kebijakan legislasi pidana menunjukkan arah yang lebih inklusif. Namun, pengakuan tersebut harus selalu disertai dengan prinsip kehati-hatian konstitusional. Hukum pidana adat hanya dapat diterapkan sepanjang tidak bertentangan dengan HAM dan prinsip negara hukum. Hukum pidana adat tidak ditempatkan sebagai “hukum alternatif” yang kebal kritik, melainkan sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang tunduk pada konstitusi.
Perdebatan mengenai konstitusionalitas dan batasan HAM dalam penerapan hukum pidana adat mencerminkan dinamika lebih luas antara tradisi dan modernitas, antara lokalitas dan universalitas. Negara hukum Indonesia dituntut untuk tidak memilih salah satu secara ekstrem, melainkan merajut keduanya dalam kerangka keadilan substantif. Hukum pidana adat dapat dan harus tetap hidup, tetapi kehidupannya harus selaras dengan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai nilai tertinggi dalam konstitusi. Di sinilah ukuran sejati konstitusionalitas hukum pidana adat diuji: bukan semata pada pengakuan normatif, melainkan pada kemampuannya menghadirkan keadilan yang manusiawi dan beradab. ***












.jpg)





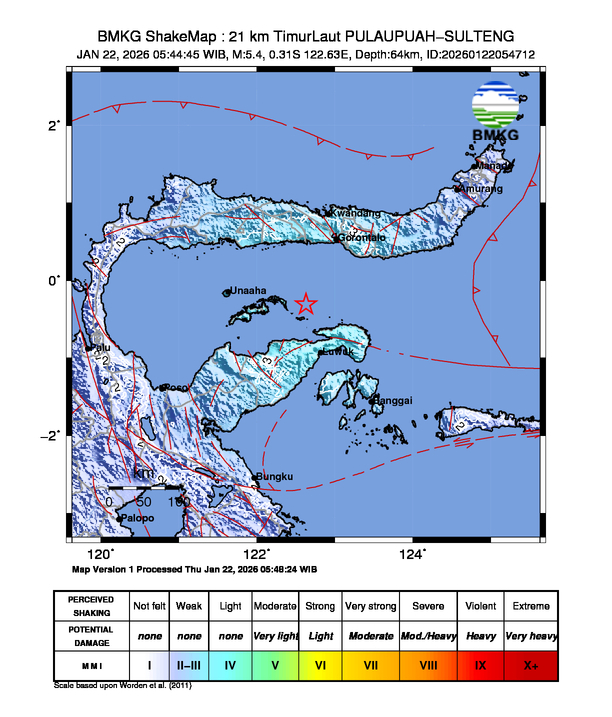
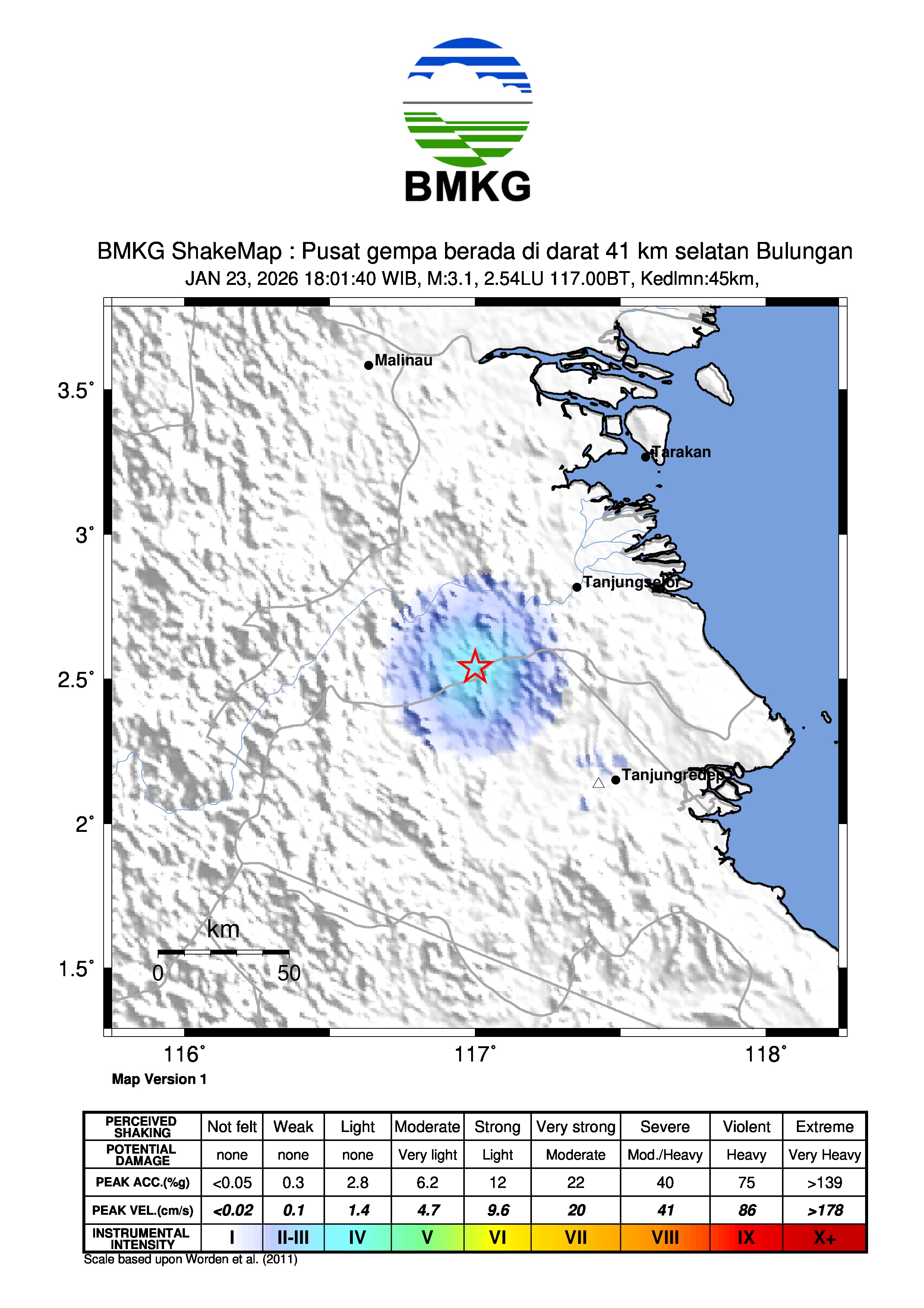






No comments:
Post a Comment