Penulis: Citra Ayu Annisa Mahasiswa Mahasiswa Biologi Universitas Andalas Padang
SUMATRAJUGAINDONESIA
Sawit juga pohon, dia punya daun, juga bisa menyerap karbondioksida”
Ketika Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa kelapa sawit tidak perlu ditakuti karena “itu juga pohon” dan “juga menyerap CO₂,” publik kembali dihadapkan pada penalaran yang membuag kita berpikir bahwa hutan menjadi sekadar batang dan daun. Sebuah penyederhanaan yang tampak sepele, tetapi berbahaya, sebab ia menentukan arah kebijakan yang berhubungan langsung dengan masa depan ekologi Indonesia.
Masalahnya bukan pada sawit sebagai komoditas. Masalahnya muncul ketika sawit digunakan sebagai pembenaran untuk menormalisasi hilangnya hutan tropis. Ketika hutan dianggap bisa diganti, digeser, atau disubstitusi oleh perkebunan monokultur. Ketika logika ekologis yang mestinya menjadi dasar pengambil keputusan diganti dengan logika komoditas. Padahal ekosistem hutan tidak pernah sama dengan kebun. Hutan memerlukan ratusan tahun untuk membangun jaringan tanah, organisme, kanopi, sungai kecil, dan daur air. Sawit, sebaliknya, memerlukan pola pengelolaan yang seragam, teratur, terkuras, dan berorientasi produksi.
Sementara itu, Indonesia semakin sering diterjang bencana hidrologis yang intensitasnya meningkat dari tahun ke tahun. Ketika hujan deras turun, air tidak lagi diserap tanah karena tanahnya telah hilang. Ketika sungai meluap, tidak ada lagi vegetasi rapat yang menahan arus. Ketika banjir menghantam permukiman, seolah tidak ada lagi kemampuan negara membaca pola kerusakan yang sudah sangat jelas. Lalu, di tengah situasi ini, muncul lagi narasi bahwa sawit dapat menggantikan fungsi hutan. Sungguh ironi yang pahit.
Bila kita menyimak apa yang terjadi di Sumatra dalam beberapa tahun terakhir, deretan polanya begitu tidak masuk akal. Tutupan hutan menyusut, sementara izin tambang dan perkebunan terus muncul. Ketika wilayah rawan longsor diberi lampu hijau untuk dieksploitasi, ketika daerah tangkapan air diubah menjadi area produksi, dan ketika sungai-sungai kecil terganggu alirannya, akibat yang terjadi bukanlah kebetulan. Itu konsekuensi. Itu risiko yang telah berkali-kali diingatkan oleh para ahli ekologi, ahli hidrologi, dan warga lokal yang hidup dari tanahnya. Namun peringatan itu tidak pernah benar-benar menjadi dasar keputusan.
Banjir besar di Sumatra bukanlah semata bencana alam. Ia adalah laporan terbuka tentang bagaimana tata kelola lingkungan disepelekan. Ia adalah tanda bahwa negara sedang gagal melindungi fungsi dasar ekologinya. Dan di sinilah muncul pertanyaan penting: bagaimana mungkin kebijakan publik yang menyangkut masa depan ekologi bisa lahir dari logika yang menyamakan hutan dengan sawit? Bagaimana mungkin kita berharap bencana berkurang, kalau analisis dasarnya saja tidak memadai?
Sementara itu, pemerataan perhatian nasional juga masih jauh dari ideal. Ketika bencana berada pulau Jawa, mobilisasi bantuan berjalan cepat. Namun ketika banjir hebat menghantam Sumatra atau Kalimantan, responsnya pemerintah terasa lambat seakan-akan wilayah itu tidak masuk dalam prioritas pusat. Padahal, seluruh pulau di Indonesia menghadapi ancaman ekologis yang sama: curah hujan ekstrem, perubahan iklim, penggunaan lahan yang tak terkendali, dan pengambilan keputusan yang jarang berpihak pada kelestarian jangka panjang.
Dalam situasi seperti ini, kita membutuhkan pandangan yang memahami bahwa ekologi adalah sistem yang saling terkait satu sama lain. Hutan menjaga air, tanah, udara, organisme kecil, dan iklim mikro. Ia adalah puncak utama yang tidak bisa digantikan oleh komoditas apa pun. Dan ketika kita menormalisasi penebangan hutan tropis dengan alasan sawit juga punya daun, kita sedang membuka pintu bagi kerusakan yang jauh lebih besar dari sekadar banjir sesaat.
Ke depan, langkah yang dibutuhkan bukan memperluas kebun monokultur, melainkan memulihkan fungsi ekologis hutan tropis yang tersisa. Membatasi izin tambang di daerah rawan.
Menghentikan ekspansi perkebunan di kawasan yang menjadi daerah tangkapan air. Memperkuat penegakan hukum terhadap perusak lingkungan. Mengembalikan hutan sebagai ruang hidup, bukan ruang produksi.
Dan yang tidak kalah penting: memperbaiki cara berpikir para pembuat keputusan.
Karena negeri ini tidak hanya membutuhkan pohon. Ia membutuhkan hutan yang hidup.
Ia membutuhkan kebijakan yang berdasar sains, bukan narasi yang menenangkan telinga.
Ia membutuhkan keberanian untuk mengatakan bahwa kerusakan ekologis tidak bisa dianggap sepele.
Maka, mari kita kembali ke kalimat pembuka sebuah ironi yang menggambarkan situasi bangsa saat ini:
Sawit memang punya daun.
Sawit memang menyerap CO₂.
Tetapi itu tidak cukup, bahkan benar-benar tidak cukup untuk menahan kebijakan yang memutarbalikkan logika ekologis.












.jpg)





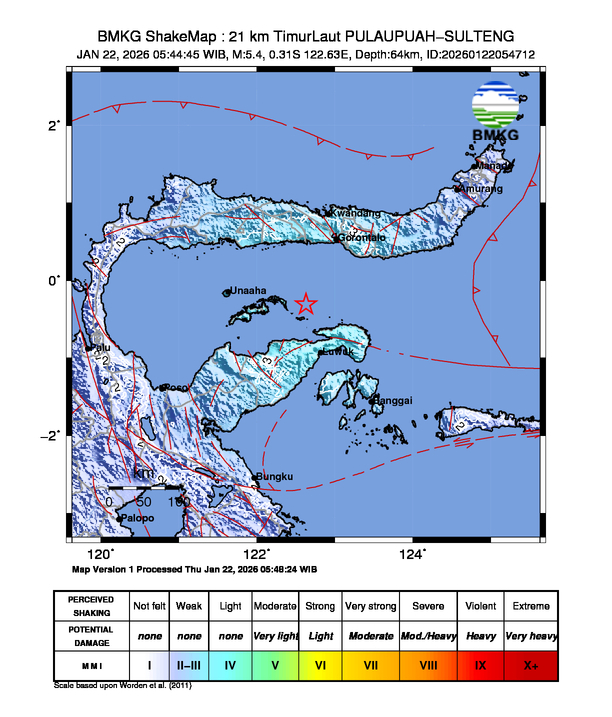
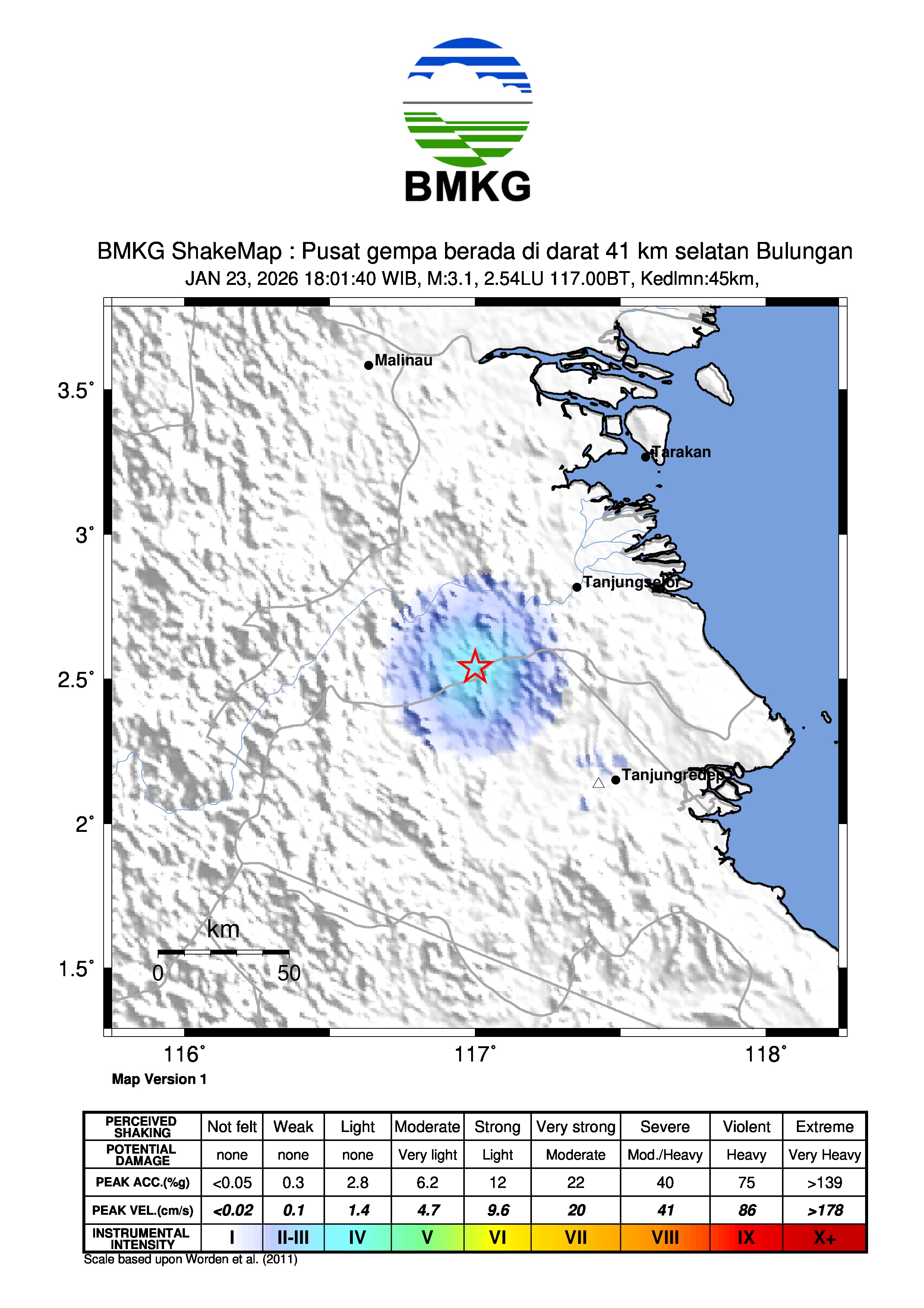






No comments:
Post a Comment