Oleh : Silvi Mahasiswa Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Andalas
Dalam beberapa Minggu terakhir ini, berbagai wilayah di Sumatera kembali diguncang oleh banjir besar yang merendam permukiman, merusak lahan, menutup akses jalan, dan memaksa ribuan warga mengungsi. Hujan dengan intensitas tinggi yang turun hampir tanpa jeda seakan menunjukkan bahwa musim penghujan kini semakin sulit diprediksi. Namun para ahli mengingatkan bahwa penyebabnya bukan hanya curah hujan ekstrem, melainkan juga, karena pembukaan hutan yang masif, penambangan di lereng bukit, serta alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Akibatnya, setiap hujan deras dengan cepat berubah menjadi banjir dan longsor.
Di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pola yang sama berulang dari tahun ke tahun yaitu air naik, rumah terendam, warga mengungsi, lalu kembali pulang untuk menemukan sisa lumpur dan kayu-kayu besar yang terbawa arus. Banjir ini membawa gelondongan kayu yang hanyut dari kawasan hutan yang rusak, menumpuk di jembatan, menutup sungai, dan memperparah kondisi bencana. Bencana hidrometeorologi yang semakin sering terjadi ini bukan hanya menyingkap persoalan tata kelola lingkungan, tetapi juga memperlihatkan hubungan manusia dengan alam. Ketika manusia mengubah bentang alam tanpa kendali, dampaknya kembali kepada manusia sendiri. Ironisnya, dalam beberapa kasus, justru satwa liar yang habitatnya ikut hancur akibat aktivitas manusia akhirnya menjadi “penolong” di tengah bencana.
Salah satu contoh yang paling menyentuh perhatian publik terjadi di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, ketika empat ekor gajah Sumatra (Elephas maximus sumatranus) jinak yaitu Abu, Mido, Ajis dan Noni dikerahkan oleh Balai Konsevasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk membantu membersihkan tumpukan gelondongan kayu besar pasca bencana banjir yang dipandu mahout. Tak hanya membersihkan kayu, gajah-gajah ini juga dikerahkan untuk membawa bantuan kepada warga yang terisolir dan mencari korban hilang. Peristiwa ini seakan menjadi ironi tersendiri. Gajah yang kehilangan habitatnya akibat penebangan pohon di hutan, kini harus membantu manusia usai terjangan banjir bandang.
Fenomena gajah yang dikerahkan untuk membersihkan tumpukan kayu pasca banjir ini tidak hanya menarik perhatian publik, tetapi juga membuka ruang refleksi. Selama bertahun-tahun, hutan di Aceh mengalami degradasi akibat pembalakan liar, alih fungsi lahan, dan tekanan pembangunan. Habitat gajah menyempit, jalur jelajah mereka rusak, dan konflik satwa-manusia meningkat. Ketika gajah masuk ke kebun atau desa, mereka sering diberi label “hama” padahal manusialah yang lebih dulu merusak rumah mereka. Banjir yang terjadi di Pidie Jaya bukanlah bencana alam murni. Gelondongan kayu yang terbawa arus menjadi bukti nyata betapa beratnya tekanan terhadap hutan. Ketika kawasan tutupan hutan ditebang tanpa kontrol, daya serap tanah menurun, limpasan air meningkat, dan sungai kehilangan penyangga alami. Gajah, sebagai bagian dari ekosistem hutan, juga merasakan dampaknya. Mereka kehilangan ruang hidup sekaligus makanan, sementara manusia kehilangan perlindungan ekologis yang selama ini disediakan gratis oleh hutan.
Dalam situasi darurat pasca banjir, manusia tidak lagi bisa mengandalkan alat berat semata. Medan licin dan sempit membuat operasi pembersihan gelondongan kayu sulit dilakukan. Di sinilah gajah mengambil peran, dengan kekuatan alami dan kemampuan bergerak di medan sulit, mereka bekerja tanpa keluhan. Gading dan belalai mereka digunakan untuk menggeser kayu besar yang tidak mampu ditangani mesin. Gajah-gajah itu, dengan belalai yang kuat dan tubuh raksasa yang seharusnya bebas berkeliaran di hutan, kini berdiri di tengah tumpukan kayu yang ironisnya berasal dari rumah mereka sendiri. Pohon-pohon yang dulu menjadi tempat makan, berlindung, dan berinteraksi kini berubah menjadi puing-puing yang harus mereka singkirkan untuk memulihkan kembali wilayah manusia.
Gajah menjadi simbol dari siklus yang kita ciptakan sendiri, dimana kita merusak, mereka menderita, kita kebanjiran, mereka yang membantu. Namun ironinya, setelah bencana berlalu, sebagian orang kembali lupa dan konflik satwa kembali terjadi. Ini bukan pertama kalinya gajah membantu bencana Aceh. Peran penting gajah jinak untuk mengangkat material berat sudah dilakukan saat tsunami Aceh 2004. Kala itu, gajah dikerahkan untuk membersihkan puing-puing dan membuka akses yang tertimbun reruntuhan. Gajah-gajah itu merupakan satwa binaan yang terbiasa bertugas dalam mitigasi konflik dan operasi lapangan di medan berat.
Sebagian orang mungkin melihat ini sebagai hal biasa, sebagai “tenaga tambahan” yang kebetulan tersedia. Namun jika kita melihat lebih dalam, adegan itu sesungguhnya adalah potret paling nyata dari hubungan kita dengan alam, ketika manusia merusak tanpa ragu, tetapi alam masih memilih untuk menolong. Padahal, gajah-gajah ini adalah korban langsung dari pembabatan hutan yang selama puluhan tahun terus berlangsung. Habitat mereka menyempit, jalur jelajah tercerai-berai, dan konflik dengan manusia meningkat drastis. Kita menebang pepohonan, mengangkut kayunya, membangun jalan, dan membuka perkebunan, sementara mereka, penghuni asli hutan kehilangan rumahnya selapis demi selapis.
Secara teknis, gajah dilatih untuk tugas berat di medan sulit dan seringkali lebih aman dibanding alat berat di kawasan sensitif. Namun, ada batas stres pada hewan, risiko cedera, dan potensi konflik jika tidak dikelola dengan standar kesejahteraan tinggi. Institusi konservasi menekankan bahwa pengerahan hewan harus disertai protokol kesehatan, jeda istirahat, dan penghitung risiko yang matang. Di sisi kebijakan, ini juga menuntut rencana penanganan bencana yang mengintegrasikan konservasi, mengurangi kebutuhan untuk “meminjam” satwa sebagai solusi darurat. Gajah-gajah di Pidie Jaya telah mengajarkan satu hal penting bahwa alam tidak menyimpan dendam, tetapi ia menyimpan pelajaran. Pelajaran tentang keseimbangan, tentang saling menjaga, dan tentang batas-batas yang tidak boleh kita langgar seenaknya. Jika hewan yang kita sebut hama saja bisa memberikan pertolongan, mengapa kita yang mengaku berakal terus mengulang kerusakan yang sama?
Kasus Pidie Jaya, Aceh ini mengajarkan beberapa langkah yang harus diperkuat oleh penegakan hukum terhadap pembalakan dan perambahan hutan, restorasi daerah tangkapan air, perencanaan tata ruang yang memperhitungkan aliran sungai, serta program pelibatan komunitas yang memberi alternatif mata pencaharian selain deforestasi. Pemerintah daerah dan pusat perlu menindak tegas pelaku ilegal serta mengalokasikan anggaran mitigasi bencana dan rehabilitasi habitat. Selain itu, transparansi penggunaan gajah tujuannya, durasi, dan kondisi kesejahteraannya harus dilaporkan ke publik agar aksi darurat tak berubah menjadi eksploitasi yang dinormalisasi.
Gajah yang mengangkat gelondongan kayu di Kabupaten Pidie Jaya layaknya cermin retak, ia memantulkan citra manusia yang kini bergantung pada makhluk lain untuk memperbaiki kenangan alam yang telah dilenyapkan sendiri. Aksi itu menyentuh nurani, menyadarkan kita bahwa solusi jangka pendek wajib diiringi dengan tindakan pencegahan jangka panjang. Jika kita benar-benar peduli pada keselamatan manusia dan kelestarian satwa, suara kita harus menuntut perubahan pola pengelolaan lahan, penegakan hukum lingkungan, dan investasi nyata pada mitigasi bencana yang berorientasi ekologi. Hanya dengan begitu, kita tidak lagi melihat gajah sebagai “alat” untuk menambal kesalahan kita, melainkan sebagai makhluk yang berhak hidup aman, sejahtera, dan tak lagi dipanggil ketika kita sibuk memperbaiki apa yang kita rusak.































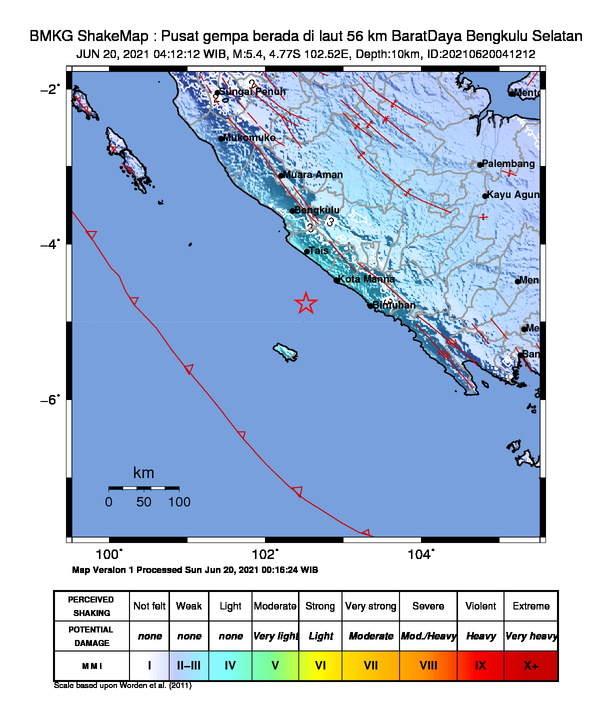








0 Comments