Oleh : Hanum Zalsa Bila (2310421003) Departemen Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Andalas
Hujan deras kembali mengguyur lereng Bukit Barisan di Sumatera, tak kenal jeda, membasahi tanah yang dulu dipeluk akar-akar pohon. Dulu, pepohonan itu berperan seperti spons besar menyimpan air hujan, menahannya perlahan, melindungi kita dari luapan. Sekarang banyak dari pohon-pohon itu sudah hilang ditebang liar, digantikan kebun atau lahan terbuka. Air pun tak lagi diserap ia mengalir deras bersama lumpur, batu, dan potongan kayu, berkumpul dan berubah jadi galodo banjir bandang yang datang tanpa ampun. Rumah hanyut, jembatan ambruk, jalur komunikasi terputus, dan hidup warga seketika berubah kacau. Bukan hanya rumah yang rusak, tapi harapan, rasa aman, dan rasa percaya bahwa alam siap melindungi kita. Bencana ini bukan sekadar curah hujan ekstrem, ia adalah amarah alam setelah janji-janji manusia diingkari.
Deforestasi di Sumatera telah berlangsung bertahun-tahun, terutama pada daerah hulu sungai dan lereng pegunungan. Aktivitas penebangan liar, alih fungsi hutan untuk perkebunan dan pertambangan, serta lemahnya pengawasan menyebabkan kawasan resapan air semakin berkurang setiap tahun. Penelitian hidrologi menunjukkan bahwa perubahan tutupan lahan secara signifikan meningkatkan volume limpasan permukaan (runoff) dan mengurangi kemampuan tanah menyerap air, sehingga memperbesar risiko banjir bandang (Haryani et al., 2022). Studi lainnya menyebutkan bahwa hilangnya vegetasi hutan dapat meningkatkan nilai runoff hingga tiga kali lipat dibandingkan kawasan yang masih memiliki hutan utuh (Putra & Ramadhan, 2021). Ketika pohon ditebang, struktur tanah melemah dan kehilangan daya ikat, sehingga saat hujan deras turun, tanah mudah terkelupas dan ikut terbawa aliran air menuju pemukiman.
Dampak deforestasi pada daerah aliran sungai (DAS) juga mempercepat sedimentasi. Sungai-sungai di Sumatera yang dahulu dalam dan stabil kini dangkal oleh lumpur hasil erosi. Penelitian DAS di Sumatera Barat menunjukkan bahwa wilayah dengan deforestasi lebih dari 25% mengalami peningkatan sedimentasi hingga 60%, yang membuat kapasitas sungai menurun drastis (Sofyan et al., 2020). Ketika hujan datang, sungai yang dangkal itu tidak mampu menampung debit air yang tinggi, sehingga meluap dan berubah menjadi galodo yang membawa material besar seperti kayu dan batu. Fenomena ini sejalan dengan temuan global bahwa hilangnya tutupan hutan di hulu DAS mempercepat pembentukan banjir bandang, terutama di daerah curam seperti Bukit Barisan (Ives & Messerli, 2017).
Ketika galodo terjadi, dampaknya tidak hanya berupa kerugian material tetapi juga trauma sosial yang mendalam. Rumah warga tersapu dalam hitungan menit, jembatan yang menjadi akses utama putus total, dan fasilitas publik seperti sekolah serta tempat ibadah rusak tertimbun lumpur. Bagi banyak keluarga, kehilangan harta benda hanya sebagian dari luka, yang lebih berat adalah kehilangan anggota keluarga yang terseret arus. Studi kebencanaan mencatat bahwa masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dan lereng curam adalah kelompok paling rentan karena tinggal di daerah yang langsung terkena dampak dari perubahan tata guna lahan di wilayah hulu (Yuniarti et al., 2019). Ironisnya, merekalah yang paling sedikit berkontribusi terhadap kerusakan hutan, tetapi menjadi korban utama dari bencana yang terjadi.
Kita sering menyebut galodo sebagai "musibah alam", padahal banyak bukti menunjukkan bahwa bencana tersebut merupakan konsekuensi dari perilaku manusia. Penebangan liar oleh oknum tidak bertanggung jawab telah lama menjadi penyebab utama kerusakan hutan di Sumatera. Laporan lapangan menunjukkan bahwa banyak penebangan dilakukan secara tersembunyi pada malam hari, melibatkan jaringan pelaku yang sulit ditindak karena lemahnya kontrol dan tumpang tindih izin pemanfaatan lahan (Sari & Nugroho, 2021). Selain itu, konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa perencanaan ekologis turut mempercepat degradasi lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa perubahan ini mengganggu siklus hidrologi dan membuat daerah tersebut lebih rentan terhadap banjir, kekeringan, dan longsor (Gaveau et al., 2016).
Ilmu pengetahuan telah lama memperingatkan kita bahwa hutan adalah penyangga utama dalam mengatur air, tanah, dan iklim mikro. Studi iklim ekologi menyebutkan bahwa tutupan hutan berfungsi sebagai pengatur kelembapan, penyerap air, penahan tanah, serta pengendali erosi. Ketika hutan hilang, semua fungsi itu ikut lenyap (Asdak, 2015). Sayangnya, rekomendasi ilmiah sering kali kalah oleh kepentingan ekonomi jangka pendek. Hutan dianggap sebagai sumber kayu dan lahan, bukan sebagai penopang kehidupan masyarakat.
Kini, dengan semakin seringnya galodo terjadi, sudah saatnya kita menata ulang cara memperlakukan alam. Tindakan pertama yang harus dilakukan adalah menghentikan deforestasi ilegal melalui penegakan hukum yang kuat. Pemerintah perlu memastikan bahwa pengawasan hutan dilakukan secara ketat dan transparan. Selain itu, rehabilitasi hutan pada lereng-lereng curam dan daerah rawan bencana perlu dilakukan secara serius dengan menggunakan tanaman lokal yang memiliki kemampuan mengikat tanah. Pengelolaan DAS juga harus berbasis ekosistem, bukan hanya pembangunan fisik seperti tanggul, tetapi pemulihan kondisi alamiah wilayah hulu. Studi restorasi menunjukkan bahwa rehabilitasi ekosistem hulu dapat menurunkan risiko banjir hingga 40% dalam kurun waktu tiga hingga lima tahun (Rahman & Dewi, 2020).
Masyarakat lokal dan adat harus dilibatkan sebagai penjaga hutan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kawasan hutan yang dikelola masyarakat adat memiliki tingkat kerusakan lebih rendah dibandingkan kawasan konsesi perusahaan (Chazdon & Brancalion, 2019). Selain itu, edukasi mitigasi bencana harus diperkuat agar warga memahami tanda-tanda awal galodo serta jalur evakuasi aman.
Pada akhirnya, galodo bukan sekadar banjir bandang. Ia adalah memo panjang dari alam yang berisi peringatan, teguran, dan konsekuensi dari tindakan kita. Alam tidak membalas dendam, tetapi ia merespons apa yang kita lakukan. Ketika kita merusak hutan, alam kehilangan keseimbangannya. Dan ketika keseimbangan itu runtuh, kita sendiri yang akan merasakan dampaknya. Bencana di Sumatera adalah pengingat bahwa kita harus kembali memegang janji dasar, menjaga alam seperti ia menjaga kita. Jika tidak, galodo berikutnya hanya tinggal menunggu waktu dan tagihan alam nanti mungkin jauh lebih berat daripada yang mampu kita bayar.












.jpg)





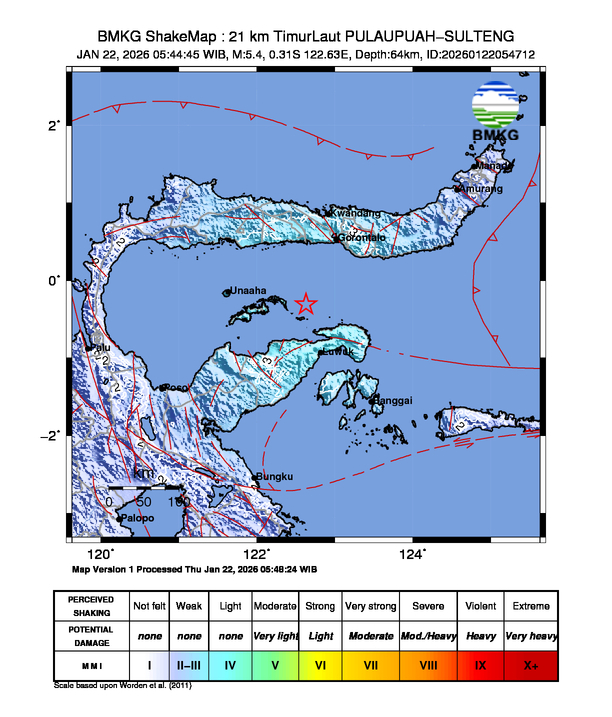
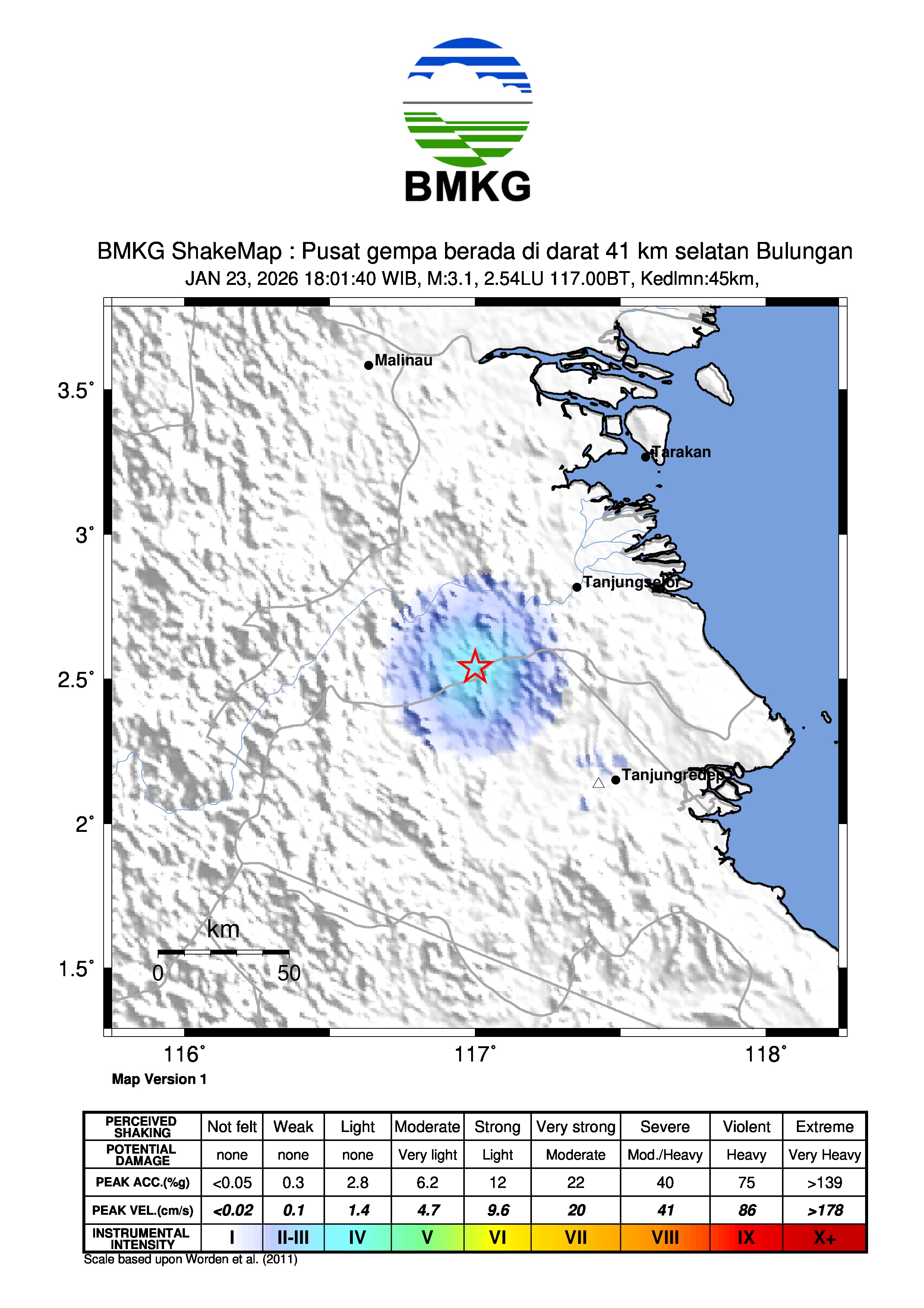






No comments:
Post a Comment