Oleh : Anggie Rega Premesty, 2310711011, Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas anggierega05@gmail.com
Padang dikenal sebagai kota yang hidup berdampingan dengan air. Laut membentang di satu sisi, sungai mengalir di berbagai penjuru, hujan turun dengan intensitas yang tak jarang tinggi. Dalam bayangan itu, air seharusnya tidak pernah menjadi sesuatu yang langka. Namun beberapa hari setelah banjir dan longsor melanda, justru air bersih berubah menjadi kebutuhan paling sulit dijangkau oleh sebagian warganya.
Di Batang Kabung, Kecamatan Koto Tangah, kehidupan berjalan dengan ritme yang berbeda. Keran-keran rumah tinggal dalam keadaan sunyi. Tidak ada bunyi air yang biasa terdengar di pagi hari. Ember-ember diletakkan di sudut dapur dan kamar mandi, kosong, menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Rutinitas harian yang selama ini berlangsung tanpa pikir panjang mendadak harus dihitung, dijadwalkan, bahkan ditunda.
Banjir memang telah surut. Tanah longsor tidak lagi bergerak. Jalanan kembali dilalui kendaraan, aktivitas perlahan terlihat normal. Namun dampaknya tidak ikut pergi bersama genangan. Layanan air bersih belum kembali pulih sepenuhnya, meninggalkan warga dalam kondisi serba terbatas. Di titik ini, waktu terasa berjalan lebih lambat, sementara kebutuhan justru semakin mendesak.
Air tidak lagi diperlakukan sebagai sesuatu yang mengalir bebas. Ia disimpan, dijaga, dan digunakan dengan kehati-hatian yang nyaris berlebihan. Setiap liter memiliki arti. Setiap tetes menentukan apakah hari bisa dijalani dengan sedikit lebih layak. Ada keluarga yang menunda mandi hingga malam, ada yang mencuci pakaian secara bergantian, ada pula yang memasak dengan sisa air yang disisihkan sejak pagi.
Dalam keterbatasan itu, ruang domestik berubah menjadi ruang negosiasi. Aktivitas dasar harus disesuaikan dengan ketersediaan air. Sesuatu yang selama ini dianggap remeh tiba-tiba menjadi pusat dari seluruh pengaturan hidup. Ketika air tidak tersedia, bukan hanya kenyamanan yang terganggu, tetapi juga rasa aman dan martabat sehari-hari.
Kesulitan ini berlangsung berhari-hari. Ketika cadangan air semakin menipis dan layanan belum juga kembali normal, bantuan air bersih akhirnya datang. Bukan dari sistem besar yang bekerja otomatis, melainkan dari inisiatif warga yang bergerak membantu sesama. Gerakan solidaritas yang lahir dari kesadaran sederhana bahwa kebutuhan paling dasar tidak bisa menunggu terlalu lama.
Sebanyak 1.500 liter air bersih disalurkan langsung ke permukiman, menjangkau sepuluh kepala keluarga yang terdampak. Jumlah itu mungkin tampak kecil jika dilihat dari skala kota, tetapi kehadirannya membawa kelegaan yang nyata. Air tersebut cukup untuk menghidupkan kembali aktivitas harian yang sempat terhenti membersihkan diri, mencuci pakaian, memasak makanan meski hanya untuk sementara.
Bantuan itu tidak datang sebagai solusi akhir, melainkan sebagai penyangga di tengah jeda panjang pemulihan. Ia menjadi pengingat bahwa di balik laporan kerusakan, jadwal perbaikan, dan angka-angka resmi, ada kehidupan yang terus berjalan dan harus dipenuhi kebutuhannya dari hari ke hari.
Peristiwa ini menunjukkan bahwa bencana tidak selalu hadir dalam bentuk yang dramatis. Tidak selalu berupa bangunan runtuh atau arus deras yang menghanyutkan. Kadang, bencana justru hadir secara sunyi dalam bentuk keran yang tak mengalir, ember yang tak terisi, dan rutinitas yang harus disusun ulang karena keterbatasan.
Padang, seperti banyak kota lain di Indonesia, hidup di wilayah yang rawan bencana alam. Namun dibalik itu, ada persoalan yang lebih mendasar tentang ketahanan layanan publik. Air bersih bukan hanya soal pipa, instalasi, atau pompa, tetapi juga soal kesiapan menghadapi krisis, kecepatan pemulihan, dan keberpihakan pada kebutuhan paling dasar masyarakat.
Ketika pasokan air terputus, yang paling terdampak bukan mereka yang memiliki cadangan berlebih, melainkan warga yang hidup dari hari ke hari. Di situlah kerentanan paling jelas terlihat. Dan disitulah solidaritas warga mengambil peran, menutup sementara celah yang belum mampu dijangkau sistem.
Namun solidaritas, sekuat apa pun, tidak bisa menjadi tumpuan permanen. Ia bekerja dalam keterbatasan waktu dan tenaga. Ia hadir untuk menolong, bukan menggantikan tanggung jawab yang lebih besar. Bantuan air memang datang, tetapi ketergantungan pada kondisi darurat seharusnya tidak menjadi pola yang berulang.
Air akhirnya mengalir kembali, setidaknya untuk sebagian warga. Tetapi peristiwa ini meninggalkan pertanyaan yang tidak ikut terangkut bersama jerigen dan tangki. Sampai kapan akses terhadap kebutuhan paling mendasar harus bergantung pada keadaan darurat dan kepedulian sesama?
Di kota yang dikelilingi air, kesulitan mendapatkan air bersih seharusnya tidak menjadi cerita yang terus diulang. Sebab air bukan kemewahan, melainkan hak.
Dan ketika hak itu terputus, yang terganggu bukan hanya kenyamanan hidup, tetapi keberlangsungan hidup itu sendiri












.jpg)





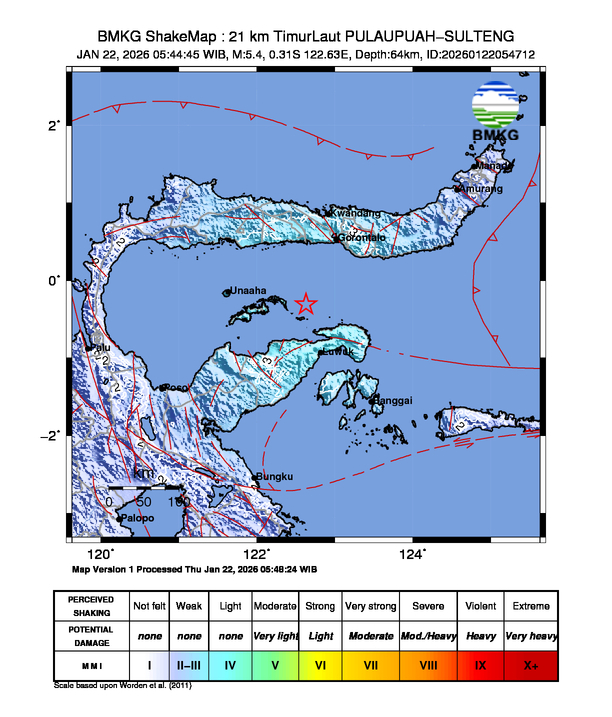
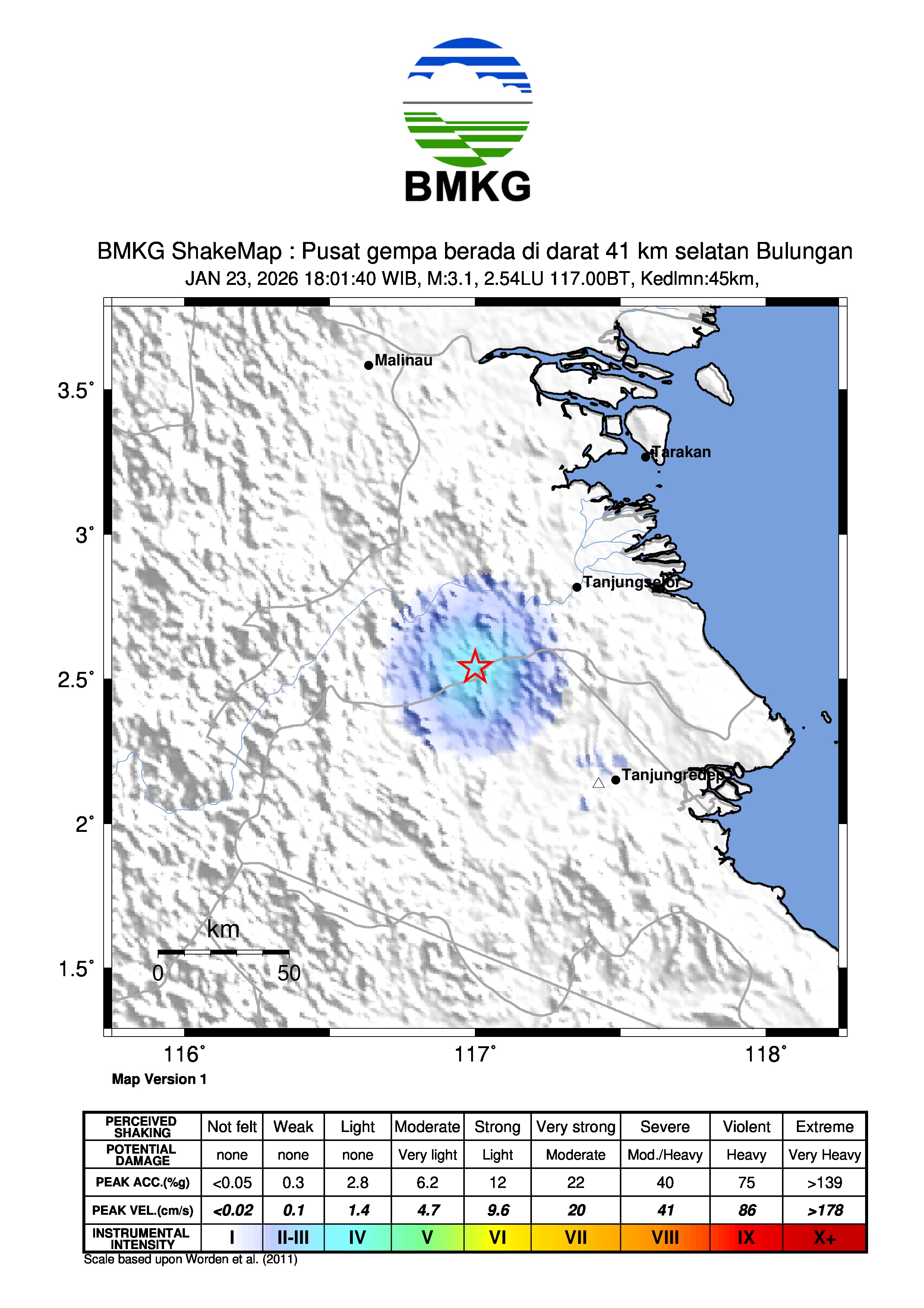






No comments:
Post a Comment