Penulis : Olivia Amanda Putri Mahasiswa Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas
Banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera bukan sekadar peristiwa alam, tetapi jeritan terakhir hutan yang hilang, jejak luka panjang dari deru gergaji yang bertahun-tahun menebas rantai ekologi.
Setiap batang pohon yang tumbang, setiap hektare hutan yang digunduli, perlahan mengikis kemampuan alam menjaga keseimbangannya.
Masyarakat kerap menyalahkan curah hujan ekstrem sebagai pemicu utama, namun fakta alam menunjukkan cerita berbeda, batang-batang kayu bekas tebangan, bukit gundul yang tersingkap jelas, serta aliran sungai penuh lumpur pekat yang menghantam pemukiman, menjadi saksi bisu bahwa kerusakan hutan telah berlangsung jauh sebelum bencana datang.
Dan kini, saat air bah menerjang pemukiman, membawa lumpur, batu, hingga korban jiwa, kita dipaksa menatap kenyataan bahwa tragedi ini bukan datang dari langit, tetapi dari tangan manusia sendiri.
Hulu sungai yang seharusnya menjadi benteng penahan air kini menghadirkan luka ekologis yang mendalam.
Dimana gelondongan kayu yang terseret hingga perkampungan, serta perubahan tutupan hutan yang menunjukkan deforestasi progresif dalam beberapa tahun terakhir.
Kawasan yang dulu tercatat sebagai hutan lindung kini berubah menjadi lahan terbuka yang sangat rentan longsor dan gagal menjalankan fungsi hidrologisnya. Air datang membawa kayu besar dengan amarah yang telah lama dibendung. Kita melihat konsekuensi dari kerusakan yang tidak pernah benar-benar ditangani. Tanpa akar pohon yang mengikat tanah, hujan deras langsung berubah menjadi arus permukaan yang destruktif.
Daerah Aliran Sungai di Sumatera mengalami perubahan serius setelah banjir besar, terutama pada bagian hulu, tengah, dan hilir yang berfungsi sebagai satu sistem hidrologis. Setelah banjir, banyak aliran sungai menunjukkan tingkat erosi dan sedimentasi yang sangat tinggi. Material seperti tanah, batu, dan kayu yang terbawa arus dari hulu mengendap di bagian hilir dan menyebabkan pendangkalan sungai. Pendangkalan ini membuat kapasitas sungai menyusut sehingga sungai semakin mudah meluap pada hujan berikutnya. Selain itu, vegetasi penyangga di tepi sungai banyak yang rusak atau hanyut terbawa arus deras, sehingga membuat system pertahanan rusak. Arus banjir juga mengubah alur sungai, memperlebar badan sungai, bahkan menggeser jalurnya dan merusak lahan pertanian, pemukiman, serta infrastruktur seperti jembatan dan irigasi. Perubahan ini menunjukkan bahwa Daerah Aliran Sungai pascabanjir berada dalam kondisi yang jauh lebih rapuh dibanding sebelumnya.
Deforestasi menjadi penyebab utama mengapa kerusakan Daerah Aliran Sungai setelah banjir di Sumatera menjadi sangat parah. Hilangnya tutupan hutan di hulu membuat air hujan tidak lagi diserap oleh tanah, melainkan langsung mengalir deras sebagai limpasan permukaan yang menyebabkan banjir bandang. Tanpa kanopi pohon yang menahan intensitas hujan dan tanpa akar yang menstabilkan tanah, lereng menjadi mudah tererosi dan material tanah masuk ke sungai, mempercepat sedimentasi. Rehabilitasi hutan dengan tanaman monokultur seperti sawit tidak mampu menggantikan fungsi ekologis hutan alami yang jauh lebih kompleks. Tanaman-tanaman ini memiliki akar dangkal dan tidak membentuk struktur tanah yang kokoh sehingga tetap menghasilkan limpasan tinggi ketika hujan. Kondisi Daerah Aliran Sungai yang sedang rusak, ditambah deforestasi yang terus terjadi, menyebabkan frekuensi banjir meningkat, kualitas air menurun, risiko longsor bertambah, dan ketidakstabilan debit sungai terjadi sepanjang tahun.
Secara keseluruhan, banjir besar di Sumatera bukan hanya peristiwa sesaat, tetapi cerminan kerentanan karna kehilangan perlindungan ekologisnya akibat deforestasi. Ketika hutan hilang, sistem alam kehilangan kemampuan alamiahnya untuk mengatur air, menyerap hujan, dan menahan tanah. Oleh karena itu, banjir tidak lagi menjadi fenomena yang hanya dipicu cuaca ekstrem, melainkan konsekuensi langsung dari kerusakan lingkungan jangka panjang.
Di tengah situasi ini, pemerintah daerah menyatakan sedang mengevaluasi izin pengelolaan hutan serta memeriksa dugaan aktivitas penebangan liar. Namun kritik bermunculan dari berbagai pihak yang menilai langkah tersebut selalu datang terlambat. Penegakan hukum dianggap tidak konsisten, sementara pengawasan lapangan terhadap aktivitas legal maupun ilegal kerap luput dan tidak transparan. Ketika proses penebangan dibiarkan bertahun-tahun, kerentanan ekologis semakin meningkat, dan masyarakat hilir menjadi pihak yang pertama menanggung risikonya.
Tragedi kali ini harus menjadi peringatan keras bahwa pendekatan pembangunan yang mengabaikan prinsip ekologis tidak dapat lagi dipertahankan. Rehabilitasi hutan lindung, restorasi zona hutan, penguatan aturan pemanfaatan lahan, serta penegakan hukum yang konsisten adalah langkah minimal yang harus segera dilakukan. Namun lebih dari itu, Sumatera membutuhkan perubahan paradigma, memandang hutan sebagai infrastruktur ekologis yang sama pentingnya dengan bangunan fisik. Tanpa hutan yang sehat, tidak ada sistem pengendalian bencana yang benar-benar efektif. Tragedi ini kembali menegaskan bahwa kerusakan hutan tidak hanya menciptakan masalah lingkungan, tetapi juga tragedi kemanusiaan. Hutan bukan sekadar kumpulan pepohonan, ia merupakan struktur ekologis yang mengatur penyimpanan air, menahan erosi, menjaga stabilitas lereng, serta melindungi masyarakat dari risiko bencana. Ketika struktur ini dipreteli demi kepentingan jangka pendek, maka keselamatan manusia menjadi harga yang harus dibayar.
Di tengah masyarakat yang masih berduka, satu hal menjadi jelas, membiarkan hutan terus ditebang adalah membiarkan bencana berikutnya disiapkan secara perlahan. Derasnya air mata hari ini adalah konsekuensi langsung dari derasnya air yang tak lagi mampu diatur oleh ekosistem yang seharusnya melindungi. Ketika gergaji bekerja di hulu, dampaknya selalu jatuh di hilir seperti di rumah-rumah yang hanyut, di lahan yang terkubur lumpur, dan pada keluarga yang kehilangan orang mereka cintai. Banjir bandang yang terjadi kali ini seharusnya menjadi momentum refleksi besar bagi kita. Membangun kembali rumah dan infrastruktur penting, tetapi memulihkan integritas ekologis daerah aliran sungai jauh lebih mendesak. Tanpa rehabilitasi hutan hulu, restorasi zona hutan, penguatan penegakan hukum, serta keterlibatan masyarakat lokal dalam pengawasan, bencana serupa hanya menunggu waktu untuk terulang.
Pada akhirnya, derasnya air mata masyarakat Sumbar hari ini lahir dari derasnya aliran air yang tak lagi mampu dibendung oleh hutan yang hilang. Ketika gergaji menumbangkan pepohonan di hulu, yang sesungguhnya terpotong bukan hanya batang kayu, tetapi juga ketahanan ekologis yang selama ini menjaga keselamatan ribuan jiwa di hilir. Bencana ini menjadi “bahasa terakhir” alam untuk menunjukkan bahwa ambang toleransi ekologis telah dilampaui. Pertanyaannya kini adalah setelah melihat begitu banyak nyawa hilang dan wilayah luluh lantak, apakah kita benar-benar siap menjadikan kelestarian hutan sebagai prioritas utama? atau akan kembali berjalan menuju siklus tragedi yang sama hingga suatu hari, gergaji terakhir itu benar-benar menghabisi kesempatan kita mencegah bencana berikutnya. Namun, cerita ini belum berakhir. Di balik gelapnya tragedi, masih ada peluang untuk memperbaiki keadaan. Upaya restorasi hutan, penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan, serta pendidikan ekologis bagi masyarakat menjadi langkah krusial untuk menghentikan siklus bencana ini.
Hutan harus kembali menjadi pelindung, bukan sekadar sumber eksploitasi.












.jpg)





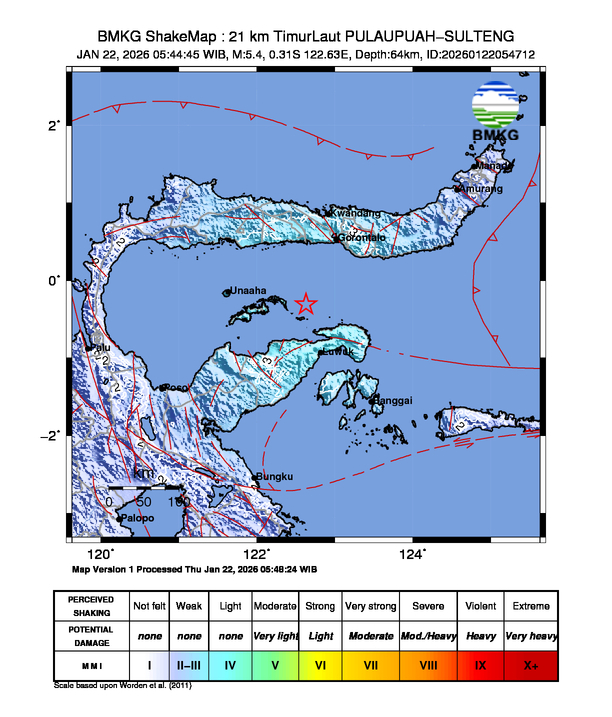
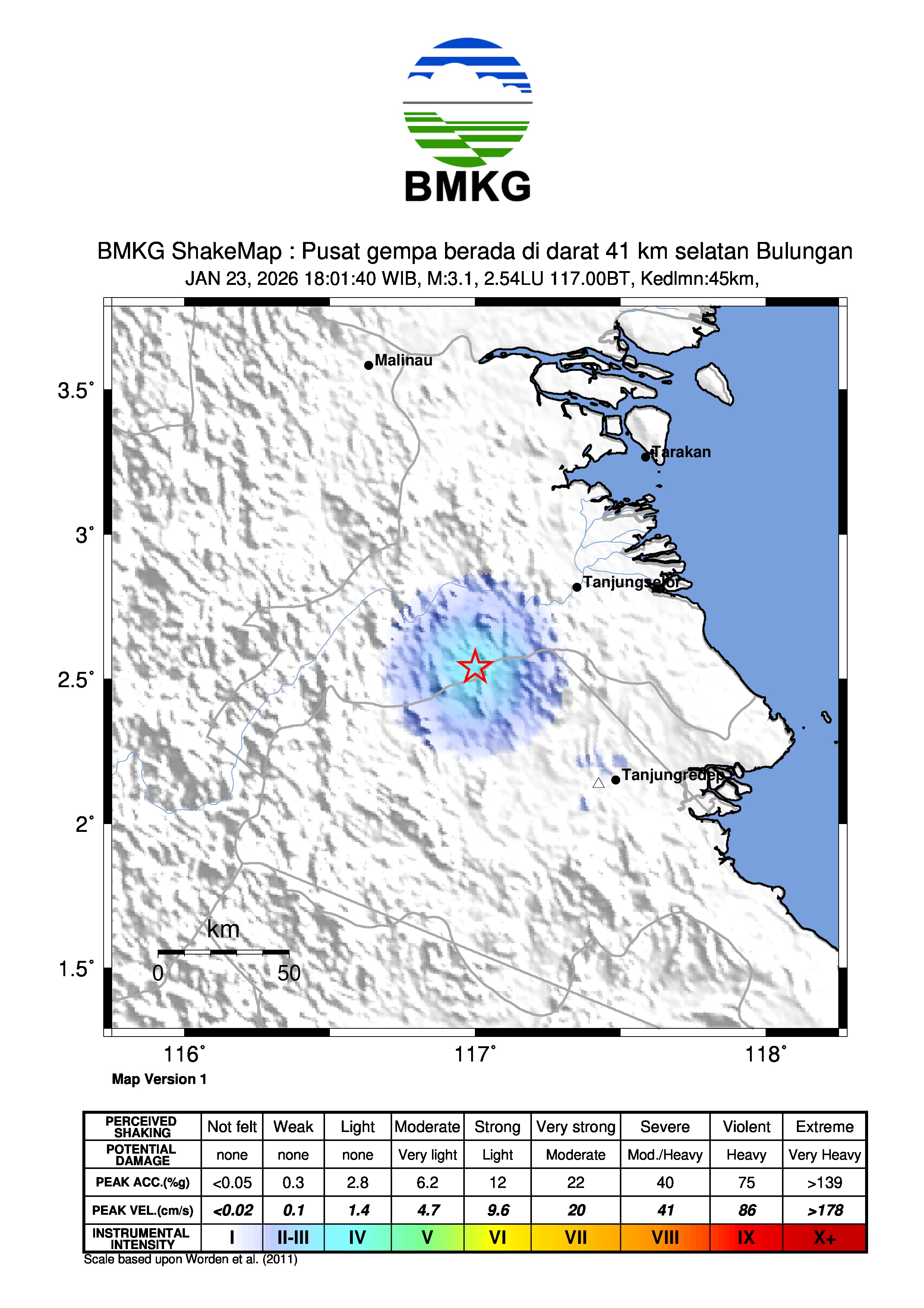






No comments:
Post a Comment