Oleh: M. Wahyu Prima Nanda M mahasiswa ilmu politik universitas Andalas Padang
Dalam setiap pemilu, anak muda selalu menjadi sorotan utama. Mereka dianggap sebagai penentu arah masa depan bangsa, penggerak perubahan, sekaligus kelompok pemilih terbesar. Data KPU menunjukkan bahwa lebih dari separuh pemilih pada Pemilu 2024 berasal dari generasi milenial dan Gen Z. Angka itu membuat partisipasi politik anak muda terlihat tinggi secara kuantitas. Namun, pertanyaan pentingnya: apakah partisipasi itu lahir dari kesadaran politik atau sekadar mengikuti tren saja?
Fenomena yang terlihat di lapangan menunjukkan dua hal yang kontras. Di satu sisi, banyak anak muda yang aktif di media sosial berbicara tentang politik, membahas isu sosial, dan menunjukkan dukungan pada calon tertentu. Namun di sisi lain, tidak sedikit yang bersikap apatis dan menganggap politik sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka. Bahkan, sebagian yang aktif di dunia maya justru tidak terlibat dalam kegiatan politik nyata di dunia offline.
Dalam perspektif sosiologi politik, partisipasi politik tidak hanya diukur dari hadir atau tidaknya seseorang di tempat pemungutan suara. Gabriel Almond dan Sidney Verba menjelaskan bahwa partisipasi politik mencakup semua aktivitas warga negara untuk memengaruhi keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung. Artinya, berdiskusi soal kebijakan publik, mengikuti organisasi sosial, bahkan mengawasi jalannya pemerintahan juga merupakan bentuk partisipasi politik.
Masalah yang muncul kemudian adalah kualitas partisipasi itu sendiri. Banyak anak muda yang ikut memilih tanpa memahami program dan visi kandidat. Mereka mudah dipengaruhi oleh kampanye media sosial yang penuh pencitraan, bukan gagasan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kesadaran politik belum tumbuh kuat. Partisipasi yang hanya berbasis emosi atau ikut-ikutan dapat berbahaya karena membuka ruang manipulasi politik.
Media sosial sebetulnya bisa menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan partisipasi politik anak muda. Sayangnya, ruang digital sering kali dimanfaatkan untuk menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi. Akibatnya, anak muda cenderung memilih “berjarak” dari politik karena jenuh melihat pertengkaran yang tidak berujung. Padahal, menjauh dari politik berarti membiarkan keputusan penting diambil tanpa suara mereka.
Di sisi lain, muncul juga gelombang baru partisipasi yang lebih positif. Banyak komunitas dan gerakan anak muda yang bergerak di bidang sosial, lingkungan, dan pendidikan, yang sebenarnya juga merupakan bentuk partisipasi politik non-elektoral. Gerakan seperti ini menandakan bahwa kesadaran politik anak muda sudah mulai berkembang, meskipun belum sepenuhnya terarah ke jalur formal seperti partai politik.
Tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana mengubah partisipasi politik anak muda dari sekadar simbolik menjadi substansial. Pendidikan politik harus dimulai sejak dini tidak hanya di ruang kelas, tapi juga lewat kegiatan organisasi dan ruang publik yang membiasakan dialog kritis. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan media memiliki peran penting dalam menciptakan ruang yang sehat bagi partisipasi politik generasi muda.
Anak muda perlu memahami bahwa politik bukan sekadar urusan elite, tapi tentang kehidupan sehari-hari: harga bahan pokok, pendidikan, pekerjaan, hingga kebebasan berekspresi. Ketika kesadaran itu tumbuh, partisipasi politik tidak lagi berhenti di bilik suara, tapi terus hidup dalam tindakan dan kepedulian sosial.
Sudah saatnya anak muda berhenti menjadi “penonton demokrasi” dan mulai menjadi pelaku perubahan yang sesungguhnya. Karena masa depan politik Indonesia tidak akan berubah, jika generasi penerusnya hanya menonton dari pinggir lapangan.































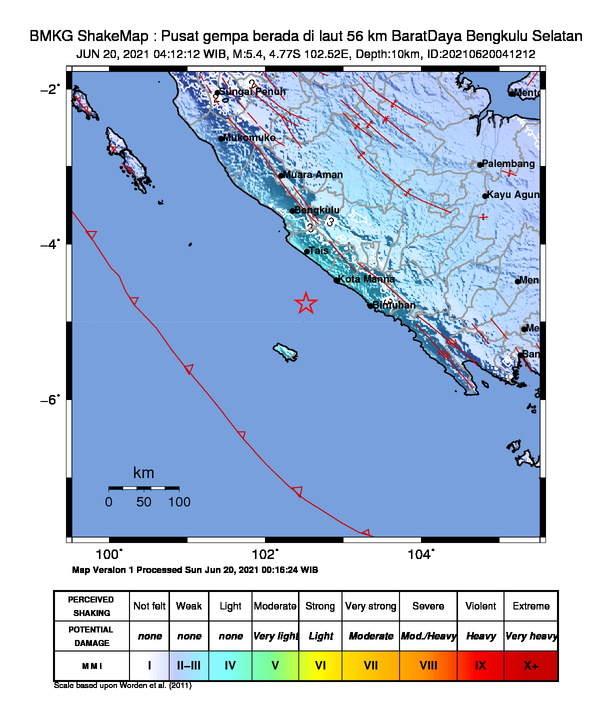








0 Comments