Oleh Alya Saputri Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Andalas
Feminisme merupakan salah satu gerakan sosial paling berpengaruh dalam sejarah modern yang berfokus pada perjuangan kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki. Gerakan ini lahir dari kesadaran kolektif bahwa posisi perempuan dalam struktur sosial, politik, dan ekonomi selama berabad-abad cenderung ditempatkan sebagai pihak yang subordinat. Feminisme tidak hanya berbicara mengenai hak perempuan semata, tetapi juga tentang sistem nilai dan struktur sosial yang menciptakan ketimpangan gender. Dengan kata lain, feminisme adalah upaya sistematis untuk menantang dan mengubah relasi kekuasaan yang menempatkan laki-laki sebagai pusat dominasi dalam berbagai bidang kehidupan.
Menelusuri evolusi gerakan feminisme berarti juga menelaah bagaimana perubahan sosial, politik, dan budaya membentuk cara berpikir masyarakat terhadap isu gender. Setiap fase gerakan ini muncul sebagai respons terhadap ketimpangan struktural yang ada pada zamannya, sekaligus beradaptasi dengan perubahan ideologis dan teknologi yang terjadi.
Artikel ini bertujuan untuk menguraikan perkembangan feminisme dari gelombang pertama hingga era digital. Melalui pendekatan historis dan konseptual, tulisan ini berupaya menelusuri bagaimana tuntutan, strategi, serta bentuk perlawanan perempuan mengalami transformasi seiring dengan perubahan zaman. Dengan demikian, pembahasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika feminisme sebagai gerakan sosial yang terus berevolusi dan beradaptasi dengan konteks masyarakat modern.
Gelombang pertama feminisme muncul pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-20, berakar kuat di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Gerakan ini lahir sebagai reaksi terhadap struktur sosial patriarkal yang menempatkan perempuan sebagai warga kelas dua tanpa hak politik maupun hukum yang setara dengan laki-laki. Pada masa itu, perempuan tidak memiliki hak untuk memilih, bekerja secara bebas, mengakses pendidikan tinggi, atau memiliki harta atas nama mereka sendiri. Kondisi ini mendorong munculnya pemikiran kritis dari sejumlah intelektual perempuan yang mempertanyakan legitimasi sistem sosial yang timpang tersebut
.
Ciri utama feminisme gelombang pertama adalah fokusnya pada aspek hukum dan politik. Perempuan berjuang untuk diakui sebagai warga negara penuh dengan hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Gerakan ini masih sangat didominasi oleh perempuan kelas menengah kulit putih, terutama di dunia Barat, sehingga isu-isu seperti ras, kelas sosial, dan kolonialisme belum banyak mendapat perhatian. Hal ini kelak menjadi bahan kritik dari generasi feminis berikutnya yang menilai bahwa pengalaman perempuan tidak dapat diseragamkan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa perjuangan feminisme gelombang pertama merupakan fondasi penting bagi perubahan sosial yang lebih luas.
Dampak gelombang pertama feminisme sangat besar terhadap perubahan tatanan sosial dan politik di berbagai negara. Keberhasilan perempuan memperoleh hak pilih membuka pintu bagi keterlibatan mereka dalam ranah publik dan pemerintahan. Meski masih menghadapi berbagai bentuk diskriminasi, keberhasilan ini menunjukkan bahwa perjuangan kolektif perempuan dapat mengubah struktur sosial yang telah mengakar selama berabad-abad. Selain itu, gelombang pertama feminisme juga membentuk kesadaran baru bahwa kesetaraan gender adalah prasyarat bagi terciptanya masyarakat yang adil dan demokratis.
Dalam konteks Indonesia, semangat feminisme gelombang pertama memiliki gema tersendiri, meskipun muncul dalam bentuk yang berbeda. Tokoh seperti Raden Adjeng Kartini menjadi simbol awal kesadaran perempuan terhadap pentingnya pendidikan dan kebebasan berpikir. Melalui surat-suratnya yang kemudian dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang, Kartini mengungkapkan keresahan terhadap ketidakadilan yang dialami perempuan Jawa akibat budaya patriarkal dan sistem feodal. Meskipun belum secara eksplisit menggunakan istilah “feminisme,” gagasan Kartini sejalan dengan semangat feminisme gelombang pertama yang menuntut hak perempuan untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pendidikan dan kehidupan sosial.
Latar belakang munculnya gelombang kedua feminisme tidak terlepas dari dinamika sosial-politik pasca Perang Dunia II. Pada masa itu, banyak perempuan yang sebelumnya bekerja di industri dan sektor publik saat perang berakhir kemudian “dipaksa” kembali ke peran tradisional sebagai ibu rumah tangga. Dalam masyarakat Barat, terutama Amerika Serikat, muncul kekecewaan di kalangan perempuan kelas menengah yang merasa kehidupannya dibatasi hanya pada urusan domestik.
Gelombang kedua feminisme memperluas cakupan perjuangan menuju isu-isu kesetaraan di tempat kerja, pendidikan, kesehatan reproduksi, hingga kebebasan seksual. Muncul slogan yang sangat terkenal dalam periode ini: “Dalam ranah akademik, gelombang kedua feminisme juga melahirkan berbagai teori baru yang memperkuat landasan intelektual gerakan ini. Pemikiran Simone de Beauvoir dalam The Second Sex (1949) menjadi tonggak penting. Ia menulis, “One is not born, but rather becomes, a woman,” yang berarti bahwa menjadi perempuan bukanlah kodrat biologis, melainkan hasil konstruksi sosial. Pandangan ini membuka ruang bagi analisis gender yang lebih kritis terhadap struktur kekuasaan patriarki. Selain Beauvoir, muncul pula pemikir seperti Kate Millett dengan Sexual Politics (1970) dan Shulamith Firestone dengan The Dialectic of Sex (1970), yang mengkritik bagaimana institusi keluarga, agama, dan negara mempertahankan dominasi laki-laki.
Dalam konteks Indonesia, feminisme gelombang kedua memiliki resonansi yang kuat terutama pada masa Orde Baru. Walaupun pemerintahan saat itu menekankan peran domestik perempuan melalui ideologi “ibu rumah tangga ideal,” muncul kelompok dan organisasi yang berusaha memperjuangkan peran perempuan di ruang publik. Misalnya, organisasi seperti Kalyanamitra dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mulai mengangkat isu-isu kesetaraan, perlindungan terhadap pekerja perempuan, serta kesadaran hukum. Selain itu, muncul tokoh-tokoh seperti Julia Suryakusuma yang mengkritik konsep “State Ibuism,” yakni ideologi negara yang menempatkan perempuan hanya sebagai pendamping suami dan ibu rumah tangga. Kritik ini menjadi salah satu bentuk perlawanan terhadap sistem patriarkal yang dilegitimasi oleh kebijakan negara.
Gelombang kedua feminisme membawa perubahan mendasar dalam cara masyarakat memandang relasi gender. Gerakan ini berhasil menegaskan bahwa kesetaraan tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga harus diwujudkan dalam kehidupan sosial dan budaya. Namun, seperti halnya gelombang pertama, feminisme tahap ini juga mendapat kritik. Banyak kalangan menilai bahwa gerakan tersebut terlalu didominasi oleh pengalaman perempuan kulit putih kelas menengah di negara Barat, sehingga kurang mencerminkan
keberagaman pengalaman perempuan dari ras, kelas, dan budaya yang berbeda. Kritik inilah yang kelak menjadi dasar bagi munculnya gelombang ketiga feminisme.
Feminisme gelombang ketiga muncul pada awal 1990-an sebagai respons terhadap keterbatasan feminisme gelombang kedua. Jika gelombang sebelumnya menekankan kesetaraan universal antara laki-laki dan perempuan, maka gelombang ketiga lebih menyoroti keberagaman pengalaman perempuan berdasarkan latar belakang ras, kelas, orientasi seksual, dan budaya. Feminisme gelombang ketiga menolak pandangan bahwa ada satu pengalaman “perempuan universal,” karena kenyataannya pengalaman perempuan di berbagai konteks sosial sangat berbeda. Pandangan ini dipengaruhi oleh perkembangan teori postmodern, postkolonial, dan multikulturalisme yang menekankan pentingnya pluralitas dan subjektivitas dalam memahami identitas gender.Gelombang ketiga feminisme juga menekankan pentingnya kebebasan individu dalam menafsirkan identitas perempuan. Jika feminisme gelombang kedua cenderung melihat perempuan sebagai korban sistem patriarki, maka feminisme gelombang ketiga memberikan ruang bagi perempuan untuk mengekspresikan kekuatan dan agensi mereka.
Dengan demikian, feminisme gelombang ketiga dapat dipahami sebagai fase yang menegaskan keberagaman, fleksibilitas, dan keterbukaan dalam memahami isu gender. Gerakan ini menggeser fokus dari tuntutan legal-formal ke arah identitas, budaya, dan pengalaman subjektif perempuan. Feminisme tidak lagi dipandang sebagai satu ideologi tunggal, melainkan sebagai spektrum pemikiran dan praktik yang beragam sesuai konteks sosial masing-masing.































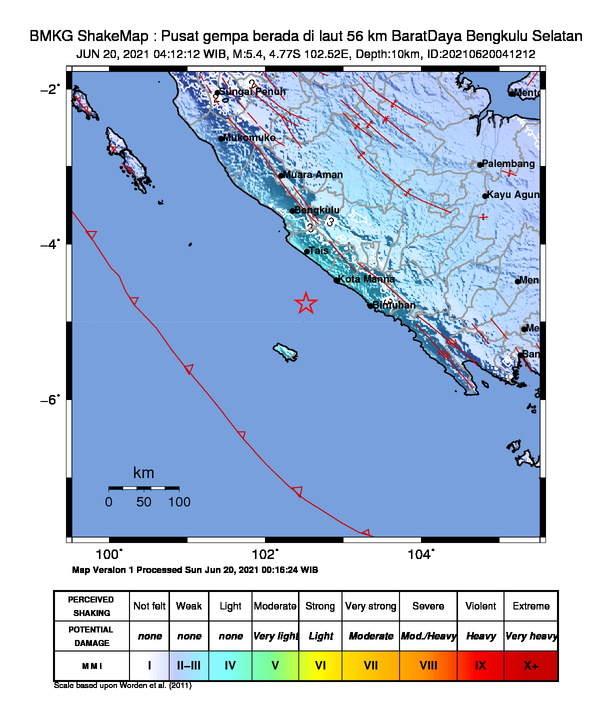








0 Comments