Oleh :Adinda wulandari NIM (2501011035)
Mata kuliah : Bahasa Indonesia. PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN FAKULTAS ILMU KSEHATAN. UNIVERSITAS DHARMAS INDONESIA TAHUN 2025
Dosen pengampu : Dr. Amar Salahuddin, M.Pd
Kita hidup di zaman yang sering disebut sebagai era konektivitas tanpa batas. Dari layar ponsel cerdas kita, dunia berada dalam genggaman.
Kita dapat berbicara dengan kerabat di benua lain melalui panggilan video, berbagi momen kehidupan secara instan di media sosial, dan menemukan komunitas yang memiliki minat yang sama hanya dengan beberapa ketukan jari.
Secara teori, kita tidak pernah sendirian. Namun, ironisnya, salah satu fenomena paling menonjol di abad ke-21 adalah meningkatnya perasaan kesepian dan terasing di tengah keramaian digital. Ini adalah paradoks era digital: kita lebih terhubung secara virtual, namun sering kali merasa semakin terisolasi secara emosional.
Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya kompleks, melibatkan pergeseran cara kita berinteraksi, definisi ulang makna "hubungan," dan sifat dasar teknologi itu sendiri.
Pertama, mari kita bahas tentang sifat interaksi digital. Komunikasi daring, meskipun cepat dan efisien, sering kali dangkal.
Pesan teks dan emoji menggantikan nuansa halus dalam percakapan tatap muka—nada suara, bahasa tubuh, dan kontak mata. Elemen-elemen non-verbal ini sangat penting untuk membangun empati dan keintiman yang mendalam.
Akibatnya, meskipun kita mungkin memiliki ratusan "teman" di Facebook atau pengikut di Instagram, hubungan-hubungan ini sering kali tidak memiliki substansi yang dibutuhkan manusia untuk merasa benar-benar terhubung dan didukung. Kita mengumpulkan koneksi, bukan membina hubungan.
Selanjutnya, media sosial memperkenalkan dimensi perbandingan sosial yang konstan. Platform-platform ini sering kali menjadi panggung di mana orang menampilkan versi terbaik—dan paling dikurasi—dari kehidupan mereka.
Foto liburan yang sempurna, pencapaian karier yang gemilang, dan hubungan yang tampak tanpa cela membanjiri lini masa kita. Secara tidak sadar, kita membandingkan kehidupan nyata kita yang penuh dengan kerumitan dan kegagalan dengan sorotan editan kehidupan orang lain. Kesenjangan antara realitas kita dan fantasi digital mereka dapat memicu perasaan iri, rendah diri, dan yang terburuk, isolasi. Kita merasa bahwa semua orang bersenang-senang atau sukses, kecuali diri kita sendiri.
Paradoks ini juga diperparah oleh cara teknologi memengaruhi durasi dan kualitas perhatian kita. Notifikasi yang terus-menerus—cahaya kecil yang berkedip, getaran singkat—melatih otak kita untuk mencari gratifikasi instan dan mengalihkan fokus kita. Kita jarang hadir sepenuhnya dalam momen apa pun, baik saat makan malam bersama keluarga, menonton film, atau bahkan saat berbicara dengan teman.
Kehadiran fisik mungkin ada, tetapi perhatian mental sering kali terbagi antara dunia nyata dan umpan digital yang tak pernah berakhir. Ketiadaan kehadiran penuh ini merusak kemampuan kita untuk menjalin ikatan yang kuat dan bermakna.
Selain itu, kemudahan akses terhadap hiburan digital sering kali menjadi pengganti interaksi sosial yang sesungguhnya.
Daripada pergi keluar untuk bertemu teman baru atau bergabung dengan klub komunitas, kita dapat menghabiskan malam dengan nyaman menonton serial TV, bermain game daring, atau menjelajahi internet.
Meskipun kegiatan ini bisa menyenangkan dan menenangkan, mereka sering kali merupakan bentuk pelarian pasif yang tidak memenuhi kebutuhan mendasar manusia akan koneksi yang aktif dan timbal balik.
Lantas, apakah solusinya adalah membuang semua teknologi dan kembali ke era yang lebih sederhana? Tentu saja tidak realistis, dan juga tidak diinginkan. Teknologi telah membawa banyak manfaat luar biasa bagi masyarakat.
Kuncinya terletak pada kesadaran dan keseimbangan—penggunaan teknologi yang disengaja, bukan konsumsi yang pasif.
Kita perlu memprioritaskan kualitas di atas kuantitas dalam hubungan kita.
Alih-alih mengejar jumlah pengikut, kita harus berinvestasi dalam beberapa hubungan dekat yang tulus. Ini berarti mengesampingkan ponsel saat sedang bersama orang lain, melakukan percakapan yang mendalam tentang hal-hal nyata, dan bersedia untuk rentan. Keintiman tumbuh dari pengalaman bersama yang otentik, bukan dari "suka" di media sosial.
Penting juga untuk mendefinisikan ulang apa arti "koneksi."
Koneksi sejati bukanlah tentang mengetahui apa yang dimakan teman lama Anda untuk makan siang; itu tentang memiliki seseorang yang dapat Anda hubungi saat Anda menghadapi krisis, atau berbagi kegembiraan dan kesedihan tanpa takut dihakimi.
Paradoks era digital bukanlah tentang teknologi yang jahat, melainkan tentang bagaimana kita membiarkan teknologi mendikte perilaku dan kesejahteraan emosional kita. Kita memiliki kendali atas alat-alat ini.
Dengan menggunakan media digital secara bijak—sebagai pelengkap interaksi kehidupan nyata, bukan sebagai pengganti—kita dapat mulai menutup kesenjangan antara konektivitas virtual yang meluas dan kesepian emosional yang mendalam. Pada akhirnya, manusia tetaplah makhluk sosial yang membutuhkan sentuhan fisik, suara tawa yang tulus, dan kehadiran nyata untuk bisa berkembang.












.jpg)





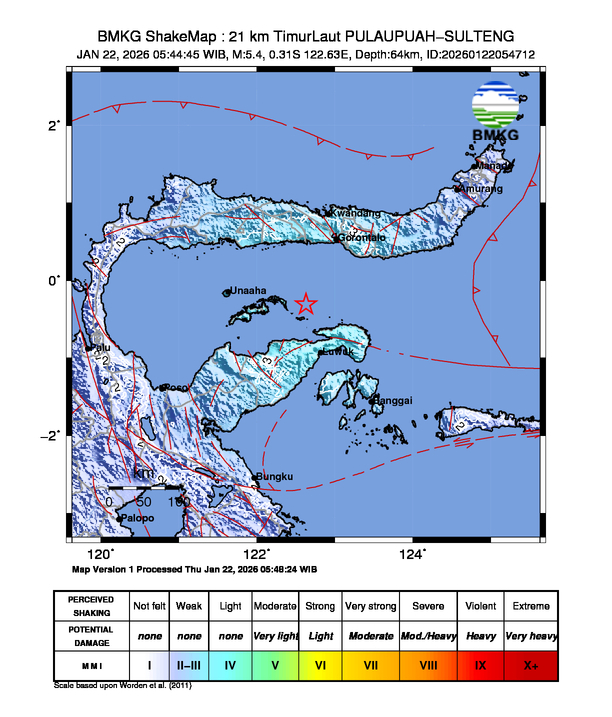
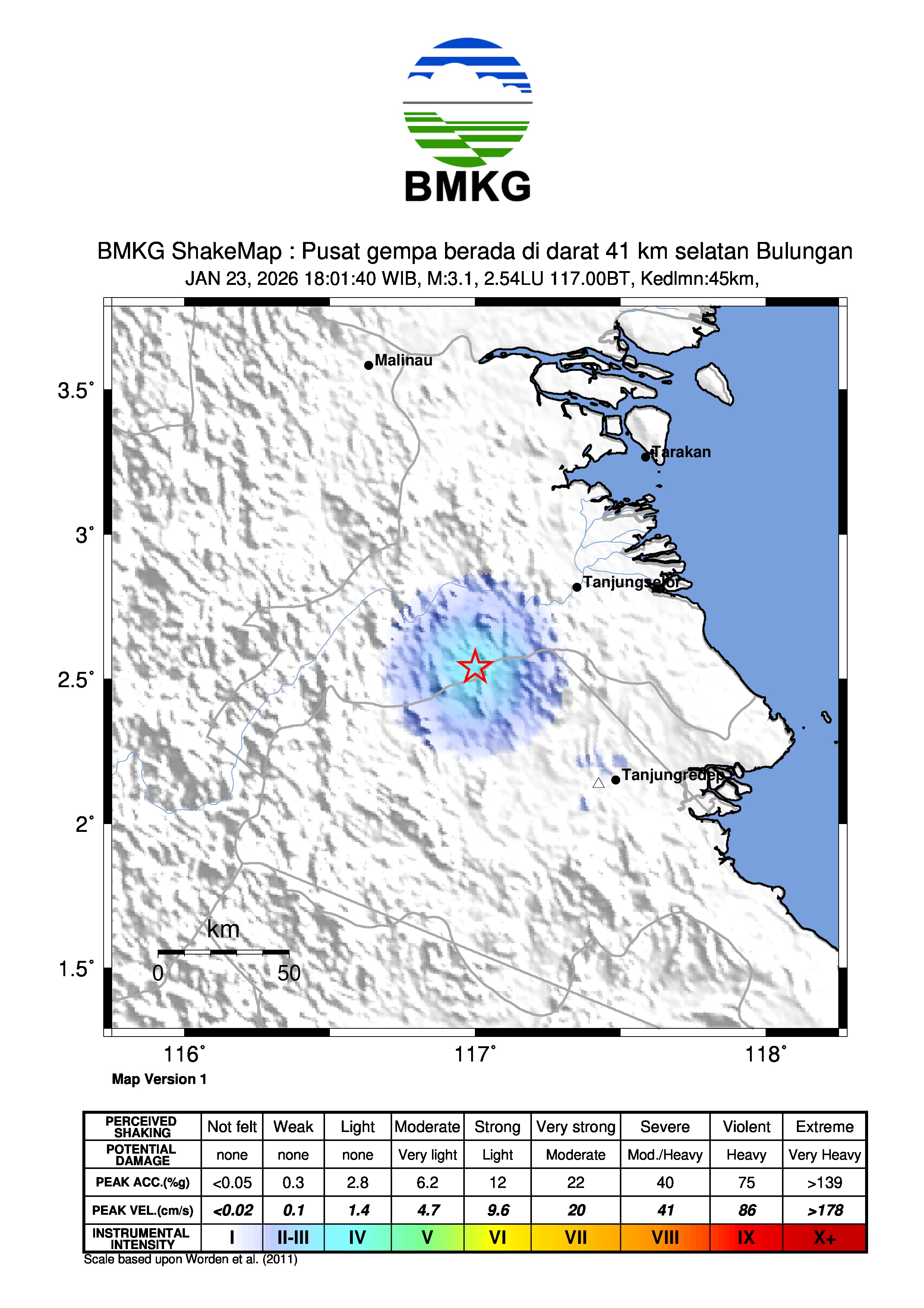






No comments:
Post a Comment