Penulis:Obral Chaniago
Di bawah langit Amerika yang biru pucat, enam anak muda asal Indonesia berdiri tegak. Bukan mengenakan batik atau seragam cokelat kebanggaan pertiwi, melainkan dibalut loreng camouflage militer Amerika Serikat. Di pundak mereka, bukan Garuda yang bertengger, melainkan bintang dan garis yang berkibar dalam diam.
Mereka adalah potret generasi Z--jiwa-jiwa berusia dua puluh yang membawa mimpi di dalam koper, terbang melintas samudera bukan untuk sekadar berwisata, melainkan menjemput takdir sebagai tentara di negeri asing. Fenomena ini, yang kini riuh di jagat media sosial, adalah simfoni yang sumbang, perpaduan antara decak kagum akan keberhasilan dan rintihan kehilangan kewarganegaraan.
Ladang Harapan di Tanah Seberang
Bagi mereka, Amerika bukan sekadar peta, melainkan tanah peluang. Di Indonesia, mereka adalah angka-angka dalam statistik pengangguran atau pejuang UMR yang sering kali tercekik beban hidup. Belum sempat mencicipi seragam TNI, Polri, atau menjadi ASN, langkah mereka telah lebih dulu melompat jauh.
Gaji yang menyentuh angka Rp 50 juta per bulan adalah magnet yang sulit ditolak. Di saat standar upah dalam negeri masih merangkak tertatih di tengah carut-marut sistim outsourcing, tawaran dolar adalah fatamorgana yang nyata. Publik pun terbelah. "Ini adalah cara sah mencari hidup," ujar suara-suara di kolom komentar. Namun, di sudut lain, tajam suara seorang pengurus MUI pusat mempertanyakan akar halal dan haramnya pengabdian pada bendera lain, sebuah sentilan yang menambah pekat kabut kontroversi.
Simalakama Konstitusi dan Hati
Namun, di balik gemerlap dolar dan gagahnya seragam, tersimpan pedang Damocles yang siap jatuh. Hukum kita bicara dengan nada dingin, menjadi tentara negara asing tanpa izin Presiden adalah tiket satu jalan menuju kehilangan status warga negara. Indonesia, dalam buku aturannya, tak mengenal pengabdian ganda pada dua tuan yang berbeda.
Ini adalah buah simalakama yang pahit. Jika negara bersikap keras, kita kehilangan putra-putri terbaik yang memiliki nyali baja.
Namun, jika dibiarkan, di mana letak kedaulatan ? Negara seolah belum bersuara, membiarkan industri pers nasional diam seribu bahasa sementara media sosial telah membakar sumbu diskusi.
Haruskah Kita Mempersoalkan Keberhasilan Mereka ?
Sungguh ironis ketika rakyat kita berhasil menembus tembok sulit negara adidaya, bangsa sendiri justru meragu. Namun, persoalan ini bukan sekadar tentang rasa iri atau bangga, melainkan tentang komitmen tentang tanah tumpah darah.
Akankah Indonesia mau menerima mereka kembali jika suatu saat mereka ingin pulang ?
Jika mereka kembali, adakah kursi bagi mereka untuk mengabdi dengan standar kesejahteraan yang serupa ? Ataukah kita akan terus membiarkan permata-mata ini berkilau di mahkota bangsa lain, karena di rumah sendiri mereka tak diberi ruang untuk bersinar ?
Peristiwa ini adalah cermin retak pemerintah. Fenomena enam pemuda dan pemudi (putra-putri) adalah alarm keras bahwa standar hidup dan kesempatan di dalam negeri sedang digugat oleh realitas global. Sebelum bicara tentang nasionalisme yang luhur, mungkin kita perlu bicara tentang perut yang harus diisi dan masa depan yang butuh kepastian.
Di ujung hari, mereka tetaplah anak-anak Indonesia yang merantau. Hanya saja, rantaunya kali ini beresiko menghapus nama mereka dari kartu keluarga besar bernama Nusantara. Sebuah harga yang amat mahal untuk sebuah peluang hidup yang lebih baik.(*).
Catatan Terkait Regulasi:
Untuk memahami lebih lanjut mengenai aturan kewarganegaraan dan sanksi bagi mereka yang bergabung dengan militer asing, anda dapat merujuk pada:
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang dapat diakses melalui laman resmi JDIH Sekretariat Kabinet.
- Informasi mengenai syarat menjadi prajurit di dalam negeri dapat dipantau melalui laman resmi Rekrutmen TNI.(*).












.jpg)





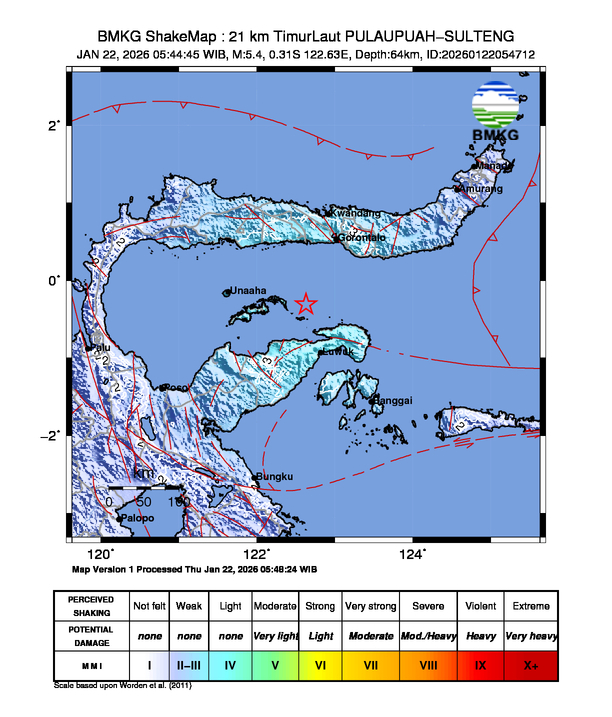
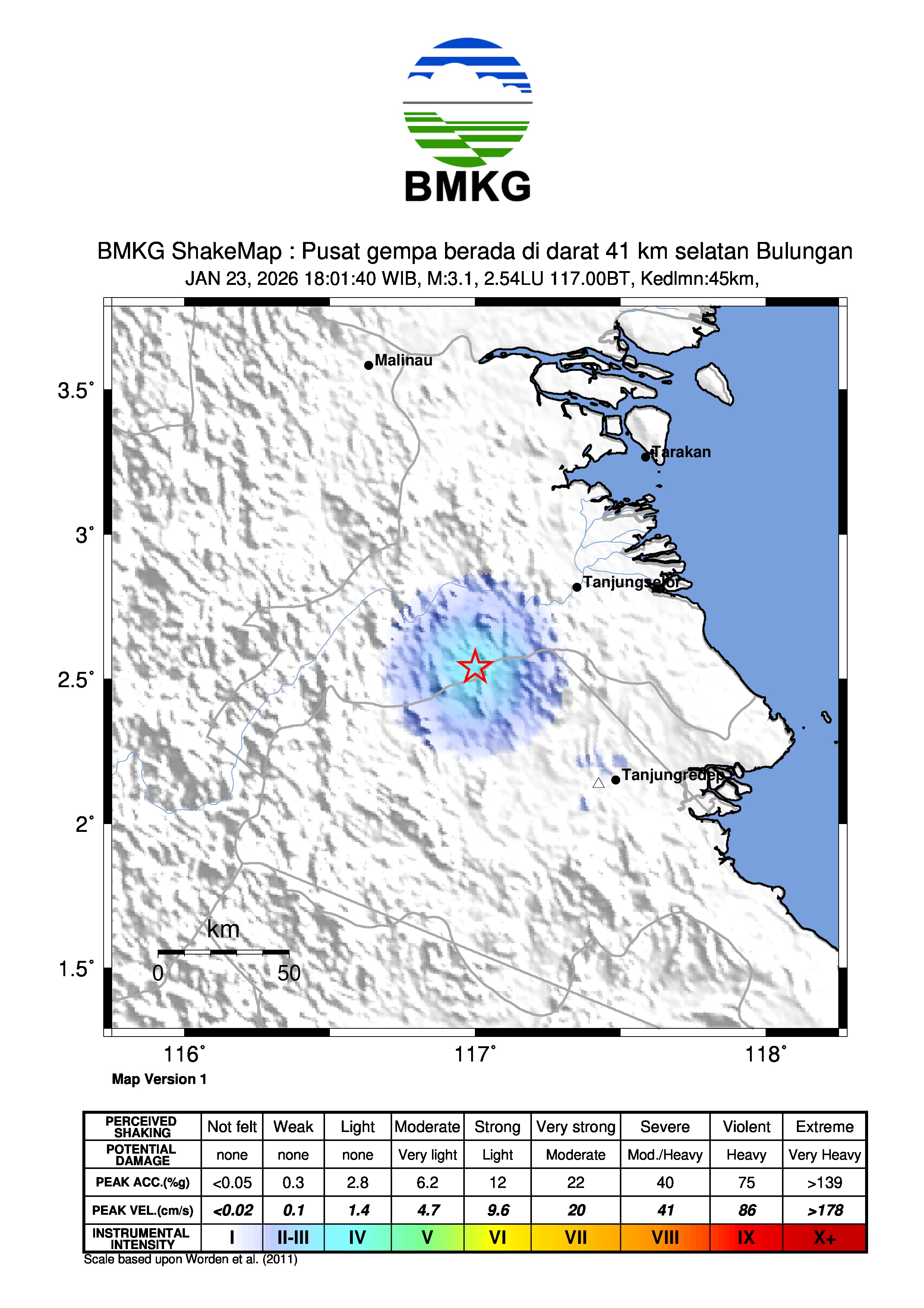






No comments:
Post a Comment