Oleh: Wulandari, Mahasiswa Ilmu Politik, Universitas Andalas
Beberapa waktu lalu, jalanan di Jakarta kembali bergemuruh oleh gelombang demonstrasi. Ribuan massa turun ke jalan menolak kenaikan gaji anggota DPR dan berbagai kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Fenomena ini bukan sekadar luapan emosi sesaat, tetapi cermin dari ketegangan antara rakyat dan elit politik yang kian melebar. Demokrasi yang seharusnya menjadi wadah partisipasi dan kesejahteraan, justru tampak rapuh di tengah ketimpangan ekonomi dan krisis kepercayaan publik.
Menariknya, situasi serupa juga terjadi ribuan kilometer dari Indonesia, di Nepal. Dalam beberapa bulan terakhir, rakyat Nepal turun ke jalan memprotes kenaikan gaji pejabat tinggi negara dan praktik korupsi yang terus menggerogoti keuangan publik. Pemerintah yang lahir dari sistem demokrasi justru dianggap gagal menegakkan nilai-nilai kesetaraan. Di kedua negara ini, demokrasi tampak hidup di atas kertas, tetapi goyah dalam praktik. Rakyat yang merasa tidak didengar akhirnya memilih jalanan sebagai ruang ekspresi terakhir mereka.
Gerakan sosial di Indonesia dan Nepal menunjukkan gejala yang sama: rakyat kehilangan rasa percaya terhadap representasi politiknya. Ketika institusi formal tak lagi dianggap responsif, demonstrasi menjadi simbol eksistensi rakyat. Dalam teori gerakan sosial, kondisi ini disebut sebagai political opportunity structure, yakni ketika ruang politik formal tertutup, maka aksi kolektif informal muncul sebagai alternatif. Di Indonesia, demonstrasi menyoroti kesenjangan antara elit yang hidup dalam kemewahan dan rakyat yang masih bergelut dengan harga kebutuhan pokok. Sementara di Nepal, kemarahan publik mengarah pada korupsi sistemik yang merampas dana sosial dan pembangunan.
Namun, perbedaan mencolok terlihat pada respon pemerintah terhadap tekanan publik. Di Indonesia, meski aksi massa besar terjadi, kebijakan kenaikan gaji DPR masih terus dibahas tanpa transparansi yang memadai. Pemerintah tampak lebih sibuk menenangkan citra politik ketimbang mendengarkan aspirasi substantif rakyat. Sebaliknya, di Nepal, tekanan publik sempat memaksa pemerintah menunda implementasi kenaikan gaji pejabat dan menjanjikan evaluasi kebijakan fiskal, meski banyak yang menilai langkah itu sekadar penenang sementara. Dua respons yang berbeda, namun sama-sama memperlihatkan lemahnya komitmen terhadap prinsip responsiveness dalam demokrasi.
Kedua kasus ini menegaskan satu hal: gerakan sosial masih menjadi napas terakhir demokrasi. Ia hadir ketika saluran aspirasi politik formal tersumbat oleh kepentingan elit. Rakyat turun ke jalan bukan karena benci terhadap negara, tetapi karena ingin mengingatkan bahwa negara ada karena rakyat. Sayangnya, dalam praktik demokrasi modern, partisipasi rakyat sering hanya diminta saat pemilu, bukan saat keputusan penting diambil. Inilah yang membuat demokrasi kita “gelisah” hidup, tapi kehilangan arah moralnya.
Sebagai mahasiswa, saya melihat gerakan sosial di Indonesia dan Nepal bukan sekadar perlawanan, melainkan bentuk check and balance dari bawah. Di tengah kemapanan elit dan melemahnya lembaga representatif, rakyat mencoba merebut kembali ruang politik yang dirampas. Tantangannya kini adalah bagaimana gerakan sosial bisa bertransformasi dari sekadar protes menjadi kekuatan pengawasan yang berkelanjutan, baik melalui partisipasi digital, advokasi kebijakan, maupun pembentukan jaringan masyarakat sipil yang kuat.
Meski gelombang demonstrasi di kedua negara berhasil menarik perhatian publik, hasil nyatanya masih jauh dari kata memuaskan. Di Indonesia, tuntutan agar DPR membatalkan rencana kenaikan gaji belum berujung pada keputusan tegas. Sebagian elite politik justru mengalihkan isu dengan narasi pembenaran administratif dan kebutuhan “penyesuaian kesejahteraan pejabat negara.” Padahal, narasi ini terasa timpang di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil. Aksi massa besar yang berlangsung beberapa hari hanya berbuah janji evaluasi tanpa transparansi kebijakan lebih lanjut. Akibatnya, sebagian masyarakat merasa perjuangan mereka diabaikan, seolah suara di jalan hanyalah gema yang cepat memudar ketika sorotan media reda.
Situasi di Nepal tidak jauh berbeda, meski terdapat sedikit perbedaan dalam reaksi pemerintah. Tekanan publik sempat memaksa parlemen menunda kenaikan gaji pejabat tinggi dan menjanjikan audit terhadap anggaran belanja negara. Namun, banyak aktivis menilai langkah itu hanyalah kompromi politik sementara, bukan bentuk perubahan struktural yang menjawab akar masalah korupsi dan ketimpangan sosial. Rakyat Nepal masih menunggu tindak lanjut nyata, seperti reformasi sistem gaji pejabat atau peningkatan alokasi dana untuk kesejahteraan umum. Dengan demikian, baik di Indonesia maupun Nepal, demonstrasi memang menunjukkan daya hidup demokrasi, tetapi juga menyingkap betapa sulitnya suara rakyat menembus tembok kekuasaan yang semakin tebal.































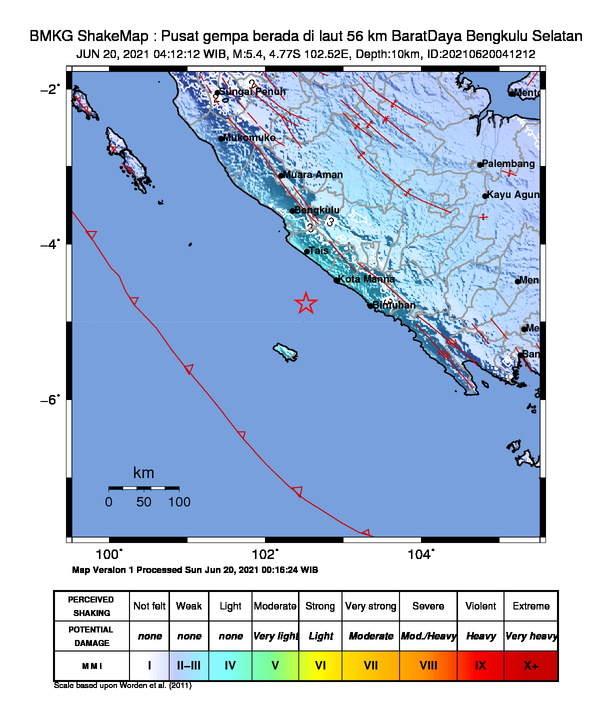








0 Comments