Jejak Generasi Intelektual yang Tersapu
Gelombang Politik 1965
AMSTERDAM, BELANDA, — Sebanyak 263
peserta dari berbagai penjuru dunia, baik secara daring maupun luring,
berkumpul dalam sebuah forum diskusi bertajuk “Menyelami Kehidupan Eksil
Indonesia di Belanda: Generasi Intelektual Bangsa”.
Diselenggarakan oleh Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Belanda dengan PPI
Amsterdam, acara ini menyajikan wawasan mendalam tentang pengalaman eksil
melalui cerita dan pandangan tiga narasumber yang terkait erat dengan peristiwa
tersebut; Lea Pamungkas dari Organisasi Watch65, serta pasangan suami istri
Sungkono dan Wati.
Di awal diskusi, sebuah kalimat puisi yang penuh makna dibacakan oleh
Dini, “Dan mereka yang menimba ilmu yang bisa membuat Indonesia maju, dilarang
pulang”. Penggalan tersebut mewakili kondisi ratusan pelajar Indonesia yang
terjebak dalam pusaran politik Indonesia tahun 1965, diantaranya adalah bapak
Sungkono, yang kisahnya membawa kita ke masa lalu yang penuh kekecewaan.
Sungkono memulai ceritanya dengan nada yang penuh perenungan, “Saya
termasuk 30 mahasiswa yang diberangkatkan ke Rusia oleh Kementrian Departmen
Perguruan Tinggi dan Ilmu pengetahuan, kami diberi gelar Amanat Penderitaan Rakyat
(Ampera), menegaskan kewajiban kami mengabdi kepada negeri setelah
menyelesaikan studi,” ujar Sungkono.
Sebelum berangkat, Bapak Menteri menekankan pentingnya belajar dengan
serius, agar kelak kami dapat memanfaatkan kekayaan Indonesia untuk
kesejahteraan rakyatnya. Sebagai simbol komitmen, kami menerima sebuah gong,
yang seharusnya dikumandangkan sebagai tanda telah menuntaskan misi kami
sepulang ke tanah air,” sambung Sungkono dalam ceritanya.
Namun, tragisnya, gong milik Sungkono tidak pernah berdentang, wujud dari
mimpi dan harapan yang terkubur bersama peristiwa politik yang mengguncang
Indonesia.
Pasca insiden G30S, Sungkono beserta mahasiswa lainnya harus menghadapi
serangkaian pemeriksaan intensif terkait kemungkinan keterlibatan mereka dalam
peristiwa tersebut, meskipun dengan tegas menyatakan ketidaktahuannya serta
tidak terlibat, sikapnya yang menolak untuk mengutuk Presiden Soekarno
diinterpretasikan sebagai tindakan tidak setia terhadap pemerintahan baru.
Akibatnya pada tahun 1966, Sungkono kehilangan identitas dan haknya
sebagai warga negara Indonesia.
Pelajar bukan satu-satunya yang menjadi bagian eksil. Dampak politik
tersebut merambah lebih luas, mencakup setidaknya lima kelompok lain yang
terdampak, termasuk perwakilan Indonesia di organisasi internasional, advokat
demokrasi Indonesia, delegasi negara dalam perayaan kenegaraan, wartawan, serta
para diplomat yang sedang bertugas.
Contohnya, Sutrisno (ayah dari Wati), yang saat itu menjabat sebagai Duta
Besar Indonesia di Vietnam, juga menghadapi pencabutan kewarganegaraan setelah
menolak untuk bekerja di bawah pemerintahan orde baru, konsekuensinya, ia
beserta seluruh keluarga harus kehilangan identitas mereka sebagai warga negara
Indonesia.
Lea Pamungkas, seorang aktivis kemanusian, mengungkapkan, “Eksil
Indonesia tahun 1965 menunjukkan situasi unik yang belum pernah terjadi di
negara lain. Mereka dibuang oleh pemerintah yang sedang berkuasa saat menjadi
representasi Indonesia di luar negeri. Mereka kehilangan hak sebagai warga
negara dan terkurung di negeri lain selama puluhan tahun,” ungkap Lea.
Pada sidang International People’s Tribunal di Den Haag tahun 2015,
dinyatakan ada sembilan pelanggaran HAM berat terkait kejadian 1965. Lea
menambahkan, “Di antaranya, penyiksaan dan propaganda kebencian menjadi
kejahatan yang dialami oleh eksil Indonesia. Tanpa mengalami penyiksaan fisik,
mereka tetap merasakan penyiksaan emosinal yang tak kalah menyakitkan. Bukan
hanya kehilangan identitas tanpa proses hukum yang adil, tetapi menjadi sasaran
stigmatisasi institusional,” imbuhnya.
Sungkono memperkuat pernyataan tersebut dengan menyebutkan praktik KBRI
di Moskow yang menegaskan streotipe negatif kepada para eksil. “KBRI
mengeluarkan surat pencabutan kewarganegaraan secara massal, sekaligus
memperingatkan warga Indonesia lainnya di Uni Soviet untuk tidak memberikan
bantuan apapun, baik moril dan materil,” ungkapnya.
Stigmatisasi tersebut tidak hanya berdampak pada para eksil tetapi juga
menimpa keluarga mereka di Indonesia. Hal yang sama disampaikan Wati, “Saya
memutuskan untuk tidak berkomunikasi dengan kerabat di tanah air, demi
menghindari dampak lebih lanjut terhadap mereka,” ungkapnya.
Para peserta diskusi mengungkapkan bahwa meskipun bertahun-tahun telah
berlalu, stigma terhadap eksil masih berlangsung. “Persepsi negatif tentang
eksil sebagai sosialis, komunis, dan penghianat negara masih ada. Terbukti
dengan penolakan film eksil di sebuah kota di Indonesia. Ini menunjukan bahwa
kita memiliki kebebasan, tetapi belum sepenuhnya Merdeka,” ujar salah satu
mahasiswa peserta diskusi.
Sayangnya, upaya pemerintah dalam menangani isu eksil Indonesia tahun
1965 tampak stagnan. Lea menyoroti, “Presiden Gus Dur merupakan satu-satunya
pemimpin yang telah meminta maaf atas tragedi 1965 dan berjanji akan melakukan
pemulihan termasuk kepada para eksil. Namun sebelum inisiatifnya terwujud, masa
jabatannya telah berakhir,” tegasnya.
Pada tahun 2023, pada era pemerintahan Joko Widodo, pemerintah mengakui
adanya pelanggaran HAM yang berkaitan dengan G30S. Dalam sebuah diskusi yang
diwakilkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD, diadakan pertemuan dengan eksil
Indonesia di Belanda. Agenda utama kegiatan tersebut adalah kemudahan pelayanan
imigrasi kepada para eksil yang ingin kembali ke Indonesia.
Wati, dengan nada kritis, menanggapi, “Penawaran visa tersebut seperti
tindakan simbolis yang kurang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam
menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang kami derita. Kami mengharapkan
permintaan maaf resmi dari negara dan penyelesaiannya secara yudisial - secara
hukum, termasuk pencabutan TAP MPR No XXV/MPRS/1966. Namun, realisasi dari
harapan ini tampak masih jauh dari kenyataan,” ungkap Wati.
Sejak pecahnya kejadian G30S 1965, rasa kecewa, sedih, dan marah terhadap
sikap pemerintah memang tak terelakan. Namun pasangan suami istri tersebut
memilih untuk melangkah maju.
“Saya sempat kuliah kedokteran di Tiongkok, namun tidak dapat
menyelesaikannya karena situasi yang ada. Meskipun tidak bisa menjadi dokter,
saya tidak berhenti mencari alternatif. Dalam pengungsian, saya belajar giat
agar menjadi juru rawat dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seperti
itulah hidup harus dimaknai, bahwa sebuah tragedi tidak seharusnya menghentikan
semangat berusaha,” ujar Wati.
Timur, yang juga merupakan eksil generasi kedua dan hadir dalam diskusi
tersebut, menampilkan karya-karya lukisannya sebagai ekspresi dari ketahanan
hidup. Meskipun menghadapi pengasingan, beliau tetap berusaha memberikan
manfaat bagi orang lain dengan menjadi relawan di panti asuhan di Rusia.
Dengan penuh semangat, Timur berbagi ceritanya, "Kehilangan
identitas, sebuah hak dasar manusia, tidak menghalangi kami untuk tetap
memegang teguh kemanusiaan. Selama saya menjabat sebagai relawan, saya telah
menciptakan sejumlah lukisan yang menggambarkan para lansia bersama hewan-hewan
liar yang tangguh, sebagai simbol sahabat yang menjaga mereka di masa tua."
Melalui pengabdiannya yang tulus, Timur mengajarkan bahwa bahkan dalam
kondisi yang paling menantang sekalipun, masih mungkin untuk memberikan
sumbangsih positif kepada masyarakat.
Sungkono melengkapi, “Saya berasal dari keluarga petani, dan saya
mengambil jurusan teknik mesin dengan harapan dapat berperan dalam meningkatkan
efisinsi pertanian dengan alat modern. Meski impian itu tidak pernah bisa saya
realisasikan, saya berpesan kepada kalian generasi muda : Anda adalah matahari
terbit bagi bangsa Indonesia, sementara kami, para eksil- adalah matahari
terbenam.”
Namun, penting bagi kita untuk memelihara api. Beranilah memperjuangkan
apa yang benar. Meskipun Jalan kalian masih panjang dan ujungnya tidak
terlihat, teruslah berjalan maju demi bangsa Indonesia. Saya, untuk selamanya
akan tetap menjadi orang Indonesia,” pungkas Sungkono.
Ahmad Abyan Aushaf, Sekjen PPI Belanda 2023-2024 menyampaikan, harapan
digelarnya diskusi mengenai eksil bisa membuka ruang-ruang Sejarah yang belum
pernah terpublish.
“Diskusi eksil ini diharapkan bisa membuka pengetahuan generasi muda
tentang peristiwa masa lalu yang selama ini jarang dikuak di ranah publik.
Dengan berdiskusi dan mendengarkan pengalaman langsung dari para eksil, kita
bisa lebih tahu tentang kronologi dan konteks peristiwa saat itu sehingga
membuat kita lebih kritis dan terbuka untuk perbaikan masa depan bangsa,"
ujar Abyan.
Bersamaan dengan pergantian hari menuju malam, acara diskusi tersebut
berakhir dengan suasana haru. Hari itu kami menyaksikan matahari terbenam yang
apinya tak pernah padam. Meskipun peserta diskusi beranjak meninggalkan
ruangan, semangat dan pesan yang dibagikan terus membakar semangat juang,
mengingatkan bahwa esok hari matahari akan terbit kembali.












.jpg)





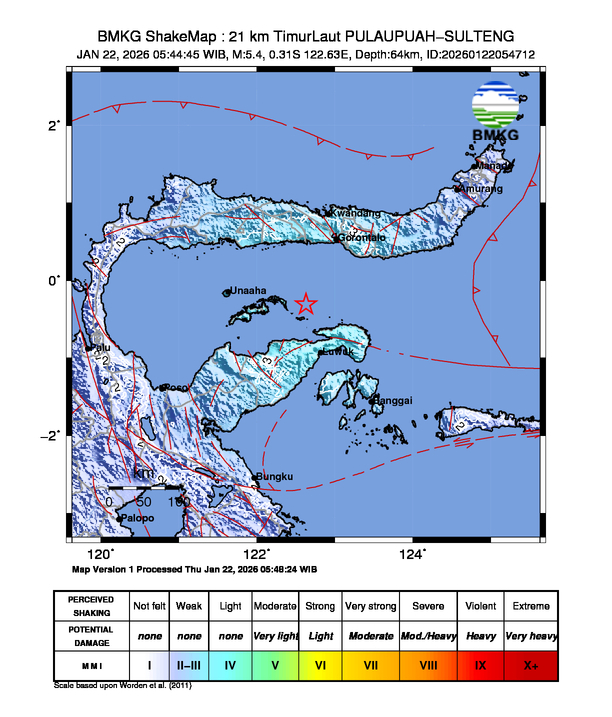
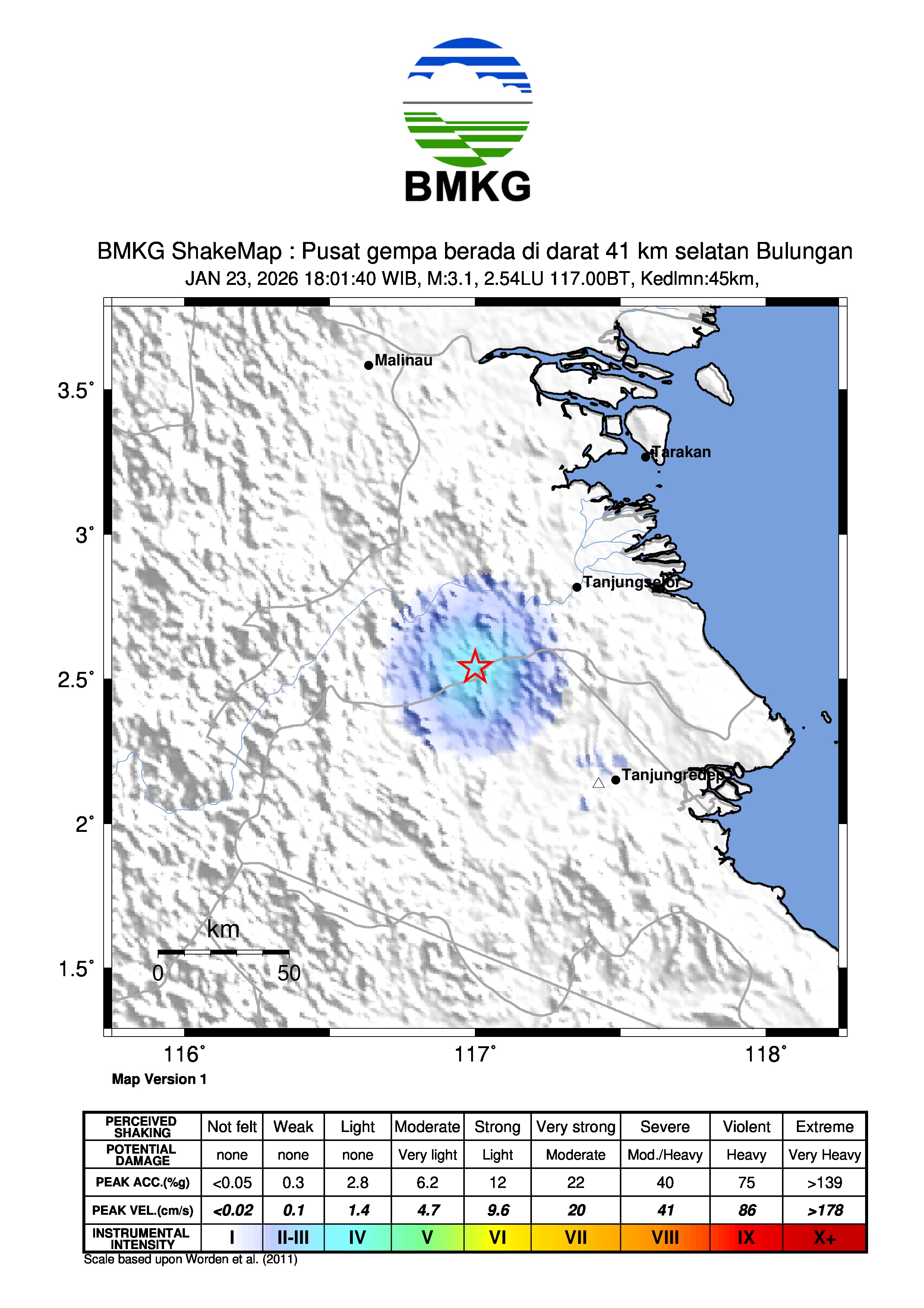






No comments:
Post a Comment