Penulis:Obral Chaniago
Publik Berbisik ke telinga saya, apa kata publik, ini kata publik: ada sebuah ironi dalam struktur ekonomi Sumatera Barat, provinsi yang kaya dengan tanahnya yang subur, budayanya yang unik, dan lautnya melahirkan ikan-ikan gemuk, tetapi terperangkap dalam lingkaran setan ketergantungan pada komoditas mentah. Ketika dunia sedang berlomba-lomba membangun ekonomi berbasis inovasi, Sumatera Barat masih sibuk bertanya, "apa itu diversifikasi ?"
Seperti tokoh Dorian Gray dalam novel Oscar Wilde, ekonomi Sumatera Barat tampak muda dan indah di permukaan, tetapi di baliknya tersimpan keretakan struktural yang mengancam.
Sumatera Barat, seperti banyak wilayah di Indonesia, hidup dari dua nafas, komoditas dan pariwisata.
Minyak, gas, kelapa sawit, karet-semua ini adalah 'emas hijau' yang seharusnya membawa kemakmuran.
Tetapi, apakah kita lupa bahwa komoditas adalah dewa yang capricious ? Harganya naik-turun seperti ombak Mentawai, dan ketika pasar global bergoyah, Sumatera Barat pun ikut linglung.
Pariwisata, di sisi lain, adalah ilusi keindahan yang rentan. Jam Gadang yang menjulang tinggi mungkin memesona, tetapi apakah cukup hanya dengan itu untuk menarik wisatawan di tengah persaingan global ? Ketika Bali dan Lombok sudah bermain di level branding internasional, Sumatera Barat masih sibuk memperbaiki jalan berlobang menuju destinasi wisatanya.
Resesi bukan sekedar angka-angka ekonomi. Resesi adakah cermin dari kegagalan berpikir. Di Sumatera Barat, ada tiga virus yang menggerogoti.
Kapitalisme ekstraktif. Ketergantungan pada eksport komoditas membuat Sumatera Barat menjadi korban dari sistem kapitalisme global yang eksploitatif. Ketika Tiongkok atau Eropa mengalami resesi, permintaan minyak dan CPO anjlok-dan Sumatera Barat pun seperti kehilangan oksigen.
Infrastruktur yang terbelah. Pelabuhan Teluk Bayur yang sempat digaungkan sebagai 'gerbang perdagangan' masih seperti lukisan yang belum selesai.
Sementara itu, jalan-jalan di daerah pedalaman seperti Solok atau Pasaman masih penuh lubang, seolah metafora ketimpangan pembangunan.
Otak yang terasing. Generasi muda Minang lebih memilih merantau ke Malaysia atau Jawa, mencari peluang yang tidak mereka temukan di tanah kelahirannya. Brain drain ini adalah tragedi filosofis, orang-orang cerdas meninggalkan rumah karena rumah itu sendiri tidak memberi ruang untuk berpikir.
Rekomendasi. Membangun ekonomi berbasis akal sehat dan keberanian. Menghadapi resesi, Sumatera Barat butuh lebih dari sekadar retorika pembangunan. Ini adalah waktu untuk bertanya. Apa artinya menjadi bagian dari cita-cita nagari di era post-truth ini ?
Transformasi ekonomi dari komoditas ke nilai tambah. Jangan hanya menjual kelapa sawit mentah. Ubah CPO menjadi biodisel, kosmetik, atau produk farmasi. Jangan hanya mengekspor kopi, tetapi ciptakan brand "Kopi Minang" yang punya cerita dan identitas.
Digitalisasi bukan sekadar gimmick. UMKM harus diajarkan bukan cara menggunakan e-commerce, tetapi juga bagaimana berpikir seperti startup. Bukan sekadar "jualan onlin", tetapi membangun ekosistem inovasi.
Pariwisata berkelanjutan, wisata budaya vs wisata massa. Fokus pada wisata budaya yang mendalam, bukan sekadar spot foto Instagram mobil. Ajak wisatawan untuk memahami filosofi "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah", bukan hanya selfie di depan rumah gadang.
Infrastruktur sebagai proyek filosofis. Perbaiki pelabuhan Teluk Bayur bukan hanya sebagai proyek pisik, tetapi sebagai simbol konektivitas antara tradisi dan modernitas.
Bangun jalan-jalan di pedalaman sebagai metafora perlawanan terhadap ketimpangan.
Kritik, pemerintah yang tidak berani bermimpi besar. Pemerintah Sumatera Barat sering terjebak dalam rutinitas birokrasi yang membosankan. Mereka sibuk membagi anggaran untuk proyek-proyek 'aman', tetapi tidak berani mengambil resiko dengan investasi berbasis inovasi. Ketika dunia sedang berlomba-lomba membangun smart Cities, Sumatera Barat masih sibuk dengan rapat-rapat yang tidak menghasilkan ide.
Ini adalah kritik yang lebih dalam, ketidakyakinan pada potensi diri sendiri. Ketika generasi muda Minang merantau karena tidak percaya pada masa depan di kampung halaman, itu adalah kegagalan sistem yang tidak memberi ruang untuk bermimpi.
Dan, pada muaranya, mimpi Minang di tengah badai global.
Sumatera Barat tidak bisa lagi hidup dari nostalgia kejayaan masa lalu. Jika tidak ada tranformasi struktural, resesi 2024-2025 bukan hanya ancaman ekonomi, tetapi juga krisis identitas. Provinsi ini harus berani bertanya, apakah kita ingin menjadi penonton di tengah perubahan global, atau menjadi aktor yang menulis ulang narasi pembangunan ?
Pilihan ada di tangan kita. Seperti kata filsuf Prancis Albert Comus, "di tengah badai, kita tidak bisa mengubah angin, tetapi kita bisa mengatur layar". Sumatera Barat butuh layar baru, layar inovasi, keberanian, dan keyakinan bahwa mimpi Minang bisa menjadi nyata.(*).












.jpg)





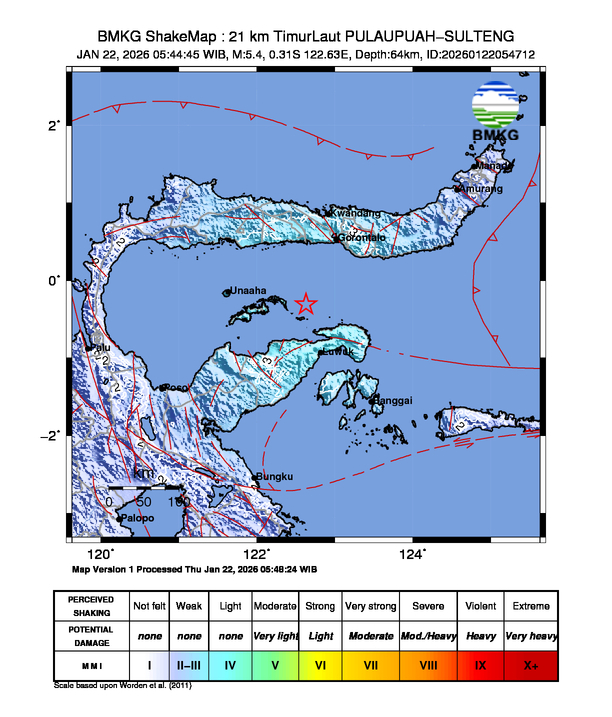
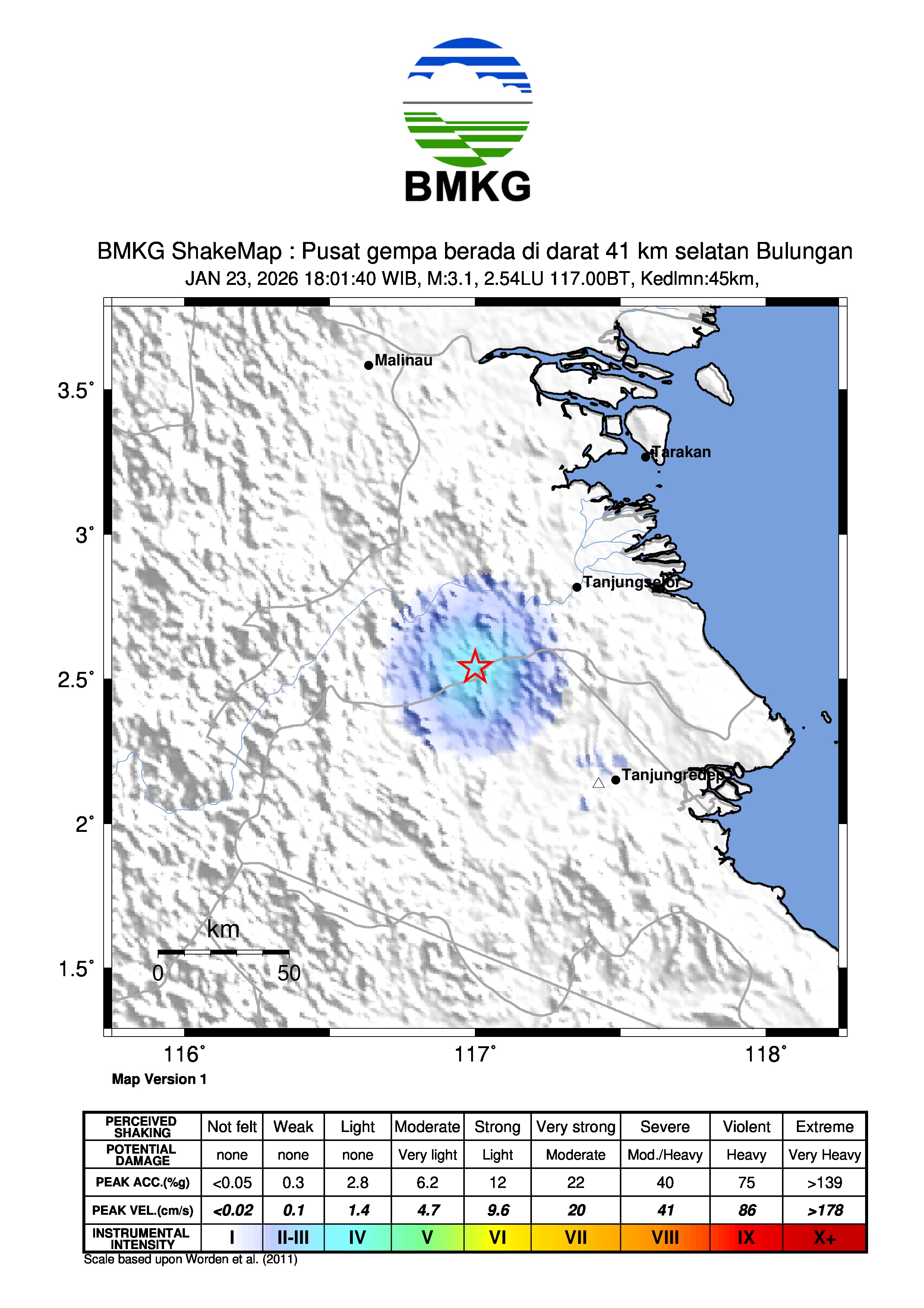






No comments:
Post a Comment