Oleh: Cindila Syafira Pasaribu Mahasiswi Universitas Andalas Departemen S-1 Ilmu Politik
"One-stop service hingga pelayanan publik berbasis Elektronik” yang digaungkan harusnya tak hanya menjadi slogan. Data menunjukkan bahwa negara-negara dengan indeks persepsi korupsi rendah seperti Denmark dan Selandia Baru berhasil mengeliminasi praktik percaloan melalui kombinasi sistem digital yang efisien dan perubahan kultur birokrasi yang fundamental.
*Sebuah realita kontradiktif masih menghantui pelayanan publik Indonesia:* eksistensi calo yang masih ada dan mengakar dimasyarakat. Fenomena ini bukan sekadar anomali, melainkan indikator adanya kesenjangan serius antara cita-cita reformasi birokrasi dan implementasinya di lapangan.
Keberadaan calo adalah antitesis dari good governance dan cerminan kegagalan kita dalam menciptakan sistem yang benar-benar melayani. Setiap rupiah yang mengalir ke kantong calo adalah defisit dalam akuntabilitas publik, dan setiap prosedur yang "dipermudah" melalui jalur informal adalah erosi dalam fondasi good governance yang sedang kita bangun
Reformasi birokrasi harus lebih dari sekadar digitalisasi, ia harus menjadi transformasi menyeluruh yang menjadikan calo sebagai reliket masa lalu, bukan necessity di masa kini. Dengan itu, kita bisa mewujudkan good governance yang lebih dari sekadar jargon belaka tentunya
Indonesia telah mengadopsi sistem e-government yang ambisius dengan menciptakan lebih dari ribuan aplikasi layanan publik digital di berbagai daerah, menganugerahi beberapa desa/kota/kab/prov dalam keterbukaan informasi publik bahkan inovasi daerah yang paling menarik mendapatkan dan anggaran, tapi dibalik indahnya itu semua praktik percaloan masih berkembang biak dibergam instansi-instansi serta menghadirkan kepuasan publik atas pelayanan yang diberikan masih dalam indeks tak puas, hal ini tentunya mengindikasikan kegagalan sistemik dalam transformasi birokrasi.
Menelisik dari laman databoks.katadata.co.id menyebutkan hasil survei Populi Center yang dilakukan terhadap 1.200 responden berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah menyatakan bahwa masalah utama pelayanan publik yang dikeluhkan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan yaitu :
Persyaratan berbelit 11,4%
Lamban 11,3%
Kurang transparan 9,7%
Birokrasi berbelit 9,3%
Sarana tak memadai 8,6%
Biaya mahal 8,4%
Pelayanan tak sesuai 6,2%
Pungutan liar 4,8%
Ketidakjelasan prosedur 3,8%
Tidak responsif 3,6%
Kualitas SDM rendah 3%
Pelayanan tak ramah 2,7%
Lainnya 5,1%
Tidak tahu/tidak jawab 12,3%
Lalu menelaah dari hasil kajian yang dilakukan oleh ORI DIY sejak akhir 2021 sampai dengan awal 2023. Bahwasanya 42,3 persen responden yang gagal mengikuti ujian SIM memilih untuk mencari jasa perantara atau calo, kemudian 34,6 persen memilih untuk membayar ke oknum petugas atau menembak. Kemudian 7,7 persen memilih untuk berlatih kembali, 11,5 persen mencari lembaga kursus, dan 3,8 persen memilih membuat SIM lewat SIM keliling. Mereka mengaku "terpaksa" menggunakan jasa calo untuk memperlancar urusan mereka dikarenakan merasa dipersulit saat membuat SIM.
Sebenarnya tidak hanya pada pembuatan SIM saja, KTP, SAMSAT dan hampir seluruh pelayanan publik dihiasi calo-calo, hadirnya calo ini tak lain dan tak bukan dikarenakan adanya situasi yang sulit "ditembus” di pelayanan publik, situasi yang sulit ditembus adalah tidak wajar. Karena pelayanan publik harus mudah diakses oleh seluruh masyarakat, tanpa pandang bulu dan ini tentunya memang sudah hak semua masyarakat mendapatkan pelayanan yang optimal. Ini jikalau dikaji juga karena budaya lama yang membandel dan di pupuk dengan kurangnya rasa sadar diri baik dari pihak birokrat maupun masyarakat yang cenderung mengeksklusifkan birokrat padahal mereka sudah tugasnya melayani masyarakat dengan sepenuh hati.
Fenomena ini tentunya mencederai prinsip-prinsip good governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Ketika sebuah sistem yang dirancang untuk mempermudah justru "memaksa" masyarakat mencari jalan pintas, kita menyaksikan kegagalan dalam menciptakan clean governance.
Data dari Ombudsman RI menunjukkan bahwa sepanjang 2023, terdapat 3.417 laporan maladministrasi, dengan 24,7% terkait penundaan berlarut dan 18,9% terkait penyimpangan prosedur tentunya hal ini yang memungkinkan masyarakat beralih ke calo padahal pelayanan yang prima adalah hak semua masyarakat Indonesia
*DILEMA : mana yang keliru?*
Di tengah gemuruh modernisasi pelayanan publik melalui e-government, sebuah fenomena klasik ini masih jua bertahan yaitu keberadaan calo, ini menggambarkan betapa kompleksnya permasalahan birokrasi di Indonesia.
Padahal pemerintah telah berupaya mereformasi birokrasi dengan menghadirkan layanan berbasis elektronik yang diklaim lebih efisien, transparan, dan mudah diakses. Walaupun sebenarnya masih banyak yang tidak becus dalam melaksanakan E- Government.
Fenomena eksisnya calo di era digital adalah anomali, hal ini sepertinya dikarenakan: Pertama, layanan publik yang telah didigitalisasi memiliki prosedur yang bertele-tele dan berbelit serta banyaknya aplikasi yang harus diakses ini masih menjadi momok bagi masyarakat. Kedua, adanya "kesenjangan digital" di mana tidak semua lapisan masyarakat mampu mengakses atau memahami sistem online. Ketiga, dan mungkin yang paling mengkhawatirkan, adalah indikasi adanya "simbiosis mutualisme" antara oknum birokrat dengan para calo.
Banyak yang beranggapan bahwa menggunakan jasa calo lebih "efisien" karena dapat mempersingkat waktu dan menghindari kerumitan prosedur. Namun, efisiensi ini adalah efisiensi semu yang justru melanggengkan sistem yang tidak sehat. Biaya tambahan yang dikeluarkan untuk membayar calo sebenarnya adalah "biaya transaksi" yang tidak perlu sehingga membuktikan sebuah indikator bahwasanya pelayanan publik belum berjalan sebagaimana mestinya.
Keberadaan calo di era e-government ini juga bukanlah sekadar masalah teknis, melainkan tantangan budaya dan tata kelola dan juga ialah sebagai alarm yang memperingatkan kita bahwa modernisasi tanpa reformasi mentalitas dan sistem yang menyeluruh hanya akan menghasilkan perubahan superfisial. Ini adalah mimpi buruk, ketika masyarakat yang harusnya tau itu haknya malah larut dalam bobroknya sistem yang di cacatkan demi keuntungan elite-elite birokrasi.
*Implikasi terhadap Tata Kelola Pemerintahan*
Eksistensi calo merupakan parasit yang menggerogoti sendi-sendi tata kelola pemerintahan, eksistensi calo ini tentunya secara langsung menggerogoti 5 pilar utama good governance:
a. Transparansi: Praktik percaloan menciptakan "pasar gelap" informasi dan prosedur. Padahal transparansi, adalah pondasi utama pemerintahan yang bersih.
b. Akuntabilitas: Apabila terjadi suatu hal yang merugikan masyarakat maka sulit melacak kejanggalannya dimana dan bingung meminta pertanggungjawaban karena menggunakan jasa calo, sebab ketika menggunakan calo banyak prosedur resmi yang dilewati.
c. Efisiensi: Akibat memupuk subur para calo, masyarakat terpaksa mau tidak mau harus merogoh kocek untuk biaya tambahan, padahal pelayanan yang baik adalah hak masyarakat, jadinya masyarakat terpaksa membayar lebih demi pelayanan yang prima dan sigap.
d. Efektivitas: Pun akhirnya tujuan reformasi birokrasi yang sudah direncanakan dan menghabiskan banyak anggaran untuk pelayanan optimal jadi terhambat karena beberapa oknum.
e. Keadilan: Apabila selalu memupuk calo maka akan menciptakan ketimpangan akses layanan antara yang "mampu bayar" dan tidak, sebab ditelisik dari data yang ada banyak yang menggunakan calo karena minusnya pelayanan publik.
Sebenarnya ada dampak lebih jauh lagi, praktik percaloan ini dapat memicu kemarahan publik, membuat krisis kepercayaan terhadap pemerintah, dan memperlebar jurang kesenjangan sosial. Percaloan juga bisa dikhawatirkan menjadi pintu masuk bagi praktik korupsi yang lebih besar, membentuk suatu siklus yang sulit diputus. Maka demikian, percaloan tak hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak-hak masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.
*Solusi Sistemik*
1. Simplifikasi Radikal:
Audit dan Eliminasi Prosedur yang tidak perlu menyederhanakan birokrasi secara drastis dengan memangkas prosedur yang tidak relevan atau menghambat pelayanan lalu kalau bisa dengan sistem online.
Contoh penerapan: Mengurangi jumlah dokumen yang harus diurus, memperpendek waktu tunggu, atau menggabungkan beberapa proses menjadi satu lalu mempercepat pelayanan: masyarakat tidak perlu lagi berurusan dengan birokrasi yang berbelit-belit dan mengurangi peluang terjadinya korupsi, semakin sedikit prosedur, semakin kecil pula celah untuk melakukan pungutan liar serta meningkatkan efisiensi, sumber daya dapat dialokasikan untuk hal-hal yang lebih produktif.
Contohnya seperti Singapura, negara ini berhasil mengurangi 60% prosedur birokrasi dalam satu dekade dengan melakukan audit menyeluruh terhadap semua prosedur dan menghilangkan yang tidak diperlukan.
2. Penguatan Pengawasan:
Pembentukan Task Force Khusus untuk Memberantas Praktik Percaloan, dengan Sanksi Tegas bagi Oknum yang Terlibat.
Membentuk tim khusus yang bertugas secara intensif untuk memberantas praktik percaloan.
Tugas Task Force:
Melakukan penyelidikan terhadap laporan atau dugaan praktik percaloan, melakukan operasi tangkap tangan terhadap oknum yang terlibat, bekerjasama dengan lembaga penegak hukum lainnya dan memberlakukan sanksi administratif,pemberhentian dari jabatan, penundaan kenaikan pangkat.
Sanksi pidana, hukuman penjara dan denda bagi pelaku korupsi.
3. Peningkatan Kapasitas:
Program Pelatihan Intensif bagi Aparatur untuk Mengubah Mindset dari "Prosedural" menjadi "Berorientasi Layanan"
Melakukan pelatihan kepada seluruh aparatur untuk mengubah cara pandang mereka terhadap pelayanan publik.
Tujuan Pelatihan ini adalah menanamkan nilai-nilai pelayanan prima,
meningkatkan kompetensi teknis aparatur, membangun budaya kerja yang positif.
Manfaatnya tentu untuk meningkatkan kualitas pelayanan, aparatur akan lebih proaktif dalam memberikan pelayanan.
Lalu meningkatkan kepuasan masyarakat, masyarakat akan merasa lebih dihargai dan terlayani dengan baik.
4. Standarisasi Layanan: Penerapan Standar Waktu Layanan yang Ketat dan Transparan.
Seperti yang sudah diterapkan Korea Selatan dengan Sistem KONEPS: Menetapkan standar waktu yang jelas untuk setiap jenis layanan.
Contoh: Sistem KONEPS di Korea Selatan yang memberikan informasi mengenai waktu tunggu dan prosedur pelayanan secara online.
Manfaatnya meningkatkan transparansi, masyarakat dapat mengetahui secara pasti berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan suatu layanan lalu dapat meningkatkan akuntabilitas, aparatur akan lebih bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugasnya dan memudahkan masyarakat dalam merencanakan waktu pengurusan.
5. E-government
E-gov adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Mimpi indah untuk Indonesia apabila e-gov ini berhasil diterapkan, sebab keterbukaan, kemudahan, layanan prima, cepat dan tanggap lengkap ada didalam konsep E-Gov ini namun sayangnya masih banyak hal yang perlu dibereskan, termasuk transformasi digital/ E-Gov yang seharusnya tak sedangkal pada pengadaan sistem dan konsep saja, tetapi juga mencakup transformasi pola pikir dan budaya kerja birokrasi.
Ketika layanan publik benar-benar efisien, transparan, dan mudah diakses, keberadaan calo akan kehilangan relevansinya dengan sendirinya, dengan catatan masyarakat memang mau menolak hal yang seharusnya tidak ada dan menuntut dengan mengkritisi bahwasanya pelayanan yang baik adalah hak yang seharusnya dipenuhi pemerintah.

































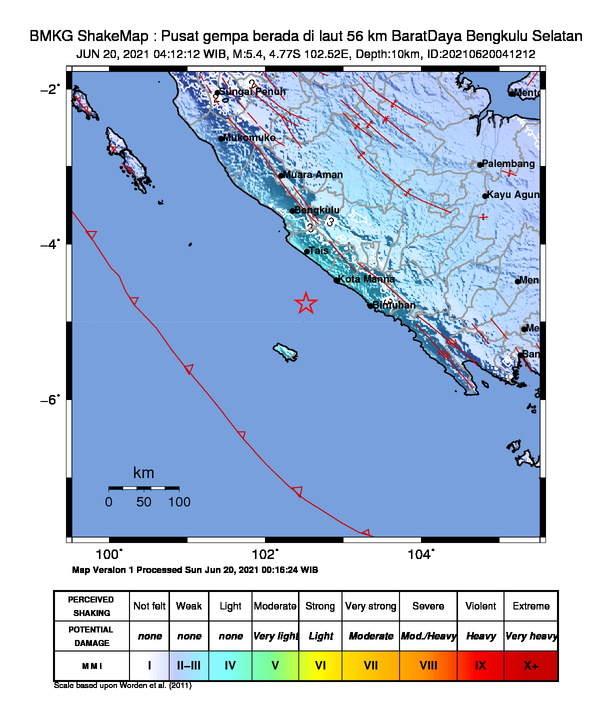








0 Comments