Penulis
a. Aisyah Triana Purnomo
b. Aziztia Ratiwi Subarta
c. Afra Nada Syafira
d. Shierly Luthfia Shalsa
(Mahasiswi Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand)
Dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2007 dalam BNPB manyatakan bahwa bencana adalah rangkaian peristiwa yang mengancam manusia dan disebabkan oleh faktor alam atau non alam maupun faktor manusia yang mengganggu kehidupan manusia lainnya serta dapat mengakibatkan yang dampak besar seperti dapat mengakibatkan adanya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan juga dampak psikologis (Rosyida & Adi, 2017). Seperti yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang No.24 tahun 2007 dimana bencana ini banyak jenisnya, ada bencana yang terjadi akibat faktor alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan lainnya, lalu ada juga bencana akibat faktor non alam seperti kegagalan modernisasi, epidemik, wabah penyakit; serta bencana akibat faktor manusia seperti kebakaran hutan, perang, tanah longsor, banjir, dan lainnya (Widjanarko & Minnafiah, 2018).
Indonesia adalah negara yang termasuk rawan bencana (Maizar, et al., 2021). Indonesia merupakan negara yang seringkali dilanda oleh bencana, selain dari Amerika Serikat, China, Filipina, dan India (CRED, 2018 dalam Proulx & Aboud, 2019). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memiliki data yang menyatakan bahwa ada sekitar 3.721 bencana alam yang terjadi diseluruh Indonesia mulai awal tahun hingga akhir tahun 2019, (Rahmat & Alawiyah, 2020). Ini dikarenakan letak geografis negara Indonesia secara tektonis berada antara pertemuan dari 3 lempeng dunia yaitu lempeng Eurasia, IndoAustralia dan Pasifik, serta Indonesia secara vulkanis adalah tempat jalur dari berbagai gunung api aktif yang disebut juga Pacific ring of fireside atau cincin api pasifik yang menjadi penyebab Indonesia menjadi negara yang rawan akan terjadinya bencana (Hermon, 2014 dalam Hadi, et al., 2019). Berdasarkan pemaparan tersebut kita tahu bahwa wajar saja jika Indonesia sering dianggap sebagai pasar bencana.
Jurnalis merupakan salah satu profesi yang menjadikan bencana yang terjadi sebagai salah satu perhatian mereka (Panuju, 2018). Berdasarkan konsep jurnalisme bencana, terdapat aturan bagaimana seharusnya sikap serta praktik yang harus dilakukan oleh para jurnalis dalam meliput bencana yang terjadi (Hariyanto, 2016). Ahmad Arif (2010, dalam Hariyanto, 2016) menyatakan bahwa ada beberapa hal yang berkaitan dengan jurnalisme bencana, yaitu dimana wartawan harus mengenali seperti apa lingkungan sekitar tempat bencana itu terjadi, lalu ketika meliput peristiwa bencana para wartawan harus merespons peristiwa yang terjadi dengan cepat, kemudian wartawan juga harus terus mengingatkan akan pentingnya mitigasi bencana, wartawan yang terjun langsung ke lokasi bencana harus memiliki persiapan, wartawan harus memahami batas dirinya, wartawan harus dirotasi dalam peliputan bencana (tidak satu dua orang saja yang diterjunkan ke wilayah tersebut), wartawan harus memiliki empati ketika meliput korban bencana, dan wartawan pada saat menampilkan para korban perlu untuk bisa menampilkan tulisan, gambar, ataupun siaran yang menyentuh dan bisa menggalang solidaritas, tetapi tidak sadis, serta mendeskripsikan kehancuran, namun tidak menimbulkan trauma.
Pada tradisi dalam hal jurnalistik, terdapat anggapan bahwa liputan menganai peristiwa bencana sama tingkatannya dengan liputan pada medan perang, hal ini dikarenakan keduanya memiliki risiko yang begitu tinggi bagi jurnalis yang bertugas (Panuju, 2018). Praktik jurnalisme air mata ketika ada bencana yang terjadi yaitu praktik jurnalisme yang menyajikan penderitaan yang dialami korban bencana tersebut secara dramatis (Sukmono & Junaedi, 2018). Seperti yang diungkapkan oleh Nazaruddin (2007, dalam Syarah, dkk, 2020), praktik jurnalisme bencana pada media di Indonesia masih berkutat dengan dramatisasi berita. Tema pemberitaan bencana selalu berkutat pada pemberitaan traumatik dan dramatik, berisi isak tangis, ekspresi sedih, ataupun nestapa korban dengan dalih menumbuhkan solidaritas. Itulah mengapa media Indonesia seringkali dikritik dalam hal peliputan bencana. Alih-alih memberikan informasi yang mencerahkan dan membantu publik, namun justru dianggap sebagai sumber masalah baru. Hal ini pada dasarnya merupakan dilema bagi para jurnalis dari berbagai media, di mana di satu sisi jurnalis harus membuat sebuah berita menarik banyak pembaca, namun di satu sisi yang lain tetap harus apa adanya dan tidak didramatisir. Hal inilah yang dapat membuat sebuah berita dapat dikatakan tidak berkualitas.
Dramatisasi terhadap penderitaan korban ditunjukkan dengan penyajian foto dan video para korban bencana dalam ukuran bingkai close up dengan fokus pada penderitaan yang dialami oleh korban. Praktik ini dilakukan dengan komodifikasi pada korban bencana sebagai materi utama pemberitaan. Akan ditampilkan foto close up dari korban bencana di berbagai media berupa cetak dan daring (online), serta adanya video yang diambil dengan close up oleh para wartawan dari lokasi bencana yang nantinya akan disiarkan melalui berita televisi dan akan menjadi pelajaran yang berharga mengenai pemberitaan tentang bencana (Sukmono & Junaedi, 2018). Tentu hal ini akan menjadi sebuah peristiwa yang amat traumatis bagi berbagai pihak terutama korban seperti mengingat hal ini terjadi secara tiba-tiba, mengerikan, menimbulkan perasaan takut yang mendalam, mengancam keutuhan fisik maupun mental, serta dapat menimbulkan dampak yang sangat membekas pada fisik, pikiran, perasaan, dan perilaku, baik bagi mereka yang mengalami atau menyaksikan peristiwa bencana tersebut (Panuju, 2018).
Korban bencana hanya akan dilihat sebagai magnitude pada sebuah berita. Dimana bencana ini akan semakin dibesar-besarkan seiring semakin banyaknya korban. Peliputan bencana semacam itu dapat meniadakan fakta-fakta potensial. Sebaliknya, ketika menempatkan peristiwa bencana sebagai suatu tragedi maka akan dapat menguatkan gejala traumatis pada masyarakat, baik korban maupun para penerima informasi (Sukmono & Junaedi, 2018). Kurang akuratnya berita yang disampaikan dan apabila cenderung mengedepankan sensasi demi untuk sekedar meraih jumlah target atau khalayak maka bisa disebut sebagai praktik jurnalistik yang kurang mempertimbangkan dampak psikologis bagi khalayak (Sukmono & Junaedi, 2018)
Sehingga wartawan memiliki berbagai dilema, salah satunya di mana ketika di satu sisi mereka harus mencari akses sebanyak mungkin, namun di sisi lain mereka dituntut obyektif (Nugroho & Samsuri, 2013). Kejujuran merupakan hal yang sangat krusial dalam menjalankan profesi wartawan (Nugroho & Samsuri, 2013). Seperti halnya yang terjadi pada penelitian Arif (2010 dalam Sukmono & Junaedi, 2018) yang membahas tentang jurnalisme dan bencana dalam kasus gempa dan tsunami yang terjadi di Sumatera pada tahun 2004. Penelitian ini berfokus pada Aceh sebagai wilayah yang paling terkena dampak bencana. Dalam penelitian tersebut ditunjukkan bahwa media massa di Indonesia saat itu kesulitan untuk mendapatkan akses informasi bencana di hari-hari pertama bencana. Dibanding melaporkan informasi tentang Aceh, media massa Indonesia justru lebih banyak mendapatkan informasi tentang dampak tsunami di India, Thailand, dan Srilanka dan mengolah informasi tersebut menjadi bahan berita untuk audiens di Indonesia. Awalnya, tidak ada berita yang menggambarkan kondisi Aceh sebenarnya dikarenakan telekomunikasi dan transportasi terputus akibat bencana. Kemudian, kondisi tersebut berubah ketika wartawan datang ke Aceh. Media massa dengan cepat dipenuhi dengan gambar mayat bergelimpangan yang berbaur dengan bangkai mobil dan puing, serta rekaman video amatir orang-orang yang berlarian menghindari kejaran air tsunami. Tak hanya itu, televisi pun memperdengarkan teriakan kengerian dan ratapan orang-orang yang kehilangan anggota keluarga yang kemudian diiringi lagu alunan sedih. Tayangan dari lokasi bencana yang disiarkan oleh salah satu stasiun televisi diulang secara terus-menerus dan diikuti dengan gambar penyiar yang menangis. Stasiun televisi lain pun melakukan praktik jurnalisme yang sama, di mana jurnalisme air mata dipertontonkan dengan vulgar oleh media massa dalam peliputan dan pelaporan bencana gempa dan tsunami di Aceh (Sukmono & Junaedi, 2018).
Selain itu, dalam pelaporan bencana ini jurnalis mengalami dilema lainnya, yaitu di satu sisi adanya tuntutan profesi sedangkan disisi lain nilai kemanusiaan juga menjadi peran batin. Pasalnya, peliputan bencana dinilai memiliki risiko dan tanggung jawab tersendiri bagi seorang jurnalis (Hamdan, Abbas, & Astrid, 2019). Kode etik jurnalistik, menurut Ichlasul Amal (Panuju, 2018), merupakan hasil dari pergumulan hati nurani para wartawan. Pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik berarti pengkhianatan terhadap hati nurani profesi wartawan. Pelanggaran ini adalah perbuatan tercela bagi setiap wartawan. Di samping faktor di atas, kompetensi wartawan juga signifikan. Ketika wartawan tidak dibekali dengan pengetahuan serta keterampilan jurnalistik yang baik saat peliputan, akan mengakibatkan karya jurnalistik para wartawan tersebut memiliki potensi menjadi masalah nantinya di masyarakat (Panuju, 2018). Sebagai seorang wartawan dibutuhkan kecakapan dalam aspek jurnalisme dan kebencanaan, serta didukung ketersediaan alat dan perlengkapan yang memadai menjadi pondasi kuat jurnalisme optimis.
Buruknya sebuah karya jurnalistik bukan hanya karena rendahnya pemahaman jurnalis terhadap etika jurnalistik, namun juga hal lainnya seperti persaingan antar media. Industri media online saat ini terus bersaing mencari click dengan segala cara untuk mengoptimalkan search engine, tidak terkecuali dalam hal peliputan bencana. Hal ini tentunya menambah dilemma para jurnalis dalam meliput berita yang berkualitas. Persaingan tersebut bahkan terjadi di antara kanal-kanal yang ada di media. Seperti yang dikemukakan oleh Erwin Dariyanto, salah seorang jurnalis media online Detik.com, dimana ketika kanal news, kanal politik, kanal entertainment sedang terus menerus menulis berita soal banjir dan mendapat banyak click, kanal akan “mati angin.” Itulah sebabnya, kemudian ada berita-berita yang mengaitkan antara banjir dengan artis – sesuatu yang seringkali tidak memiliki kaitan (Pedoman Peliputan Bencana, 2021). Sebagian besar hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pola pemberitaan pada media-media mainstream ketika mereka meliput bencana, dimana mereka cenderung mengikuti pola-pola yang sudah umum yaitu fokus terbesarnya tertuju pada dampak dari peristiwa bencana yang menggunakan perspektif korban, ada berapa banyak korban tewas dan luka, seberapa besar kerusakan materi yang ditimbulkan, dan seterusnya. Media seringkali gagal dalam memperdalam penyebab peristiwa bencana, bahkan kadang justru malah memperburuk situasi (Sanusi, 2018).
Padahal sejatinya, masyarakat yang menjadi korban bencana pada dasarnya tentu menginginkan informasi yang disampaikan media dapat membantu mereka untuk bangkit kembali. Bukan berita yang tidak “berkualitas” dan dapat dikatakan tidak membantu keadaan. Oleh karena itu, penyampaian berita bencana ini harus didasarkan pada etika serta nurani jurnalis tersebut agar pemberitaan pada media televisi tidak berlebihan, namun dapat sesuai fakta yang ada dan mampu menarik simpati khalayak yang menyaksikannya (Riski, Kiswandono, & Rozaq, 2011 dalam Sukmono & Junaedi, 2018). Paling tidak ada 4 prinsip mengenai peliputan serta penulisan berita bencana yang harus diterapkan media (Nazaruddin, 2007, dalam Syarah, dkk, 2020). Prinsip tersebut yaitu akurasi, humanis (terkhusus pada prinsip suara korban), komitmen menuju rehabilitasi, serta kontrol dan advokasi. Prinsip ini dapat menjadi tolak ukur untuk menilai sejauh mana media memiliki kepedulian dalam meliput peristiwa bencana. Keempat prinsip ini menjadi penting untuk dilakukan karena publik tentu akan menggantungkan pengetahuan informasinya kepada media massa.
P3SPS BAB XXIV Pasal 34 mengenai peliputan bencana alam menyatakan bahwa ada beberapa ketentuan bagi lembaga penyiaran dalam meliput dan atau menyiarkan program yang melibatkan pihak-pihak yang terkena musibah. Pertama, harus dapat mempertimbangkan proses pemulihan korban serta keluarganya ketika akan melakukan peliputan subjek yang tertimpa musibah. Kedua, tidak menambah penderitaan ataupun trauma orang dan atau keluarga yang berada pada kondisi gawat darurat, korban kecelakaan, korban kejahatan, atau orang yang sedang berduka dengan cara memaksa, menekan, dan mengintimidasi korban dan atau keluarganya untuk diwawancarai dan atau diambil gambarnya dan menyiarkan gambar korban dan atau orang yang sedang dalam kondisi menderita hanya dalam konteks yang dapat mendukung tayangan (Sukmono & Junaedi, 2018).
Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, dilema peliputan bencana dapat mempengaruhi kualitas jurnalisme. Di Indonesia, kualitas jurnalisme terutama dalam konteks jurnalisme bencana, masih perlu ditingkatkan dari sisi profesionalisme dan etika. Salah satu yang dapat dilakukan adalah menggunakan konsep jurnalisme optimis sebagai arus utama dalam jurnalisme bencana (Sukmono & Junaedi, 2018). Jurnalisme optimis merupakan praktik jurnalisme dalam bencana yang mengedepankan edukasi mitigasi bencana kepada audiens. Memahami bahwa setiap orang yang ada di lokasi bencana pada dasarnya merupakan orang yang mengalami kelelahan, kemarahan, dan trauma. Situasi seperti ini menuntut aktivitas wawancara terhadap korban bencana dengan penuh rasa hormat (Panuju, 2018). Penghormatan pada korban bencana mengindikasikan bahwa wartawan bukan sekadar hanya untuk meliput dan mendapatkan bahan berita, wartawan juga berbagi harapan dengan korban bencana, baik saat meliput maupun memberitakan hasil liputannya (Panuju, 2018).
Dalam jurnalisme optimis, jurnalis tidak mengeksploitasi penderitaan korban bencana, mengedepankan sensitivitas pada penderitaan yang dirasakan para korban bencana, informasi mitigasi bencana yang diperhatikan dengan baik, fungsi edukasi media dijadikan aspek utama, mitos dipahami sebagai sebuah kearifan lokal, dan optimisme pada penyintas menjadi perspektif yang utama (Sukmono & Junaedi, 2018). Paradigma jurnalisme optimis ini ditempatkan pada tiga fase jurnalisme bencana. Pertama, yaitu fase prabencana, di mana jurnalis yang terjun ke lokasi bencana bertanggung jawab memberikan informasi terkini yang akurat kepada masyarakat di sekitar lokasi bencana yang memiliki potensi terdampak bencana. Kedua, yaitu fase bencana, divmana jurnalis harus mengutamakan empati pada korban bencana. Peliputan bencana juga perlu menampilkan karya jurnalistik yang dapat memberikan harapan lepada masyarakat dan mengajak mereka belajar dari bencana. Ketiga, fase pascabencana, di mana jurnalis perlu mengabarkan tentang rekonstruksi bencana agar sesuai dengan peruntukannya (Arif, 2011, dalam Sukmono & Junaedi, 2018).
Lebih lanjut, pada penerapan jurnalisme bencana para jurnalis sebaiknya juga mengembangkan kemampuan tertentu. Hal ini agar memudahkan mereka dalam meminimalisir dilema ketika peliputan bencana. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, salah satu kemampuan yang berkaitan dengan jurnalisme bencana adalah empati. Empati dalam jurnalisme dapat dijelaskan melalui konsep jurnalisme empati (empathy journalism). Ashadi Siregar (2010, dalam Winarno, 2020) memaparkan bahwa jurnalisme empati ini diharapkan dapat menggambarkan empati sebagai “to see with eyes of another, to hear with the ears of another and to feel with heart of another”. Pada pemberitaan dengan jurnalisme empati akan terdapat unsur belas kasihan di dalamnya. Tugas jurnalis bencana adalah disini selain merasakan mereka juga akan sekaligus mengajak para pembaca atau masyarakat untuk bersama-sama merasakan apa yang dirasakan oleh korban dalam sebuah pemberitaan bencana. Siregar kemudian menyebutkan bahwa pada jurnalisme empati ini ada upaya untuk mengajak wartawan untuk selalu mencurigai kekuasaan yang melatari relasi sosial dalam setiap situasi sosial. Dalam konteks jurnalistik, maka “kecurigaan” ditujukan pada “korupnya kekuasaan dalam interaksi sosial yang akan membawa korban manusia.” (Haryanto, 2016). Bagian lain yang tidak terpisahkan dari jurnalisme empati adalah metode dalam mengeksplorasi kenyataan. Siregar menganjurkan bahwa pada saat wartawan mengeksplorasi kenyataan, dan ada seorang korban yang dijadikan subjek berita, maka sudah sepantasnya wartawan berupaya mendapatkan gambaran tentang kenyataan korban dilakukan dengan menggunakan metode partisipatoris. Dengan metode ini, seorang jurnalis berusaha untuk memasuki kehidupan subjek dengan sikap etis agar tidak melakukan penetrasi yang sampai mengganggu kehidupan subjek (Haryanto, 2016).
Untuk itu Siregar mengajukan pertanyaan “manakala korban ditetapkan sebagai subjek berita, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mendapatkan gambaran tentang kenyataan korban?” Atau jika sikap ini ditarik dalam persoalan etika, maka jurnalis perlu untuk bisa menjawab pertanyaan ini: “Pada saat menjadikannya [subjek] sebagai informasi, jurnalis tetap berada dalam lingkup pertanyaan etis, apakah merugikan, dan apa kemanfaatannya bagi subjek?” Dengan begini, jurnalisme empati membawa konsekuensi dalam framing (membingkai) suatu kenyataan sosial, bahwa di dalam setiap kenyataan selamanya berlangsung interaksi antar manusia, dan dalam setiap interaksi secara potensial dapat ditemukan korban (Haryanto, 2016).
Liputan yang tidak disertai empati terhadap kondisi psikologis korban tersebut menandakan bahwa media massa hanya semata-mata menjadikan bencana tak ubahnya sebagai komoditas belaka atau komodifikasi (Pribadi, 2018). Sebagai contoh, Gaya pemberitaan bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala melalui www.serambinews.com dan www.suara.com yang dramatis dan penuh kepedihan menunjukkan pergeseran sikap empati dari pihak jurnalis (Pribadi, 2018). Oleh karena itu, dalam praktik jurnalisme bencana, bukan hanya aspek kebenaran dalam berita dan sajian data namun pilihan bahasa maupun gambar juga harus sangat diperhatikan. Sebab penampilan bahasa maupun gambar berdampak secara psikologis bagi korban ataupun menimbukan kegelisahan kepada masyarakat (Pribadi, 2018). Empati kepada korban bencana juga diharapkan mampu membangun optimisme hidup korban bencana (Annapisa, 2018).
Dalam peliputan berita, ada banyak dilema yang dihadapi oleh para jurnalis, terutama saat berada di situasi bencana. Jurnalis dituntut untuk bersikap profesional dengan menayangkan berita yang aktual sekaligus mengedepankan nurani. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan dan diterapkan oleh para jurnalis, mengingat kondisi fisik dan psikis penyintas bencana setelah mengalami kejadian traumatis tersebut. Beberapa cara di antaranya adalah dengan menggunakan paradigma jurnalisme optimis ketika meliput bencana dan mengembangkan kemampuan empati. Dengan begitu, jurnalis dapat menyajikan berita berkualitas baik yang sesuai fakta untuk masyarakat dan juga dapat membantu membangkitkan harapan penyintas bencana.
Annapisa, M. (2018). Peran Media Cetak Lokal Dalam Komunikasi Bencana Sebagai Pendukung Manajemen Bencana. Buletin Pembangunan Berkelanjutan, 2(1), 102-115.
BNPB. Definisi Bencana. https://bnpb.go.id/definisi-bencana
Hadi, H., Agustina, S., & Subhani, A. (2019). Penguatan kesiapsiagaan stakeholder dalam pengurangan risiko bencana gempabumi. Jurnal Geodika, 3(1), 30-40.
Hamdan, M., Abbas, N., & Astrid, A. F. (2019). Performa jurnalis televisi pada implementasi jurnalisme bencana di Makasar. Jurnal Public Relations Indonesia, 3(2).
Maizar, E., Gayatri, D., & Nuraini, T., (2021). Knowledge of mitigation and attitude of preparedness of vocational health programs students in Jakarta in facing earthquake disasters. Enfermería Clínica, 31(2), 419-423.
Nugroho, B., & Samsuri. (2013). Pers berkualitas, masyarakat cerdas. Dewanpers.
Haryanto, I. (2019). Performa media, jurnalisme empati, dan jurnalisme bencana: kinerja televisi Indonesia dalam peliputan bencana (kasus liputan tv one terhadap hilangnya Air Asia qz 8501). Jurnal Ilmu Komunikasi : ULTIMACOMM, 8(1).
Proulx, K., & Aboud, F., (2019). Disaster risk reduction in early childhood education: effects on preschool quality and child outcomes. International Journal of Educational Development, 66, 1-7.
Rahmat, H. K., & Alawiyah, D., (2020). Konseling traumatik: sebuah strategi guna mereduksi dampak psikologis korban bencana alam. Jurnal MIMBAR: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani, 6(1), 34 – 44.
Rosyida, F., & Adi, K. R., (2017). Studi eksplorasi pengetahuan dan sikap terhadapkesiapsiagaan bencana banjir di SD Pilanggede Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. Jurnal Teori Dan Praksis Pembelajaran Ips, 2(1), 1-5
Sanusi, H. (2018). jurnalisme dan bencana (Refleksi peran jurnalis dalam liputan bencana gempa, tsunami dan likuifaksi Palu-Donggala). Jurnal Jurnalisa: Jurnal Jurusan Jurnalistik, 4(2).
Sukmono, F. G., & Junaedi, F. (2018). Menggagas jurnalisme optimis dalam pemberitaan tentang bencana. Jurnal Ilmu Komunikasi, 15(1), 107-120.
Syarah, M. M. (2020). Jurnalistik Bencana Pada Pemberitaan Covid-19 di Republika Online. Jurnal Public Relations (J-PR), 1(1), 56-63.
Panuju, (2018). Etika jurnalistik dan jurnalisme bencana pada pemberitaan gunung agung di portal berita Balispot.co. Jurnal Ilmu Komunikasi, 15(2), 219-232.
Pribadi, F. (2018). Komodifikasi Derita Korban Bencana. The Journal of Society and Media, 2(2), 146-153.
Widjanarko, M., & Minnafiah, U., (2018). Pengaruh pendidikan bencana pada perilaku kesiapsiagaan siswa. Jurnal Ecopsy, 5(1), 1-7.
Winarno, S. (2020). Narasi Banjir di Media. Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi Akademik.












.jpg)





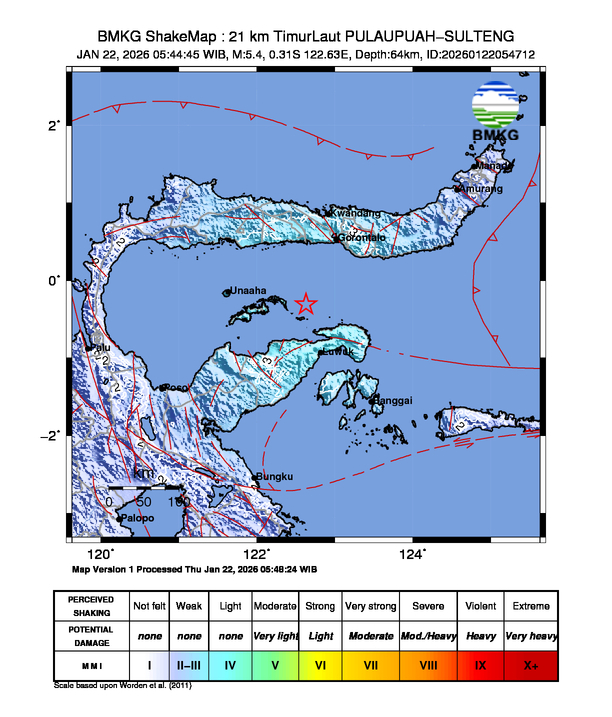
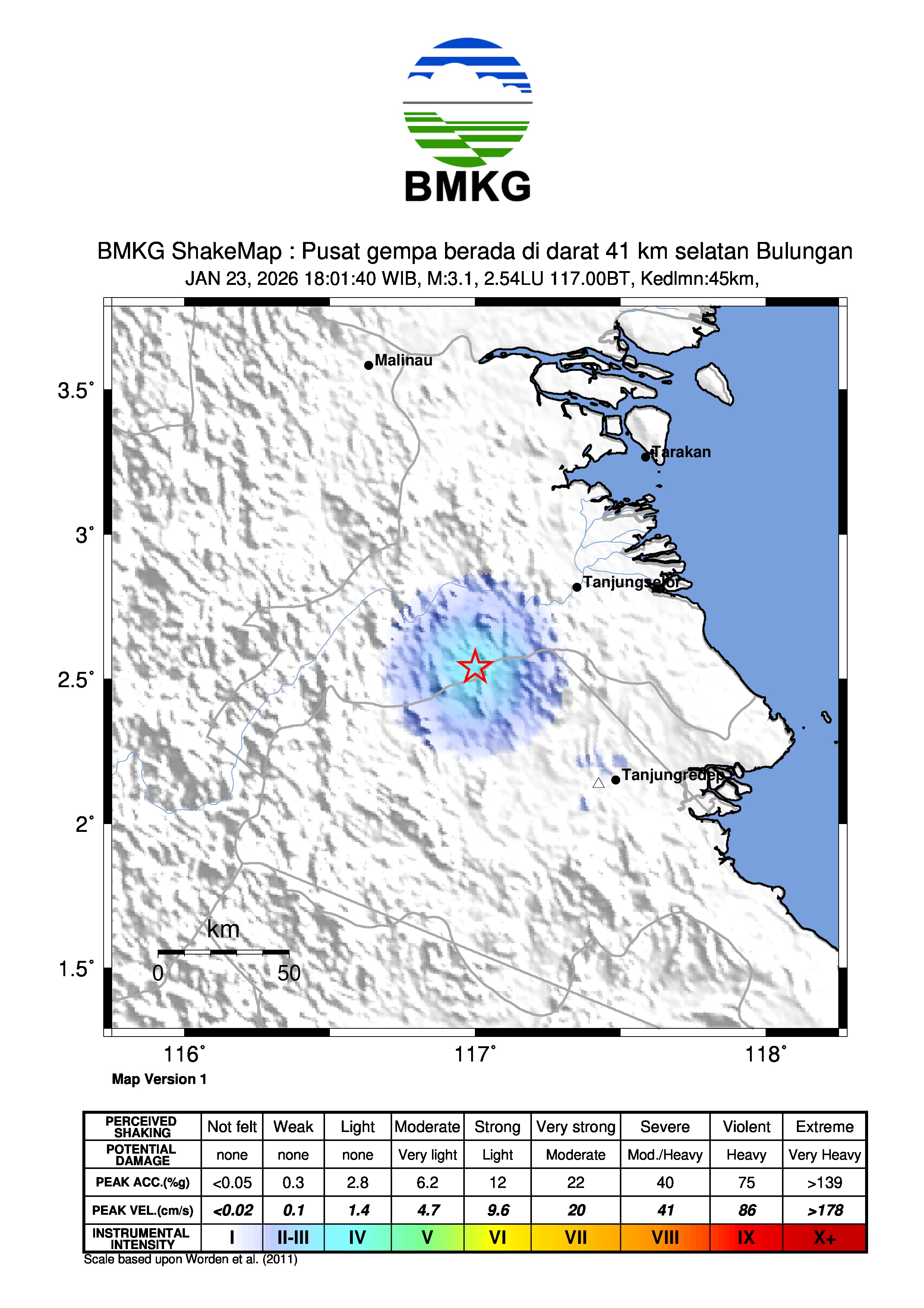






No comments:
Post a Comment