Penulis: Nofri Hamdi,S.H.I (Mahasiswa Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat)
Era Society 5.0 yang ditandai dengan integrasi teknologi canggih, kecerdasan buatan, dan hiperkonektivitas telah menjadikan internet serta perangkat Android sebagai “teman sehari-hari” bagi anak-anak dan remaja. Di satu sisi, teknologi ini membuka akses ilmu pengetahuan yang tak terbatas. Di sisi lain, dampak negatifnya sangat nyata: paparan konten pornografi, radikalisme berbasis agama yang salah paham, hoaks keagamaan, game dan media sosial yang membuat kecanduan, hingga hilangnya adab dalam pergaulan daring. Di tengah gempuran ini, guru Pendidikan Agama Islam (PAI) bukan lagi sekadar pengajar fiqih dan akidah, melainkan benteng terakhir akhlak dan iman generasi muda.
Pertama, guru PAI harus bertransformasi menjadi “filter hidup” bagi peserta didik. Di era di mana algoritma YouTube dan TikTok lebih berpengaruh daripada nasihat orang tua, guru PAI wajib memiliki literasi digital yang mumpuni. Ia tidak boleh alergi teknologi, tetapi justru menguasainya untuk kemudian mengarahkan anak-anak pada konten-konten yang membangun iman dan akhlak. Membuat channel dakwah yang menarik, memanfaatkan Instagram atau TikTok untuk menyampaikan kisah-kisah nabi dengan visual kekinian, atau mengadakan kelas daring tentang “Etika Bermedsos Menurut Al-Qur’an dan Hadits” adalah beberapa langkah konkret yang bisa dilakukan.
Kedua, guru PAI memiliki tanggung jawab membangun ketahanan ruhani (spiritual resilience) siswa. Internet dan Android sering kali menawarkan kepuasan instan yang bertentangan dengan konsep sabar dan tawakal dalam Islam.Konten-konten hedonis dan materialistis membuat anak-anak lupa bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari like dan follower, tetapi dari ridha Allah. Di sinilah peran guru PAI untuk terus-menerus mengingatkan konsep qana’ah, zuhud di dunia, dan pentingnya menjaga hati dari penyakit ain, riya, dan takabbur yang kini muncul dalam bentuk flexing dan pamer harta di media sosial.
Ketiga, guru PAI harus menjadi pendamping kritis, bukan hanya pengajar normatif. Banyak siswa yang diam-diam terpapar konten radikal atau paham keagamaan yang keliru karena merasa “lebih pintar” setelah membaca artikel-artikel di internet. Guru PAI perlu membiasakan diskusi kritis di kelas: mengajarkan cara memverifikasi sumber keislaman, mengenali ciri-ciri konten provokatif, dan membandingkan informasi yang beredar dengan Al-Qur’an dan Sunnah yang shahih. Pendekatan ini jauh lebih efektif daripada hanya melarang anak memakai gadget, karena larangan tanpa pemahaman hanya akan memicu rasa penasaran yang lebih besar.
Keempat, sekolah harus menjadikan guru PAI sebagai koordinator program literasi digital berbasis nilai Islam. Kerjasama dengan orang tua melalui parenting class bertema “Mendampingi Anak di Era Android Tanpa Kehilangan Akhlak” dan pembuatan komunitas “Muslim Millennial Beretika Digital” dapat memperluas dampak guru PAI di luar jam pelajaran.
Pada akhirnya, di era 5.0 ini, guru PAI bukan lagi sekadar “pengajar agama” yang datang membawa buku LKS dan Al-Qur’an, tetapi seorang pendidik sejati yang mampu berdakwah di tengah badai informasi. Ia adalah penjaga terakhir ketika filter orang tua mulai lemah dan filter negara belum cukup kuat. Jika guru PAI gagal beradaptasi dan tetap bertahan dengan metode konvensional, maka kita akan kehilangan satu generasi yang shalatnya rajin tetapi hatinya kosong dari akhlak mulia.
Maka, sudah saatnya kita menempatkan guru PAI di garda terdepan perang melawan dampak negatif internet dan Android. Bukan dengan menolak teknologi, tetapi dengan mengislamkan teknologi itu sendiri. Karena di era 5.0, pemenangnya bukan yang paling canggih gadgetnya, tetapi yang paling kuat iman dan akhlaknya di tengah kecanggihan itu. Wallahu a’lam.












.jpg)





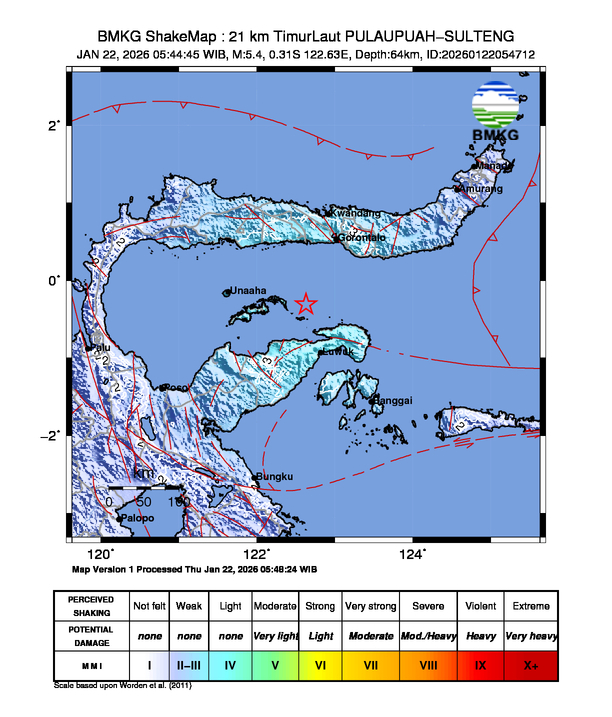
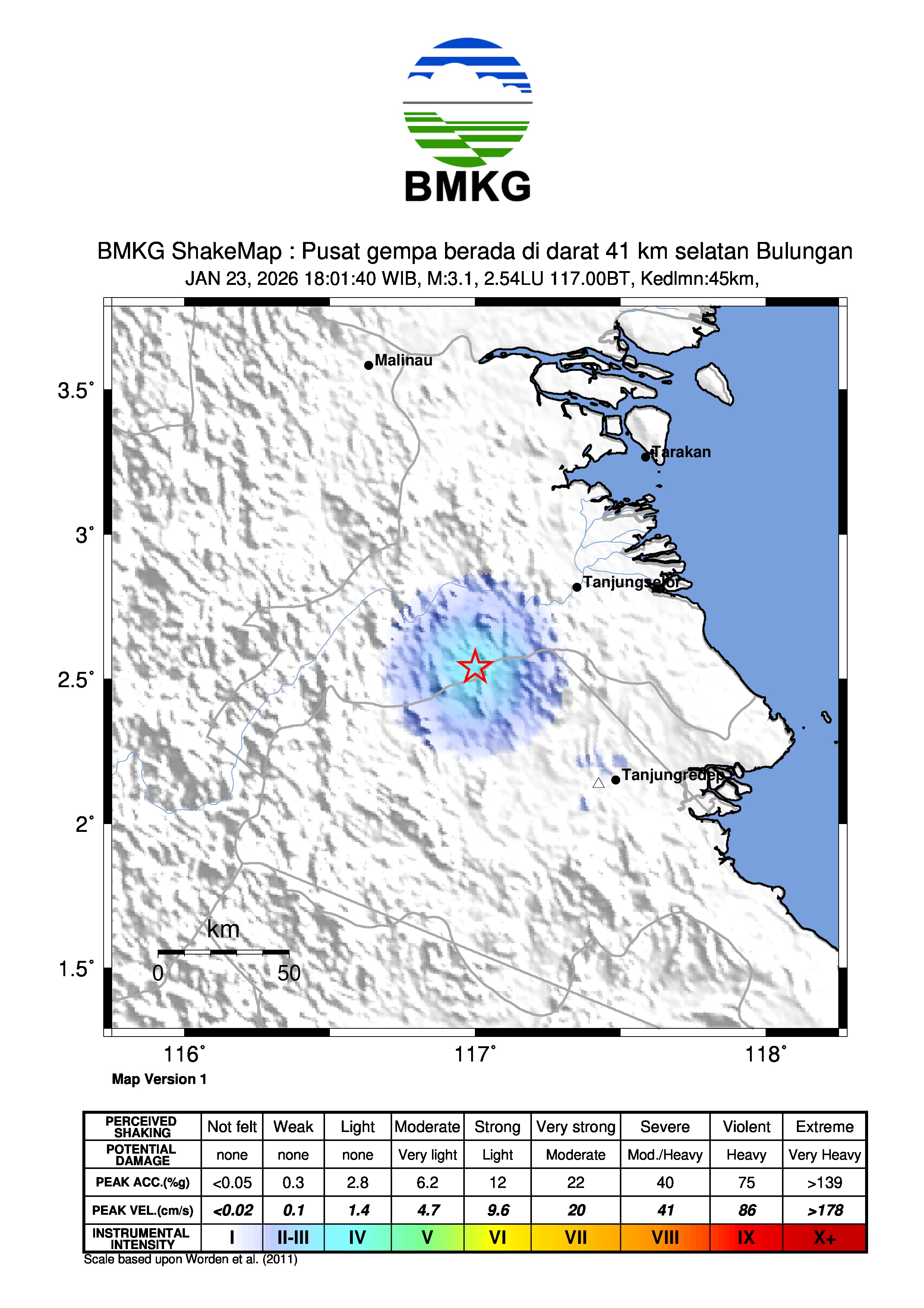






No comments:
Post a Comment