Oleh: Ari Yuliasril
Di lereng tenang Gunung Singgalang, di antara kabut pagi dan desir angin sejuk, berdirilah sebuah nagari yang memiliki dua wajah, wajah ilmu dan wajah rasa. Nama nagari itu adalah Koto Gadang, salah satu permata di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, kampung yang menumbuhkan intelektualitas sekaligus menjaga kehangatan tradisi dapur Minangkabau.
Di sini, suara palu perak berdenting dari bengkel kecil di sudut jalan, aroma cabai hijau menyengat dari dapur rumah gadang, dan kisah para cendekiawan masih bergaung di udara.
Kampung Para Intelektual
Sejarah mencatat, Koto Gadang adalah tempat lahirnya para pemikir besar bangsa. Sutan Syahrir, perdana menteri pertama Republik Indonesia, tumbuh dari rahim nagari ini, dari keluarga yang menghargai pendidikan dan kebebasan berpikir.
Prof. Emil Salim, ekonom terkemuka Indonesia, juga merupakan keturunan Koto Gadang.
Kedua nama ini hanyalah dua dari sekian banyak anak nagari yang berkiprah di panggung nasional, membawa semangat rasional dan kemanusiaan yang mereka warisi dari nagari kecil di bawah kaki Singgalang ini.
Pada masa kolonial, Koto Gadang menjadi salah satu pusat pendidikan modern di Sumatera Barat. Sekolah-sekolah Belanda berdiri di sekitarnya, dan banyak pemuda Minang berangkat dari nagari ini untuk menuntut ilmu ke Padang, Batavia, bahkan ke Belanda.
Namun, modernitas tidak membuat mereka tercerabut dari akar adat. Di sela diskusi dan pelajaran, mereka tetap pulang ke rumah gadang, bersila di surau, dan makan bajamba bersama keluarga. Di sinilah letak keistimewaan Koto Gadang, intelektualitas tumbuh di atas fondasi adat dan tradisi.
Dari Lado Hijau hingga Taruok
Selain dalam ilmu, Koto Gadang juga terkenal karena warisan kulinernya yang khas.
Cita rasanya tajam, namun tetap elegan, seperti cara bicara orang-orangnya yang tenang tapi bernas.
Yang paling terkenal tentu Ayam Lado Hijau Koto Gadang. Ayam kampung dimasak perlahan dengan cabai hijau, bawang, tomat, dan perasan jeruk nipis.
Hasilnya adalah perpaduan rasa pedas segar dengan sedikit asam yang menggigit, cocok dengan udara pegunungan yang sejuk.
Warna hijaunya cerah, tapi rasanya dalam, seolah mencerminkan karakter masyarakat Koto Gadang yang berani tapi berimbang.
Selain ayam lado hijau, ada juga Gulai Itiak Lado Ijau, olahan bebek dengan bumbu serupa namun lebih kuat aromanya. Masakan ini biasa hadir dalam alek nagari, pesta adat besar di mana seluruh warga berkumpul. Daging bebeknya empuk, kuahnya kental dan berlemak, pedasnya tidak membakar lidah, tapi justru menenangkan hati di udara dingin perbukitan.
Sebagai penutup manis, ada Taruok, kue tart susu khas Koto Gadang yang lembut dan halus.
Kue ini menjadi simbol pertemuan antara kuliner Minangkabau dan pengaruh kolonial Belanda. Susu, tepung, dan mentega berpadu dengan sentuhan rasa lokal yang manis dan penuh kelembutan.
Melalui Taruok, kita bisa melihat bagaimana dapur Koto Gadang mampu berdialog dengan perubahan tanpa kehilangan jati diri. Ia membuktikan bahwa warisan tidak harus beku, ia bisa beradaptasi sama seperti masyarakatnya yang cerdas sekaligus berakar
Kerajinan Perak
Namun keindahan Koto Gadang tak hanya berasal dari masakannya.
Nagari ini juga terkenal dengan kerajinan peraknya, seni yang sudah turun-temurun diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Di bengkel kecil, para perajin duduk berjam-jam menunduk, mengukir logam mulia menjadi miniatur rumah gadang, perhiasan, atau peralatan ibadah. Setiap detail dikerjakan dengan tangan, tanpa mesin besar, hanya mengandalkan kesabaran dan ketelitian mata.
Kegiatan ini, dalam banyak hal, tidak jauh berbeda dengan dunia dapur. Seorang perajin perak dan seorang juru masak di Koto Gadang sama-sama bekerja dengan kesunyian, presisi, dan cinta pada detail. Mereka mengolah bahan mentah menjadi karya yang bermakna, satu dalam bentuk logam berkilau, satu lagi dalam bentuk rasa yang menggugah selera.
Dari bengkel perak hingga tungku dapur, Koto Gadang mengajarkan nilai yang sama, bahwa keindahan lahir dari ketekunan dan kesabaran.
Intelektualitas yang Bersahaja
Di tengah arus modernisasi, Koto Gadang tetap mempertahankan identitasnya. Rumah gadang masih berdiri megah di antara rumah bergaya kolonial, surau masih menjadi tempat anak-anak belajar mengaji, dan pasar nagari tetap ramai di pagi hari.
Masyarakatnya terbuka terhadap dunia luar, tetapi tetap menakar perubahan dengan kebijaksanaan lokal. Mereka percaya bahwa kemajuan tidak berarti meninggalkan akar, dan pengetahuan sejati harus disertai dengan moral dan rasa.
“Hidup itu seperti lado hijau,” kata Mak Eri, salah satu ibu rumah tangga yang ditemui di dapurnya. “Pedas, tapi menyehatkan. Jangan takut pada panasnya, karena di sanalah rasa hidup.”
Ilmu dan Rasa yang Tak Pernah Padam
Koto Gadang bukan sekadar tempat lahir para tokoh besar, bukan pula sekadar kampung wisata perak atau kuliner. Ia adalah ruang perjumpaan antara intelektualitas dan tradisi, antara akal dan rasa, antara modernitas dan adat.
Setiap dentingan palu perak, setiap uap panas dari wajan lado hijau, dan setiap kata bijak yang terucap di surau, semuanya menjadi bagian dari narasi panjang tentang bagaimana sebuah nagari kecil bisa melahirkan gagasan besar tanpa kehilangan jati dirinya.
Koto Gadang membuktikan bahwa kemajuan dan tradisi bukanlah dua kutub yang saling meniadakan.
Keduanya bisa hidup berdampingan, seperti sambal lado hijau yang pedas tapi tetap menenangkan, tajam tapi penuh keseimbangan.






























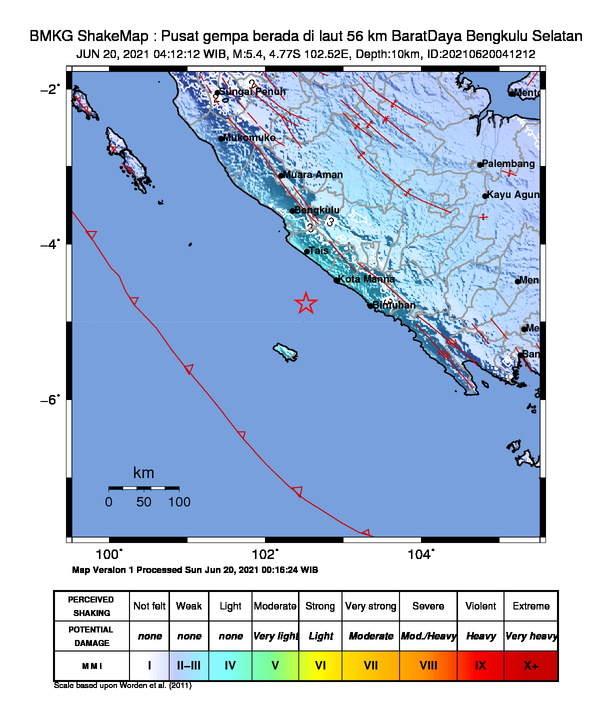








0 Comments